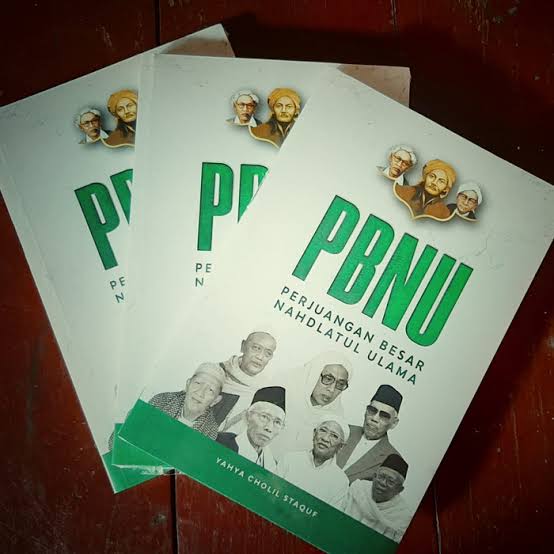Jika kita mengingat-ingat dan ziarah ke 36 tahunan yang lalu, KH. Achmad Siddiq pernah menyinggung satu persoalan penting untuk kehidupan mendatang. Perdamaian, kerukunan umat manusia, adalah poin pentingnya. Bahwa gerak perbedaan menuju pada persatuan umat manusia hanya akan terjadi jika kita berpegang teguh pada ukhuwah basyariah. Hal inilah yang kemudian oleh Gus Yahya disebut dengan istilah kehidupan ini berada pada perahu yang sama; Nusantara (Yahya Cholil Staquf, 2020).
Artinya bola salju globalisasi pasti akan segera bergulir dan turut menghiasi kehidupan kita. Jika pada awal perubahan globalisasi dipengaruhi oleh sistem perdagangan, pertukaran budaya, imigran dan lain sebagainya. Namun hari ini globalisasi yang oleh Kofi Annan disebut sebagai gravitasi, tentu adalah bagian dari sunnatullah yang bisa bergerak lebih cepat melalui perkembangan teknologi dan terbukanya cadar atau batas negara satu dengan yang lain, bahkan sampai pada titik terdekat manusia yaitu personalitasnya.
Tentu seperti sekeping uang dengan dua sisi yang selalu beriringan. Ada peran positif dan ada peran negatif, hal ini sudah menjadi satu keniscayaan. Globalisasi adalah perubahan dan respon terhadapa ragam budaya yang – seperti ada di depan mata. Melalui teknologi, internet, dan jaringan-jaringan pendukung seperti tiada batas antara kita dan dunia luar. Sehingga wajar jika seseorang di Malang bisa bertukar tawa dengan yang di Madura, Sumatera bahkan di berbagai benua di Eropa.
Ibarat sebuah pertandingan, globalisasi juga menyediakan satu potensi agenda perpecahan, seperti bertukar hoaks, saling mencaci melalui gawai pintarnya, bahkan bisa berkomentar sambil rebahan atau bahkan jongkok di kamar mandi. Artinya perlu adanya kuda-kuda kesadaran dan keselarasan yang harus disiapkan untuk menanggulagi perpecahan atau benturan-benturan perbedaan yang kerap kali diblow-up untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Pendidikan adalah kunci utama dari pembentukan kuda-kuda kewasapadaan tersebut.
Pendidikan pesantren, di samping menjadi pendidikan tradisional yang cukup leluasa dan luwes dalam proses nyawiji dengan kondisi sosial, adalah modal awal untuk – paling tidak menjadi wanti-wanti bagi kita semua untuk memasang kuda-kuda kewaspadaan dalam menghadapi arus global yang destruktif tentunya, perihal arus global yang memiliki manfaat bagi sesama dan semua umat jangan sesekali ditinggalkan dan lalu dipukul rata. Pesantren melalui Wali Songo, para kyai-kyai terdahulu seperti Mbah Mutamakkin, Mbah Sholeh Darat, Mbah Ilyas, Mbah Dalhar, atau pada era kemerdekaan seperti Mbah Kyai Siddiq, Mbah Kyai Hasyim Asy’ary, Mbah Kyai Wahab Chasbullah dan lain sebagainya, yang menawarkan konsep kebersamaan, persatuan dan kerukunan umat manusia.
Artinya, pesantren memiliki peran penting dalam menyambut arus global yang tentu terus berlangsung. Sejarah mencatat bahwa pesantren Mamba’ul Ulum Surakarta yang didirikan oleh Susuhuna Agung, oleh Pakubuwana pada tahun 1906 sudah mulai menerima pengajaran pengetahuan-pengetahuan umum di luar pengetahuan agama. Sehingga kemudian diikuti oleh pesantrne-pesantren yang lain di jawa timur (Nurcholis Majid, 1997).
Dengan demikian pesantren memiliki satu kondisi kesigapan dan kewaspadaan terhadap ragam perkembangan dan kemajuan di era mendatang. Ia sebagai lembaga pendidikan mempersipkan santri agar berbekal pengetahuan baik sosial, pun spiritual. Namun sebagai lembaga sosial, pesantren adalah pusat peberdayaan masyarakat, temapat di mana masyarakat menyampaikan keluh kesahnya, dan lain sebagainya.
Pesantren menjadi satu lembaga di tengah kehidupan sosial yang mendukung dan berusaha merealisasikan cita-cita peradaban dunia yang mulia, yang juga harus diperjuangkan dalam pergaulan internasional, hal ini adalah semangat dari ukhuwah basyariah. Pendek kata pesantren sebagai lembaga sosial di satu sisi harus mengakui sebuah permasalahan lalu turut serta dalam menemukan bahkan merumuskan solusinya tanpa berat sebelah atau mendahulukan kepentingan sepihak (Yahya Cholil Staquf, 2020).
Islam mengajarkan kita untuk bersika adil, dan untuk memandang segala fenomena juga harus dengan sikap yang adil. Pada konteks ukhuwah basyariah inilah sebenarnya aspek keadilan itu menjadi satu keutuhan cara berpikir. Artinya ketika setiap orang memiliki pandangan kemanusiaan dan kedalaman rasa kemanusiaannya maka, setiap perbedaan bukan lagi menjadi permasalahan, dan setiap permasalahan tentu akan dicari jalan keluarnya bersama-sama.
Pada akhirnya adalah pesantren menjadi satu ruang tumbuh kembangnya manusia, di samping untuk mengenali dirinya sendiri (Ma’rifatun nafs) ia juga harus mengenali ragam pergumulan (Ma’rifat al-jami’ah), yang mana dari kesemua itulah nantinya menjadi pegetahuan sosial, kepekaan sosial dan–tanpa memandang sebelah mata sebuah pebedaan, justru memandang perbedaan sebagai keniscayaan dan anugerah dari Tuhan. Jika pesantren dalam nilai sosial diwakili oleh Nahdlatul Ulama (NU) maka, secara tidak langsung NU adalah bagian penting dalam menyiapkan kuda-kuda kewaspadaan menyambut globalisasi, dengan – tanpa meninggalkan tradisi sebagai kearifan lokal dan warisan budaya keberagaman dan keberagamaan yang dibangun baik jauh sebelum Wali Songo, atau di era dan pasca Wali Songo.[]