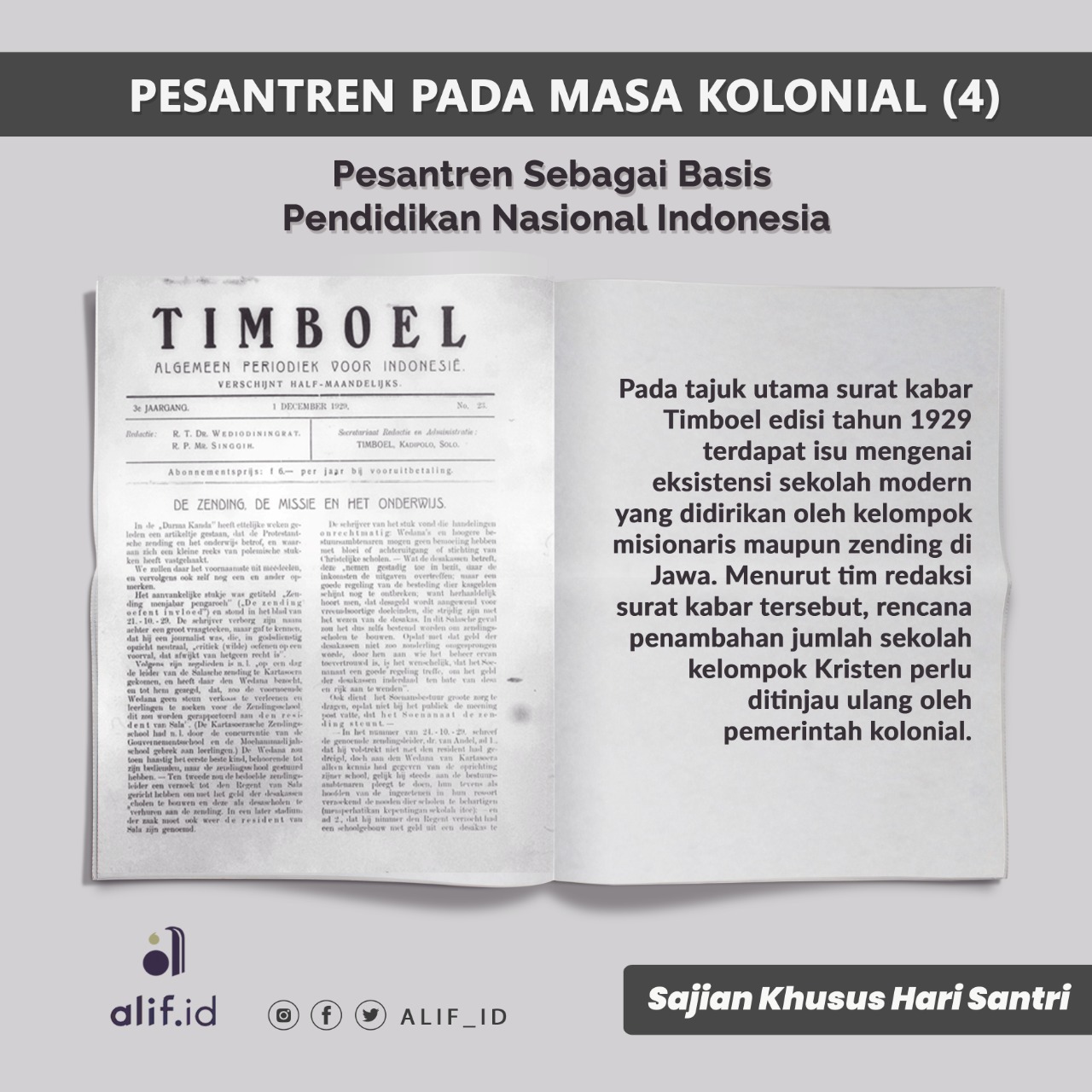Pada tajuk utama surat kabar Timboel edisi tahun 1929 terdapat isu mengenai eksistensi sekolah modern yang didirikan oleh kelompok misionaris maupun zending di Jawa. Menurut tim redaksi surat kabar tersebut, rencana penambahan jumlah sekolah kelompok Kristen perlu ditinjau ulang oleh pemerintah kolonial.
Senada dengan artikel yang dibuat oleh Haji Misbach satu dekade sebelumnya bahwa dengan terus bertambahnya jumlah sekolah Kristen di Jawa akan dilihat sebagai ancaman bagi masyarakat Jawa yang mayoritas adalah muslim. Oleh karena itu, redaksi Timboel menuntut pemerintah agar segera membatasi jumlah sekolah Kristen dan hanya mengijinkan keberadaan sekolah menengah dan lanjutan yang sudah berdiri saja.
Di dalam penjelasannya, artikel tersebut mengakui bahwa terdapat stereotype bahwa masyarakat Jawa adalah pemeluk Islam yang kurang taat dalam menjalankan perintah agama. Bahkan mereka juga menambahkan banyak peneliti juga melihat orang Jawa tersebut memiliki kelemahan iman. Akan tetapi hal tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat Jawa adalah Islam.
Redaksi mengibaratkan bahwa Islamnya orang Jawa sama seperti dengan Kristennya orang Belanda. Demikian juga karakter pemeluknya, budayanya, dan peradabannya. Maka mereka menyarankan kepada pemerintah agar mereka hanya mengijinkan pembukaan sekolah Kristen yang baru di daerah-daerah luar Jawa seperti di Minahasa, Ambon, dan lainnya dimana penduduknya mayoritas beragama Kristen.

Tajuk Utama Surat Kabar Timboel edisi 1 Desember 1929
Pernyataan redaksi surat kabar tersebut merupakan hal yang menarik bagi pembaca masa kini. Apabila dilihat dengan cermat susunan redaksi maupun orientasi surat kabar Timboel sendiri, tidak ada indikasi bahwa terdapat anasir-anasir kelompok santri di dalamnya. Semua tim redaksi Timboel adalah kelompok Jawa yang tergolong nasionalis abangan. Bahkan pemimpin redaksinya, Dr. Radjiman Wedyodiningrat justru dikenal dalam berbagai tulisan-tulisan para ahli Indonesia sebagai sosok yang antagonis terhadap Islam.
Seperti dalam tulisan Takashi Shiraishi, Akira Nagazumi, M.C. Ricklefs, dan lainnya, Radjiman Wedyodiningrat adalah seorang pelaku Kejawen maupun pemimpin teosofi yang teguh. Sebagai pemimpin Boedi Oetomo, ia pernah menolak menjadikan isu-isu terkait perkembangan agama Islam dalam program kerja organisasi tersebut.
Rupanya para nasionalis yang selama ini digambarkan sering berlawanan dengan kelompok santri dalam berbagai historiografi sesungguhnya memiliki banyak kedekatan. Sebagaimana dalam tampak dalam isu pendidikan dalam surat kabar Timboel tadi, para nasionalis seperti Dr. Soetomo dan Ki Hadjar Dewantara melihat bahwa pesantren, bukan sekolah modern seperti yang diintrodusir oleh Belanda maupun kelompok Kristen, adalah basis bagi pendidikan nasional Indonesia.
Dalam Nationaal Onderwijs Congres yang diadakan pada tahun 1935, Dr. Soetomo sebagai tokoh yang mempelopori jaman bergerak dengan mendirikan Boedi Oetomo mengemukakan bahwa jiwa dan semangat Barat yang inheren dalam sekolah modern merupakan hal yang mengkhawatirkan bagi perkembangan manusia Indonesia. Keluhuran budi dan kesucian jiwa manusia Indonesia hanya bisa dididik dalam model pendidikan yang telah berurat akar dalam masyarakat Indonesia yakni pesantren. Menurut Soetomo:
“Maksud saya dengan sistem pondok pesantren adala supaya pengajaran dan kehidupan guru dengan muridnya menjadi persatuan yang harmonis, menjadi een harmonisch geheel. Ini perlu bagi kita, karena sebahagian besar pemuda-pemuda kita yang belajar, hidup di luar lingkungan rumah tangga, artinya di luar pengawasan orang tua, sehingga buat kita perlu satu pondok, dimana anak-anak kita selain mendapat makan dan minum, bahkan terutama sekali mendapat pendidikan kecerdasan jiwanya, yaitu dengan bercermin paaa kelakuan dan kehidupan sang guru atau kyai.”
Ki Hadjar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional sekaligus pendiri Sekolah Taman Siswa juga mendukung pendapat Dr. Soetomo. Ki Hadjar menyatakan bahwa sistem pondok inilah yang merupakan sistem pendidikan nasional yang sejati. Masyarakat Indonesia sejak masa lampau hingga masa kini telah memiliki rumah pengajaran sekaligus pendidikan yakni pondok pesantren. Bahkan di masa yang disebut masa Hindu-Buddha, institusi ini telah eksis dengan nama pawiyatan atau asrama. Karakteristik utamanya adalah komplek kediaman sang kyai atau guru selain juga menyediakan akomodasi bagi para santri atau cantrik dibuat sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Ki Hadjar menyebutkan bahwa:
“Pada jaman sekarang, pondok itu hanya terpakai untuk pengajaran agama saja, tetapi pada jaman dahulu rumah guru itu tidak cuma dipakai sebagai rumah pengajaran saja melainkan juga menjadi rumah pengajaran rupa-rupa ilmu yakni agama, ilmu alam, falakiah, ilmu hukum, bahasa, filsafat, seni, keprajuritan, dan lain-lain pengetahuan yang dulu sudah dipelajari oleh kaum terpelajar atau para sarjana.”
Apa yang dikemukakan oleh Dr. Soetomo maupun Ki Hadjar tersebut mendapat tentangan keras dari seorang intelektual muda, Sutan Takdir Alisjahbana. Menurutnya sistem pondok pesantren merupakan sistem pendidikan yang harus ditinggalkan. Masyarakat Indonesia harus segera menerima pendidikan modern untuk mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain. Lebih lanjut Sutan Takdir Alisjahbana berpendapat bahwa pesantren hanya mengajarkan kekolotan dan kepatuhan buta murid terhadap kyai atau gurunya. Para murid atau santri tidak bisa berpikir kritis karena kebiasaan tersebut. Bahkan ia menyebutkan bahwa tanpa adanya pendidikan Barat tidak mungkin terdapat tokoh-tokoh seperti Dr. Soetomo dan Ki Hadjar.
Dengan cepat Dr. Soetomo menjawab tudingan tersebut dengan memberikan berbagai contoh termasuk pengalamannya sendiri. Menurutnya orang-orang seperti Ki Hadjar, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Ir. Sukarno, dan para tokoh nasionalis lainnya memang pernah mengenyam pendidikan Barat. Akan tetapi Dr. Sutomo menyebutkan bahwa para tokoh tersebut merupakan luaran dari sistem pendidikan Barat yang tidak diinginkan.
Maksudnya adalah kesadaran kritis para tokoh tersebut tidak berasal dari pendidikan Barat melainkan dari apa yang mereka pernah alami dan rasakan dalam kehidupan pribadinya, dan bukan berasal dari pelajaran yang didapat dari sekolah. Pendidikan Barat hanya berniat untuk mengajarkan manusia untuk menjadi individualis dan materialis. Para tokoh tersebut hanyalah beberapa gelintir saja dari sekian banyak lulusan pendidikan Barat.
Dr. Soetomo sendiri menuliskan pengalamannya dalam dunia pendidikan pesantren sebelum ia mendapatkan pendidikan Barat. Menurutnya kehidupan masa kecilnya di dalam pesantren milik kakeknya adalah suatu hal yang sungguh-sungguh mempengaruhi jiwanya sebagai manusia Indonesia. Hal tersebut bukanlah pelajaran mengaji atau kegiatan di siang hari, melainkan bagaimana ia diajak ke luar rumah tiap malam untuk kemudian melakukan sembahyang sekaligus menghitung-hitung bacaan dengan tasbih (berdzikir). Pada awalnya, Soetomo kecil tidak mengetahui apa makna dari kegiatan tersebut. Hanya yang pasti dari kegiatan rutin tersebut ia mengaku mendapat rasa nyaman, tenteran, aman dan sejuk di hatinya.

Otobiografi Dr. Soetomo bertajuk Kenang-Kenangan
Hal serupa juga dialami Soetomo ketika ia melanjutkan sekolah di Bangil. Pada saat itu, Soetomo tinggal bersama keluarga pamannya yang bernama Arjodipuro. Menurut Soetomo, pamannya ini adalah seorang keturunan Pangeran Diponegoro yang berhasil menyelamatkan diri karena sejak kecil dititipkan di dalam suatu pesantren. Tidak heran kebiasaannya di pesantren terus dilakukan hingga pamannya berumah tangga. Satu kebiasaan yang mencolok seperti yang diamati oleh Soetomo adalah kebiasaan untuk keluar rumah tiap malam hari dan pergi bersembahyang. Sama seperti yang dilakukan kakek dan neneknya di pesantren.
Berkat didikan sang kakek dan pamannya itu, Soetomo berargumen bahwa model pendidikan nasional yang paling sesuai dengan masyarakat Indonesia adalah sistem pondok pesantren. Hanya dengan modal pendidikan seperti itulah bangsa Indonesia tidak hanya akan mencapai kemerdekaannya melainkan juga kemuliaannya. Seperti diungkapkannya dalam slogan Indonesia Mulia dimana kemerdekaan hanyalah satu jalan sebelum mencapai kemuliaan.
Sayangnya setelah Indonesia merdeka, justru sistem pendidikan yang menjadi sistem pendidikan nasional adalah seperti yang diusulkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana. Bukan seperti usulan Dr. Soetomo ataupun Ki Hadjar Dewantara yang ironisnya diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Sudah waktunya momentum peringatan Hari Santri juga harus menjadi refleksi bagi dunia pendidikan secara umum di Indonesia dan tidak hanya terbatas di kalangan keagamaan saja. Dengan modal besar sebagai sistem pendidikan yang telah eksis sejak berabad-abad yang lampau, sudah waktunya pesantren bisa lebih mewarnai sistem pendidikan nasional seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa Indonesia.