Muslim Praksis: Muslim Akademis yang Organisatoris
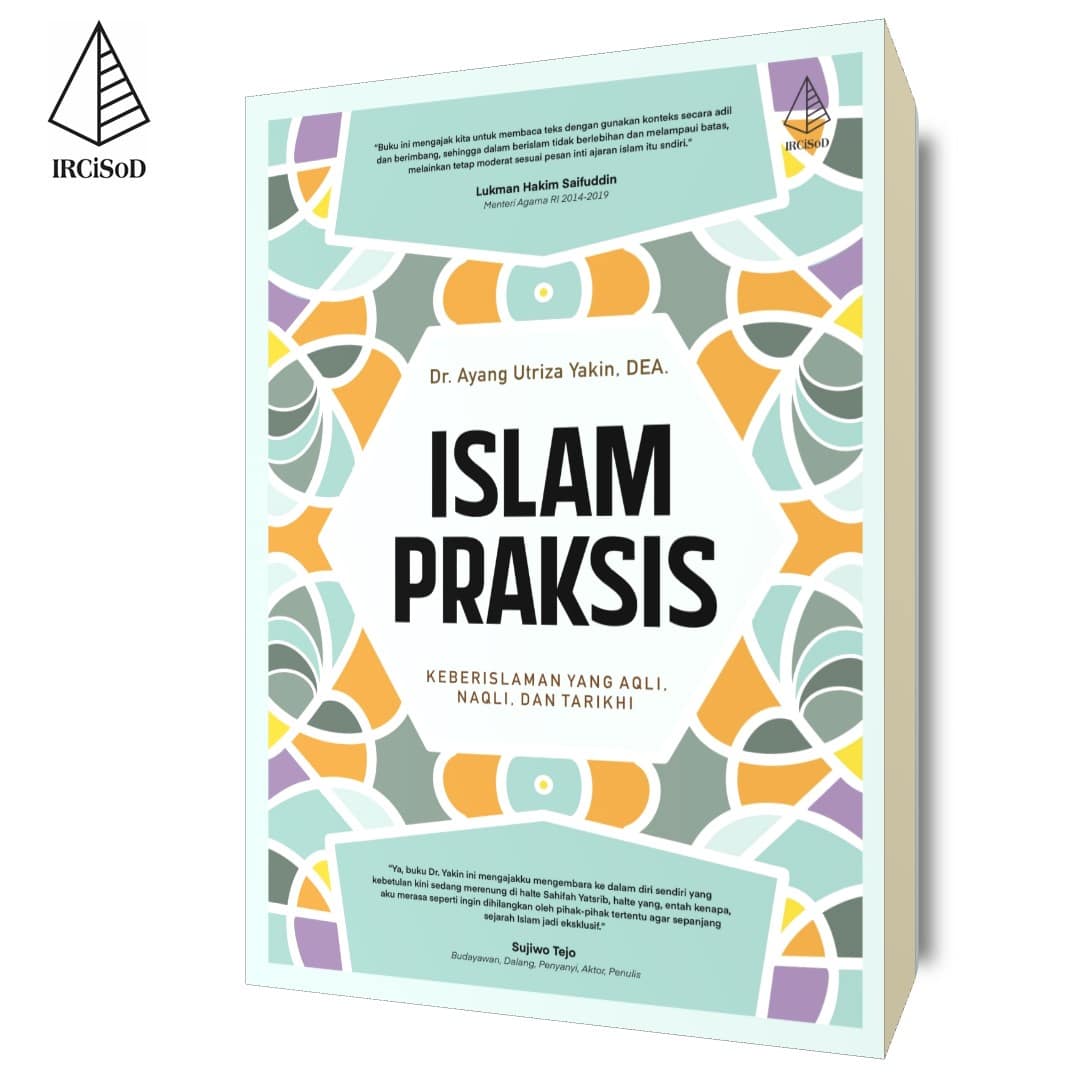
Beberapa bulan lalu, melalui medianya, seorang jurnalis lantang mengkritik pelaksanaan akbar yang mempertemukan seluruh pemuka agama di seantero dunia. Pertemuan itu, menurut pihak penyelenggara, bertujuan untuk menyatukan gagasan dalam rangka turut berperan aktif dalam mendamaikan konflik dunia dan memulihkan perekonomian.
Betapa ganjil, masalah perekonomian yang seharusnya diatasi mulai dari menumbuhkan kesadaran di akar rumput, justru mereka menjadi korban atas pertemuan akbar tersebut. Ini namanya melukai luka yang belum sembuh. Kalaupun pemulihan ekonomi bisa diperbaiki melalui diplomasi-diplomasi antar dunia, yang merasakan manisnya hanya di kalangan elit saja; terlihat manis di depan seluruh pemuka agama di dunia, dan 'manis' ekonominya.
Lantas, bagaimana nasib masyarakat yang lain? Sangat variatif. Yang tidak paham, tentu merasa bangga menjadi bagian organisasi yang menyelenggarakan acara ini. Dengan penuh rasa bangga, sampai lupa kalau yang merasakan manis hanya sosok yang dibanggainya saja. Ia tetap menjadi korban dari acara yang dibanggainya. Para akademisi dan aktivis sosial, sangat terang melihat kondisi yang kontras ini. Kritik pun dilancarkan melalui dinding media. Meskipun, algoritma lebih berpihak pada pujian-pujian dan apresiasi terhadap acara tersebut.
Upaya pertemuan tokoh agama semacam ini, sudah sering dilakukan oleh beberapa organisasi keagamaan. Namun sebatas pertemuan dalam lingkup mikro. Visinya sama, yakni memberikan solusi di tengah problem yang merebak di tengah-tengah masyarakat. Hasilnya pun tak jauh berbeda. Gagasan sebatas gagasan untuk memenuhi agenda. Dalam penerapannya, tidak sampai memberikan solusi, khususnya di kalangan akar rumput. Parahnya, gagasan dari pemuka agama itu mengendap; tidak terjamah sama sekali.
Gagasan yang baru dicetuskan, menjadi bahan bagi kaum cendikiawan, dan melahirkan gagasan yang baru lagi. Begitu seterusnya. Sedangkan rakyat tetap miskin, seperti kondisi biasanya. Kondisi demikian, membuka celah bagi kelompok yang diduga fundamentalis untuk membuat program yang langsung menyentuh ke akar rumput. Buktinya nyata. Bantuan demi bantuan dilancarkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Semua berjalan tertib dan administratif, tanpa mendesain dengan pernak pernik yang memancing media. Sebab, yang nomer wahid adalah visi dapat berjalan dan bermanfaat, bukan pengakuan dan kebanggaan.
Namun semua ini ada sisi baik dan buruknya. Dampak baiknya, masyarakat terbantu dalam hal sandang, papan, dan pangan. Dampak buruknya, akidah mereka akan ikut dengan kelompok fundamentalis. AS Laksana menggambarkan dalam bukunya, Menghidupkan Gus Dur: Di sebuah Jalan, kita membuka toko, punya banyak pelanggan, dan lama-lama kita menjadi teledor dalam mengurus toko kita dan tidak melayani pelanggan dengan baik. Di seberang jalan, ada orang membuat toko juga, lebih kecil dibandingkan toko kita, tetapi pemiliknya ramah dan ia melayani pembeli secara memuaskan. Beberapa pelanggan kita berpindah ke toko seberang jalan. Kita marah dan mengobrak-abrik toko kecil itu.
Lalu bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan? Melalui bukunya, Islam Praksis, Ayang Utriza Yakin menyinggung sikap yang seharusnya dilakukan oleh cendikiawan Muslim kita, selaku orang yang terlibat dalam pembahasan-pembahas di lingkar organisasi keagamaan. Ia membaginya menjadi dua: cendikiawan Muslim teoritis dan cendikiawan Muslim Praksis.
Adapun cendikiawan Muslim teoritis, seperti yang sudah dipaparkan di atas, yakni pihak yang beradu gagasan, dengan seabrek teori yang melintang dari barat hingga timur, dan segudang dalil-dalil otoritatif. Mereka ini masih bercanda ria dengan pemikiran dan gagasan yang jauh dari kenyataan objektif rakyat Indonesia. Kepedulian terhadap korban banjir, bencana alam, mengentaskan kemiskinan menyejahterakan masyarakat yang menjadi kantong potensial persemaian benih-benih fundamentalisme, hujjah mereka tidak tampak. Dengan demikian, lagi-lagi urusan kaum proletar ditangani oleh gerakan yang selama ini diidentifikasi sebagai fundamentalis, radikal, atau ekstrimis.
Sedangkan cendikiawan Muslim praksis, sebaliknya. Gagasan mereka membumi; terjamah dan dirasakan manfaat dan perubahannya sampai ke akar rumput. Mungkin, baiknya kita belajar dari pengalaman para cendikiawan Muslim praksis, seperti Farid Esack (1.1955) dan Muhammad Yunus (1.1940). Cendikiawan Muslim asal Afrika Selatan dan Bangladesh ini mengembangkan wacana Islam pro-rakyat tertindas di kalangan akademisi, tetapi juga terlibat dalam perjuangan kehidupan rakyat sehari-hari.
Farid Esack, melalui organisasinya, yaitu gerakan Islam progresif, The Call of Islam, merangkul seluruh umat-umat beragama lainnya: Kristen,Yahudi, dan Ateis sekalipun, untuk bersama meruntuhkan rezim Apartheid yang zalim terhadap rakyatnya. Kerangka bangunan pikirannya dalam membangun kerja sama antar umat beragama menentang penindasan, menghasilkan sebuah karya: Qur'an, Liberation, and Pluralism. An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression.
Ia menjadi landasan berjuang melawan kezaliman, mengembangkan pluralisme, dan toleransi antar umat beragama. Pun, Muhammad Yunus, peraih nobel perdamaian ini mampu mengentaskan kemiskinan di negerinya sendiri, dan menghancurkan sistem tengkulak yang menghisap perekonomian Bangladesh lewat Bank Ghrameen yang didirikannya.
Di Indonesia, Gus Dur termasuk dalam kategori ini, yaitu seorang intelektual, kiai, dan aktivis yang diterima oleh semua kalangan. Gus Dur merupakan cendikiawan Muslim Indonesia yang berhasil mengawinkan antara intelektualisme dengan aktivisme. Ia menulis, meneliti, memberikan kuliah, dan berbicara di berbagai forum untuk memaparkan ide keislamannya yang progresif dan emansipatif. Namun, ia juga seorang ustadz, kiai, dan mubaligh yang ceramah di kalangan akar rumput. Sumbangan terbesar Gus Dur adalah telah mendorong ide demokratisasi dan mengembangkan wacana masyarakat sipil, demokrasi, dan HAM di kalangan Nahdliyin. Bahkan, di kalangan aktivis pro-demokrasi, Gus Dur dihargai sebagai pejuang demokrasi dan pembela HAM yang tak kenal lelah.
Gus Dur tidak meninggalkan dunia dakwah, seperti juga Nurcholish Madjid. Soedjatmoko pernah berpesan kepada Cak Nur agar tidak meninggalkan dunia dakwah. Sebab di sanalah komunitas, umat, dan dunia Cak Nur untuk menyampaikan gagasannya hingga ke pelosok nusantara. Oleh karena demikian, Indonesia sangat butuh Muslim yang akademis dan organisatoris: Muslim Praksis, untuk memperbaiki tatanan kehidupan bernegara yang madani, sesuai tuntunan agama Islam.
Judul Buku: Islam Praksis
Penulis: Ayang Utriza Yakin
Penerbit: IRCiSoD
Cetaka: I, September 2022
ISBN: 978-623-5348-14-8





