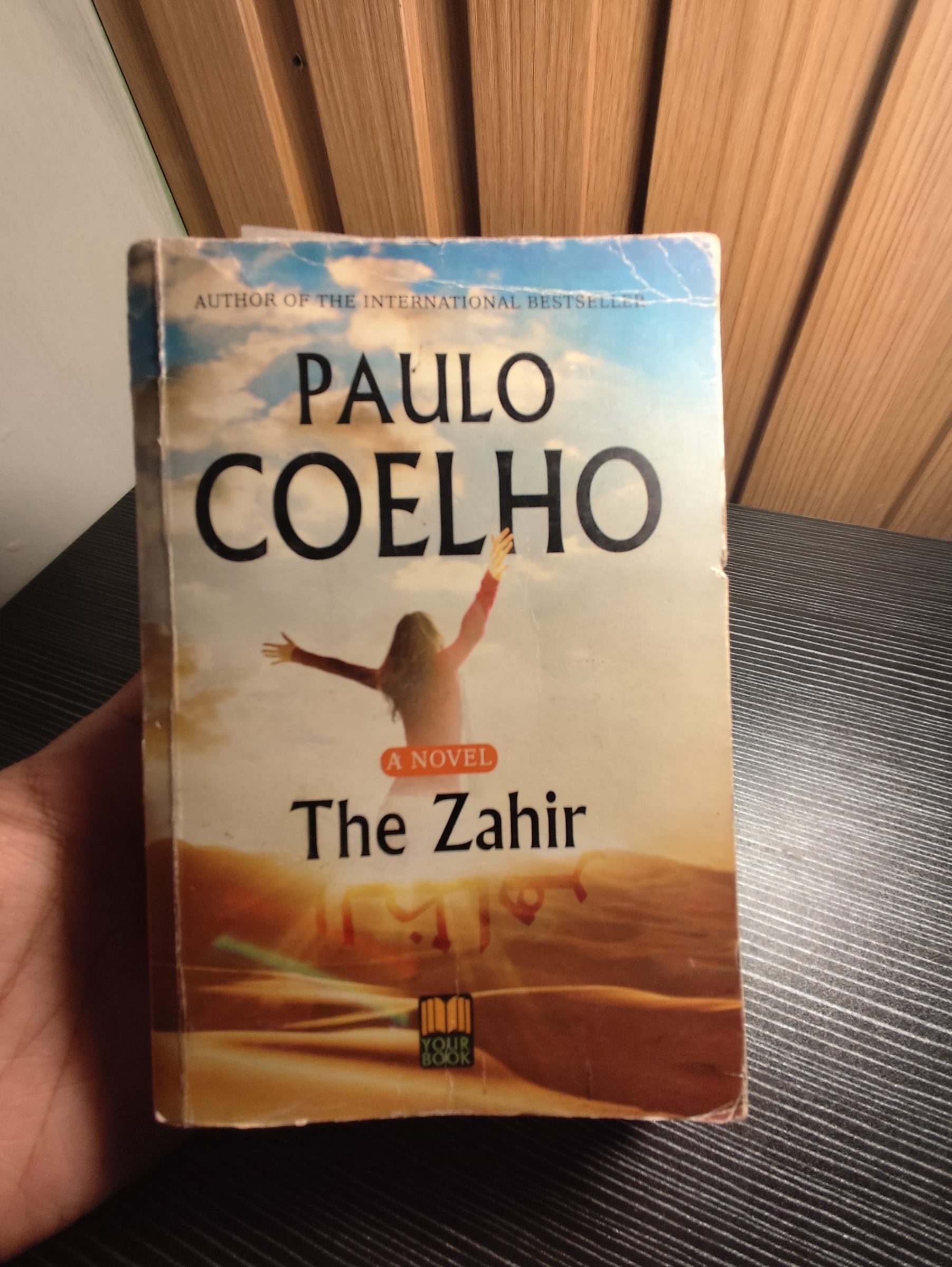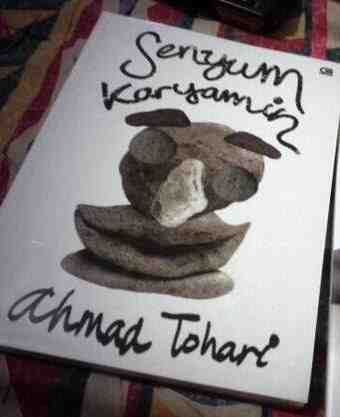Ketika pertama kali membuka halaman-halaman The Zahir karya Paulo Coelho, saya tidak menyangka bahwa novel ini akan cukup membekas dalam benak dan hati. Novel ini memanglah karya lawas, terbit pada tahun 90-an, tetapi masih sangat relevan untuk dibaca saat ini. Coelho, dengan gaya penulisan filosofisnya yang khas, mengangkat konsep Zahir, sebuah istilah dari tradisi Islam yang sarat makna. Meskipun novel ini tidak secara eksplisit membahas Islam, nilai-nilai sufisme meresap ke dalam alur ceritanya, menjadikannya lebih dari sekadar kisah tentang pencarian dan cinta.
Makna Zahir
Di awal novel, kita langsung disambut dengan kutipan yang memperkenalkan konsep dari novel tersebut:
"The idea of the Zahir comes from Islamic tradition and is thought to have arisen at some point in the eighteenth century. Zahir, in Arabic, means visible, present, incapable of going unnoticed. It is someone or something which, once we have come into contact with them or it, gradually occupies our every thought, until we can think of nothing else. This can be considered either a state of holiness or of madness."
Konsep Zahir berasal dari tradisi Islam dan diyakini telah muncul sekitar abad ke-18. Dalam bahasa Arab ظاهر yang berarti sesuatu yang tampak, hadir, dan mustahil untuk diabaikan. Ia bisa berupa seseorang atau sesuatu yang, begitu kita bersentuhan dengannya, perlahan-lahan menguasai pikiran kita hingga tak ada ruang untuk hal lain. Kondisi ini bisa menjadi jalan menuju kesucian, atau justru menjerumuskan seseorang ke dalam kegilaan.
Zahir sebenarnya memiliki makna lebih dalam dari sekadar sesuatu yang terlihat oleh mata. Zahir mengisyaratkan bahwa ada hal-hal yang begitu nyata di hadapan kita, tetapi justru terasa menghilang atau luput dari perhatian. Ini seperti seseorang yang hadir secara fisik tetapi jiwanya terasa jauh, atau sesuatu yang selalu ada dalam pikiran kita, tetapi justru sulit untuk benar-benar kita pahami atau genggam.
Mengingatkan kita dengan ayat yang berbunyi:
لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
"Mereka memiliki mata, tetapi tidak melihat dengannya. Mereka memiliki telinga, tetapi tidak mendengar dengannya." (QS. Al-A’raf: 179)
Cinta dan Pencarian Diri
The Zahir menceritakan tentang seorang penulis terkenal yang tiba-tiba ditinggalkan oleh istrinya, Esther, tanpa jejak. Kehilangan ini menjadi obsesi baginya, mendorongnya untuk melakukan perjalanan fisik dan batiniah demi menemukan sang istri dan, pada akhirnya, dirinya sendiri. Perjalanan ini membawanya melintasi berbagai negara dan budaya, mempertemukannya dengan individu-individu yang menawarkan perspektif berbeda tentang cinta, kebebasan, dan makna kehidupan.
Dalam sufisme, cinta dianggap sebagai jalan menuju Tuhan. Jalaluddin Rumi, seorang sufi terkenal, menulis bahwa melalui cinta, seseorang dapat mencapai pemahaman yang lebih tinggi tentang eksistensi. Penderitaan akibat kehilangan, seperti yang dialami tokoh utama, seringkali menjadi katalis bagi transformasi spiritual. Kehilangan Esther menjadi Zahir bagi sang penulis—sebuah obsesi yang memaksanya merenungkan kembali hidupnya dan mencari makna yang lebih dalam di balik eksistensinya.
Antara Kegilaan dan Kesucian
Coelho dengan cerdas menggambarkan Zahir sebagai pedang bermata dua: ia bisa menjadi sumber pencerahan atau justru jebakan obsesi yang menyesatkan. Dalam novel, Zahir hadir sebagai sesuatu yang terus menghantui pikiran, memaksa seseorang untuk mencari jawaban yang lebih dalam. Jika dipahami dengan benar, Zahir bisa menjadi pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Namun, jika terjebak dalam keterikatan duniawi, ia justru berubah menjadi obsesi yang menguras jiwa.
Dalam tradisi sufi, terdapat konsep fana’—keadaan di mana ego lenyap dalam kehadiran Ilahi. Ini adalah pengalaman spiritual yang begitu dalam sehingga orang yang mengalaminya seakan kehilangan dirinya sendiri, melebur dalam cinta kepada Tuhan. Namun, bagi mereka yang belum memahami esensi pengalaman ini, fana’ sering kali dianggap sebagai kegilaan atau penyimpangan.
Salah satu contoh paling terkenal adalah kisah Mansur al-Hallaj, seorang sufi abad ke-10 yang mengucapkan "Ana al-Haqq" (Akulah Kebenaran). Dalam bahasa zahir, pernyataan ini terdengar seperti seseorang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan—sebuah bentuk kesesatan dalam Islam. Namun, dalam pemahaman sufi, pernyataan "Ana al-Haqq" yang diucapkan Al-Hallaj bukanlah bentuk kesombongan atau klaim ketuhanan, melainkan ekspresi dari kefanaan dirinya dalam Tuhan. Dalam keadaan ini, ego dan identitas pribadinya telah musnah, yang tersisa hanyalah eksistensi Ilahi semata.
Seperti yang dijelaskan oleh Jalaluddin Rumi dalam Fihi ma Fihi, sebagaimana dikutip dalam The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi oleh William C. Chittick (hal. 191-193):
“When Hallaj’s love for God reached its utmost limit, he became his own enemy and naughted himself. He said, ‘I am Haqq,’ that is, ‘I have been annihilated; God remains, nothing else.’ This is extreme humility and the utmost limit of servanthood. It means, ‘He alone is.’”
"Ketika cinta Al-Hallaj kepada Tuhan mencapai puncaknya, ia meniadakan dirinya sendiri. Ia berkata, ‘Ana al-Haqq’, yang berarti, ‘Aku telah lenyap; yang tersisa hanyalah Tuhan.’ Ini bukan bentuk keangkuhan, melainkan puncak dari kerendahan hati seorang hamba."
Rumi juga membandingkan pernyataan Al-Hallaj dengan klaim Firaun:
“Pharaoh said, ‘I am God,’ and became despicable. Hallaj said, ‘I am Haqq,’ and was saved. That ‘I’ brought with it God’s curse, but this ‘I’ brought His Mercy.”
"Firaun berkata, ‘Aku adalah Tuhan,’ dan menjadi hina. Hallaj berkata, ‘Aku adalah Kebenaran,’ dan ia diselamatkan. ‘Aku’ yang satu mendatangkan murka Tuhan, sementara ‘Aku’ yang lain membawa rahmat-Nya."
Perbedaan ini menjadi inti dari konsep fana’ dalam tasawuf—bukan kehilangan akal, tetapi melebur dalam kehadiran Ilahi dengan kesadaran yang lebih dalam. Al-Hallaj tidak sedang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, tetapi meniadakan dirinya sepenuhnya dalam keesaan-Nya. Di sinilah letak paradoks spiritual yang sering kali disalahpahami: yang tampak sebagai kebesaran justru merupakan bentuk next level dari sebuah penghambaan.
Ketika orang-orang menempatkan Tuhan begitu jauh dan tak terjangkau, Al-Hallaj justru secara revolusioner menantang pandangan itu dengan mendekatkan kembali Tuhan kepada manusia. Ia ingin menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah entitas yang jauh dan tak bisa diraih, melainkan hadir dalam setiap aspek kehidupan, dalam setiap napas, dalam setiap helaan rindu seorang pencari. Namun, keberanian ini yang akhirnya membuatnya dihukum mati—bukan karena ia sesat, tetapi karena masyarakat belum siap menerima pemikirannya.
Novel ini seakan mengajak pembaca untuk merenungkan: apakah sesuatu yang terus menghantui pikiran kita adalah sebuah jalan menuju kebenaran, atau justru perangkap ego yang menghambat perjalanan spiritual kita?