Masjid di Zaman Visual
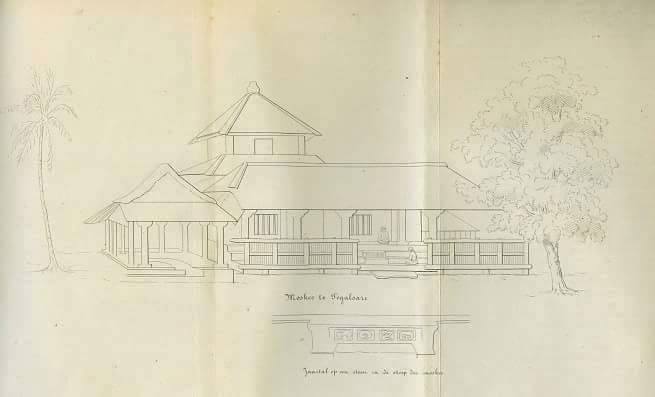
Di Solo, Jawa Tengah, Pada Tahun 1954, Raden Nganten Tumanggung Prawirodirdjo (Bu Manggung) membangun Masjid “Solichien” di Kampung Surakarta yang dibiayanya sendiri. Berita Minggu Pagi No. IX. 30 Mei 1954, menuliskan ihwal arsitektur dan maknanya:
“Bentuknja bangunan masdjid tjara djawa modern, jakni di atas memakai tiga tingkatan empat mustaka jaitu lambang : Sjariat, Tarikat, Ma'rifat dan dipuncjak Hakekatnja satu tulak guntur diedari bola lima (pantja sila), semoga para jang ada minat dan tjinta serta menghadiri masdjid ini mudah2an ditakdirkan mendjadi tergolong orang2 jang salih (baik laik), dapat memenuhi kewadjiban berbakti kehadirat Allah s.w.t. dan taat memenuhi pula kebaikan dalam pergaulan masjarakat”.
Meskipun bangunannya kecil, sederhana, dan bercorak Jawa, konstruksinya memiliki makna yang sarat nilai keislaman. Bu Manggung tahu, masjid semegah apa pun, tak bisa memastikan bahwa yang menghadirinya benar-benar memiliki niat untuk beribadah, kecuali orang itu sendiri.
Ia berharap siapa pun yang berkehendak menghadiri Masdjid Solichien untuk menunaikan kewajibannya, Insya Allah tergolong orang-orang yang saleh.
Tidak salah, kesimpulan Bu Manggung sejalan dengan hadis:
“Telah kujadikan tanah itu masjid bagiku, tempat sujud” artinya bukan hanya mengenai tempat sujud atau tempat ibadah tertentu, melainkan tiap sudut permukaan bumi, terbatas dengan sesuatu tanda ataupun tidak, beratap atau bertadah langit, bagi orang Islam sebenarnya dapat dinamakan masjid, jika di sana ia mengerjakan shalat, jika di situ hendak ia letakan dahinya. Sujud menyembah Tuhannya. (Aboebakar : 1955)
Pengisahan masjid di atas agaknya membikin resah bila menyaksikan kenyataan hari ini, utamanya berlatar ke-Indonesiaan. Di kota, kita biasanya mendapati bangunan masjid yang besar dan megah. Beberapa daerah memiliki masjid sebagai ikon atau identitas kota.
Kita mengenal Masjid Baiturrahman sebagai simbol masyarakat Aceh, atau Masjid Istiqlal sebagai simbol Ibu Kota Negara. Jauh di timur Indonesia, Tidore, Maluku Utara dijuluki sebagai kota seribu masjid. Di kota ini, pendatang nyaris kebingungan memilih masjid mana, hendak ia melaksanakan shalat. Beberapa kampungnya bahkan memiliki masjid di setiap RT.
Anomali Masjid Perkotaan
Kota dirancang untuk membuat masyarakatnya merasa nyaman. Selanjutnya dipermak untuk menarik minat pendatang/wisatawan. Sebagai manusia urban, kenyamanan kota selalu dinomor satukan. Ruang- ruang publik disulap dengan segala fasilitas yang menyenangkan. Bahkan bila itu adalah tempat ibadah. Di mana-mana masjid dibangun dengan megah.
Jumlah masjid di Indonesia pada tahun 1974 sebanyak 90.570 buah (Sidi Gazalba: 224). Pada tahun 2017, di Hotel Rafles, Ketua Dewan Masjid, Jusuf Kalla di hadapan Raja Salman Bin Abdulaziz mengatakan, jumlah masjid di Indonesia sebanyak 800 ribu dan membuat Raja Arab terkejut (Tribun, 04 Maret 2017).
Sebuah berita kecil di Republika, 23 Maret 2018, Jakarta Islamic Center (JIC) bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendorong upaya pengelolaan wisata religi berbasis masjid, di antaranya Masjid Istiqlal, Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Jakarta Islamic Center, dan Masjid Jenderal Besar Soedirman untuk mengundang wisatawan lokal maupun mancanegara.
Masjid sebagai lambang syariat, hakikat dan makrifat tereduksi ke dalam hal-hal yang profan karena kebijakan yang lalim. Bahkan menjadikan masjid sebagai lahan ekonomi, sebagaimana Pengurus Pusat (PP) Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) mengembangkan ekonomi umat melalui Masjid Mart dengan harapan dapat membantu ekonomi para Dai, agar dalam berdakwah semakin ikhlas tanpa mengharapkan imbalan (Republika, 27 maret 2018). Untuk berdakwah dengan ikhlas barangkali dianggap perlu dimakmurkan terlebih dahulu.
Sebagai pusat peribadatan dan penyelesaian masalah keumatan; pendidikan, sosial, kebudayaan, bahkan kenegaraan. Mengunjungi masjid adalah kewajiban dengan tujuan beribadah. Mendatangi untuk memakmurkannya, bukan sebaliknya dimakmurkan oleh masjid atau semata menjadikannya daftar destinasi wisata bahkan pasar.
Pergeseran Makna Masjid
Hari ini, masjid bukan lagi bangunan tapi “kamera”, hasil jepretan yang dipajang atau diposting di Instagram. Kita banyak menemukan masjid dijadikan latar dalam syuting film-film bernuansa Islami, iklan busana muslim pada poster-poster. Masjid pun hadir di baliho kandidat untuk mempertegas keislamannya di tengah maraknya perang isu saling mengafirkan.
Masjid sudah mempunyai pengertian yang lain sebagai suatu bangunan, gedung yang dipergunakan untuk melakukan ibadah salat. Ia juga sebagai tempat wisata sebagaimana tersaji pada berita di atas.
Motivasi orang ke masjid pun menjadi berbeda-beda. Pengunjung dari berbagai agama dan negara dapat mengakses masuk dengan bebas. Kita tidak bisa memastikan hal-hal yang mencoreng kesucian masjid bila pengawasannya lemah. Orang-orang berswafoto, bersuka ria bahkan bisa saja berpacaran di areal masjid.
Belakangan, beberapa jamaah haji asal Indonesia melakukan shelfie di Masjid Haram dan ditegur oleh Pemerintah Arab Saudi. (Republika, 25 Novermber 2017). Shelfie di masjid bukan dosa, tetapi perjalanan haji dan umrah adalah ibadah suci yang dilakukan dengan khusyuk. Menunaikan Ibadah tidak sama dengan perjalanan wisata. Meskipun tidak ada dalil yang mengaturnya, menjaga kekhusyukan amatlah penting.
Masjid, bagaimanapun indah dan besarnya, tetap menjadi pusat perumahan bagi tiap-tiap negeri maupun perkampungan Islam. Berlainan halnya dengan pasar, mall atau tempat wisata.
Masjid tidak semata bersifat perhubungan manusia dan dunia semata, melainkan hubungan manusia dengan Tuhan. Kita tidak sekadar melaksanakan ibadah tapi sekaligus bertamu ke rumah-Nya.
Seolah, sabda Nabi, setiap langkah kaki menuju masjid adalah ibadah barangkali tak berlaku bagi pengunjung masjid dengan tujuan wisata religi. Wallahualambissawab. []





