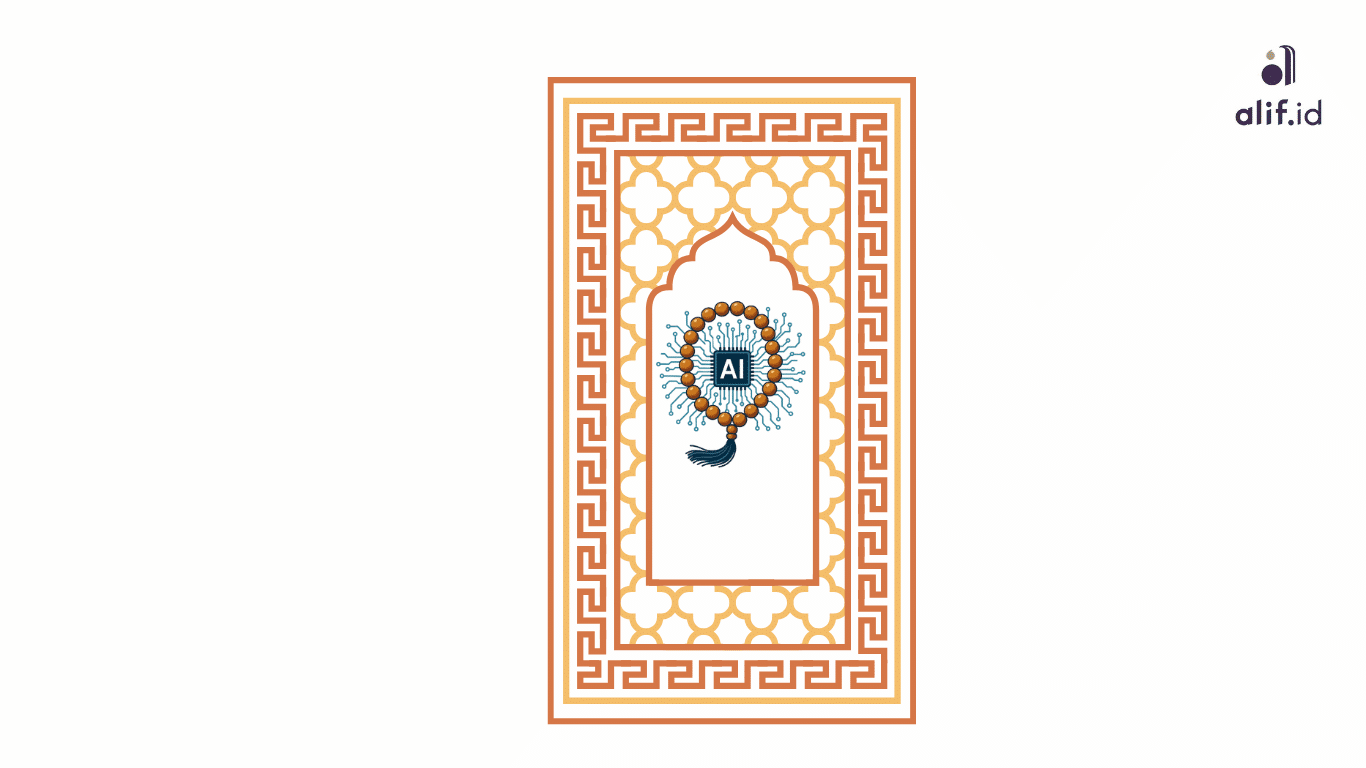
Setelah ramai kontroversi lukisan di Galeri Nasional (Galnas) yang tiba-tiba menutup sejumlah lukisan pameran tunggal karya Yos Suprapto, berjudul Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan akhir Desember 2024 lalu, meski tidak sampai berujung status tersangka, kini seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, berinisial SSS, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri karena mengunggah meme digital bergambar adegan ciuman Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo.
Meme yang dimaksud, bisa bersifat satir, lalu dianggap melanggar kesusilaan dan menjelekkan martabat pejabat publik, sehingga SSS dijerat pasal kontroversial dari UU ITE. Sebuah aturan yang kerap digunakan untuk membungkam ekspresi masyarakat.
Proses hukum masih berlangsung, sementara motif tindakan tersebut disebut “masih didalami” oleh penyidik Direktorat Siber.
Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE hanya merujuk pada individu atau perseorangan, guna mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam penerapannya.
Keputusan ini memberikan kepastian hukum kepada individu, bukan institusi. Artinya institusi atau lembaga tidak bisa lagi merasa mendapat fitnah atau serangan digital, terutama di era disinformasi yang dapat dengan cepat merusak reputasi institusi atau lembaga melalui media sosial. Jadi jelas, SSS tidak bisa dikenai UU ITE, namun perlu dilihat bahwa mahasiswi ini tentu merasa terganggu bahkan terancam secara psikologis setelah penetapan tersangka.
Sementara itu, ITB mengonfirmasi status akademik SSS dan menyatakan telah memberikan pendampingan serta menjalin komunikasi dengan orang tua dan Ikatan Orang Tua Mahasiswa. Kedatangan orang tua SSS ke kampus disertai permintaan maaf, menambah peristiwa drama yang menempatkan seorang mahasiswa seni di tengah pusaran politik dan hukum negara. Dalam hal ini mahasiswi dan keluarganya jelas dalam posisi yang lemah dihadapan kekuasaan.
Di tengah desakan moral menjaga kebebasan berekspresi, kasus ini menjadi potret getir betapa satire bisa dianggap subversif di negeri demokrasi ketiga terbesar di dunia.
Saya tidak mengerti kenapa adegan ciuman sepasang lelaki bisa ditangkap? Apakah kampanye terhadap dukungan LGBTQ, ataukah ciuman ideologis sebagai tanda persatuan? Ataukah dalam arti lain sebuah ciuman literal yang barangkali bagi sebagian orang dianggap norak. Tapi justru karena norak dan tak lazim itu, meme ini jadi bermakna subversif? Tapi apakah sesubversif itu?
Lalu kenapa negara turun tangan?
Satir dalam Negara Demokrasi
Di negara-negara dengan demokrasi mapan seperti Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat, satir bukan hanya dibiarkan, tetapi dipelihara. Gambar Presiden Emmanuel Macron menjadi Smurf atau Donald Trump dengan popok bayi tidak hanya tidak dihukum, tapi sering kali dijadikan headline majalah mingguan. Charlie Hebdo, sebuah majalah satir di Prancis, secara rutin menggambarkan para tokoh dunia, termasuk Nabi Muhammad, dengan gaya kasar, ofensif, bahkan vulgar. Mereka memang menuai protes, boikot, bahkan serangan teror, namun negara tidak pernah menangkap para kartunis.
Mengapa? karena di sana, demokrasi tidak hanya dimaknai pemilu lima tahun sekali. Demokrasi adalah kebudayaan. Sebuah sistem nilai yang menyerap kritik, olok-olok, bahkan kebodohan massal sebagai bagian dari proses hidup bersama. Mereka mengerti bahwa sebuah meme, sejelek dan senorak apapun, tak akan mengguncang republik kecuali republik itu sendiri rapuh.
Kuasa Feodalisme Atas Demokrasi
Kita, di Indonesia, hidup dalam demokrasi prosedural. Kita pemilih aktif, tapi bukan warga negara kritis yang bisa kapan saja memberikan pandangan atas keputusan yang diambil pemerintah. Kita bebas memilih pemimpin, tetapi belum bebas menertawakannya. Di sini, pemimpin adalah figur semi-sakral, setengah dewa, dan sepenuhnya kebal kritik. Meme yang mengolok mereka bisa dianggap “melanggar kesusilaan” bahkan tidak beradab. Penguasa seperti menjelma ibu tiri yang terlalu sensitif. Sedikit saja diusik, langsung mengeluarkan pasal.
Lagi-lagi, UU ITE bisa digunakan sebagai jubah suci dalam negeri demokrasi semu. Ia dipakai kapan saja, oleh siapa saja, untuk apa saja. Isinya samar, tafsirnya elastis, dan penggunaannya oportunistik. Ia seperti pisau Swiss Army yang bisa digunakan Macgyver untuk mengupas apel, mengulik kabel, membuka borgol, mengiris bawang, dan menusuk siapa pun yang mengganggu kenyamanan elite.
Inilah bentuk feodalisme digital. Raja tak lagi tinggal di istana, tapi dalam algoritma penguasa.
Apakah Meme Bisa Merusak Kesusilaan?
Pertanyaan sederhana. Apa itu “kesusilaan”? Apakah kesusilaan Indonesia sedemikian rentan sehingga satu gambar digital bisa meruntuhkannya? Kalau benar begitu, maka betapa rapuhnya bangsa ini. Bangsa yang melahirkan para penyair raksasa seperti Chairil Anwar dan WS Rendra, kini tersungkur hanya oleh gambar editan beresolusi rendah.
Di negara yang sehat, kesusilaan tak didefinisikan oleh sensitivitas penguasa, tapi oleh konsensus akal sehat.
Lebih tragis adalah logika hukum yang dipakai. Meme dianggap lebih merusak ketertiban umum daripada hoaks soal pemilu, korupsi triliunan, atau kekerasan aparat terhadap warga sipil. Di negeri ini, gambar saja bisa dianggap subversif, tapi pembunuhan karakter dianggap strategi politik.
Meme jadi musuh negara, tapi oligarki jadi mitra strategis.
Tertawalah Sebelum Tertawa itu Dilarang
Di Amerika Serikat, The Onion dan Saturday Night Live setiap minggu membuat karikatur tokoh-tokoh politik. George Bush digambarkan orang bodoh, Obama dibikin seperti nabi palsu, dan Trump sebagai badut oranye. Karena perbuatan itu tak ada satu pun komedian dipenjara. Bahkan ketika Stephen Colbert memarodikan Presiden Bush di depan Bush sendiri dalam jamuan resmi Gedung Putih tahun 2006, negara tidak reaktif. Sebab di sana, pemimpin tahu bahwa dikritik bagian dari jabatan publik.
Mengapa di Indonesia seorang mahasiswa bisa ditahan karena meme? Karena kita belum matang berdemokrasi. Masyarakat kita belum paham bahwa tertawa bukan bentuk penghinaan, tapi ujian bagi legitimasi kekuasaan. Seorang penguasa yang takut pada lelucon adalah penguasa yang selalu merasa tidak aman dan terancam.
Sejarah Tertawa dalam Politik
Jika kita melihat sejarah, tawa selalu punya peran subversif. Di zaman Romawi, para budak dipekerjakan untuk mengejek kaisar agar sang penguasa tidak lupa bahwa ia juga manusia. Di Prancis era Revolusi, para pamflet satir mengguncang takhta Louis XVI lebih keras daripada senapan. Di negeri komunis Uni Soviet, lelucon bawah tanah tentang Stalin beredar diam-diam, sebagai cara rakyat mempertahankan kewarasan dalam rezim represif.
Satir, dalam tradisi itu, adalah penyeimbang kekuasaan. Ia adalah rakyat yang bicara ketika parlemen tak bisa bersuara. Ketika media dibungkam, tawa mengambil alih.
Gejala negara yang terlalu cepat tersinggung adalah tanda kemunduran. Dekaden alias kemerosotan moral. Negara seperti tidak percaya pada warganya. Ia curiga pada suara, marah pada tawa, dan alergi pada kebebasan. Ketika negara lebih takut pada meme daripada pada korupsi atau intoleransi, itu artinya negara sedang kehilangan arah.
Lalu, siapa yang sebenarnya melanggar kesusilaan? Apakah si pembuat meme yang menyindir elite, atau negara yang memenjarakan orang karena membuat gambar?
Meme adalah dialog, bukan dosa. Benarlah meme juga bukan kebenaran mutlak. Ia hanyalah komentar sosial. Kadang lucu, kadang sarkas, kadang tak bermutu, murahan dan norak. Tapi ia adalah bagian dari percakapan publik. Menyensor meme sama dengan mematikan debat. Mengkriminalkan tawa adalah mengingkari demokrasi.
Jangan salah. Meme itu juga bisa didebat. Bisa dikritik. Bahkan bisa dianggap bodoh. Tapi ia tidak bisa dipenjara. Sebab ketika negara memenjarakan ekspresi, negara sedang membunuh kebebasan.
Negara Kuat Tidak Mudah Tersinggung
Negara yang kuat tidak mudah tersinggung. Negara yang dewasa tidak takut parodi. Negara yang sehat menganggap kritik, bahkan yang sarkastik sekalipun, sebagai vitamin demokrasi. Kalau ada meme menghina presiden, biarkan publik menilai. Kalau buruk, orang akan tertawa dan lupa. Kalau tajam, orang akan merenung.
Tapi kalau negara ikut turun tangan, apalagi dengan tangan besi, maka meme itu berubah dari lelucon jadi simbol perlawanan. Dan saat itulah kita tahu, yang ditertawakan sebenarnya bukan tokohnya, tapi keroposnya sistem kekuasaan sepantasnya terus ditertawakan.
Penulis akan menutup anekdot yang disampaikan Gus Dur. Gus Dur adalah presiden yang tidak segan menertawakan kekuasaan meski ia sedang duduk di singgasana istana negara.
Suatu ketika, Gus Dur pernah ditanya soal karakter bangsa. Dengan santai, beliau menjawab sambil memberi perbandingan antar negara.
Katanya, orang Nigeria dan Angola itu kalau ngomong sedikit, kerja juga sedikit. Orang Jepang dan Korea Selatan, ngomongnya sedikit tapi kerjanya luar biasa banyak. Sementara orang Amerika dan China, dua-duanya. Ngomong dan kerja sama-sama banyak. Nah, giliran orang Pakistan, menurut Gus Dur, hobinya ngomong banyak tapi kerja sedikit.
Lalu, si penanya penasaran, “Kalau orang Indonesia gimana, Gus?”
Dengan senyum khasnya, Gus Dur menjawab singkat tapi mengena, “Orang Indonesia itu, lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan.”





