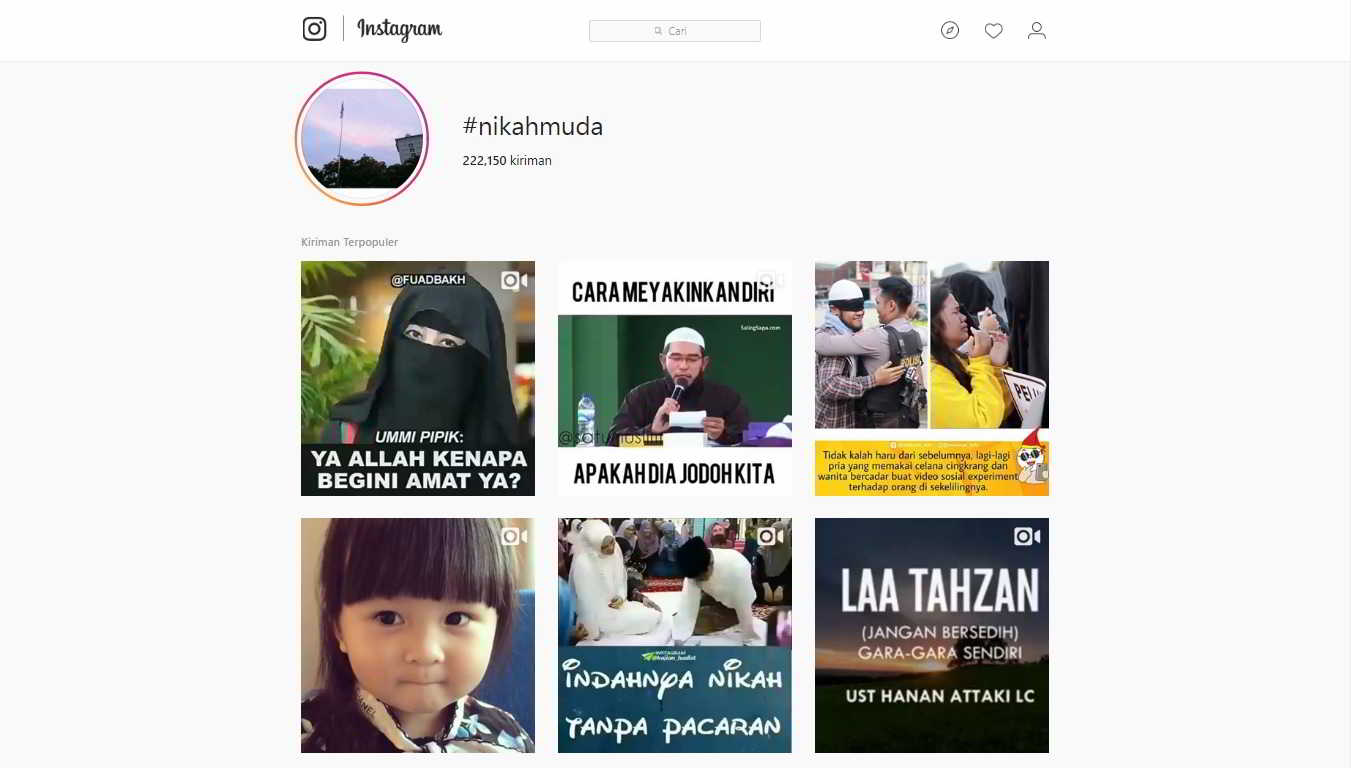Politik Kemanusiaan Ibu-ibu Berpanci
Program MBG telah menelan banyak korban. Ribuan anak keracunan usai menyantap makanan. Dari gejala pusing, mual, hingga kejang-kejang. Hal ini menjadikan mereka trauma.

Di Bundaran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pada Jumat, 26 September 2025 sore, dentang panci bergema lebih keras daripada pidato pejabat. Sekitar seratus ibu dari berbagai latar belakang memukul peralatan dapur mereka, serentak, membiarkan logam beradu jadi bahasa yang tak bisa disensor (kompas.id, 26/9/2025). Suara itu lahir dari duka, dari kasih sayang, dan dari rasa marah yang tak lagi bisa ditampung dalam kata-kata.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dijanjikan sebagai bunga kampanye, justru berbuah petaka. Ribuan anak (angka resmi 6.618, laporan independen menyebut hampir 8.000) jatuh sakit akibat makanan yang seharusnya menyehatkan. Ada yang muntah, pusing, masuk rumah sakit. Bahkan ada ibu menyusui dan guru yang ikut keracunan.
Tubuh-tubuh yang sakit itu bukan sekadar angka. Ia adalah nyawa, doa, dan harapan yang dititipkan keluarga pada negara. Ketika semua itu dicederai oleh kebijakan yang sembrono, wajar jika para ibu turun tangan.
Yang menarik, protes itu tidak tampil sebagai demonstrasi konvensional. Tidak ada orasi panjang, tidak ada spanduk partai. Yang terdengar hanyalah suara panci dan spatula, benda-benda domestik yang sehari-hari dipakai merawat hidup.
Simbol ini mengusik sekaligus menusuk. Negara yang mestinya melindungi kehidupan warganya justru menyajikan racun bagi anak-anaknya. Maka dapur ibu-ibu, ruang domestik yang paling sunyi dan paling sabar, dipaksa keluar ke jalan untuk bersuara.
Transformasi Logika
Secara antropologis, kita menyaksikan transformasi domestik menjadi publik. Antropolog strukturalis Prancis, Claude Lévi-Strauss dalam The Raw and the Cooked (1st U.S. ed,; 1983) menulis bahwa makanan adalah cara utama manusia mengolah alam jadi budaya. Tetapi ketika “makanan negara” malah mencederai anak-anak, ibu-ibu menegaskan kembali daulat dapur. Panci bukan hanya wadah nasi, melainkan wadah kritik. Suara dentangnya menolak logika kekuasaan yang salah kaprah.
Lebih jauh, aksi ini bahkan sarat dengan simbol religius. Dalam tradisi Islam, surga disebut berada di telapak kaki ibu. Hadis ini bukan sekadar romantika, melainkan penegasan posisi moral seorang ibu dalam menegakkan kehidupan. Apa jadinya jika pemilik surga itu dipaksa menyaksikan anaknya teracuni?
Dalam kerangka iman, itu bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk kedzaliman. Seorang ibu yang bangkit bersuara bukan sekadar warga negara, tetapi penjaga amanah ilahi. Ia tidak akan rela anak-anak yang tak berdosa dijadikan korban eksperimen politik.
Di sisi lain, tradisi Jawa mengenal ungkapan “swarga nunut neraka katut”—istri dan anak ditakdirkan ikut jalan suami. Tetapi aksi panci di Bundaran UGM membalik narasi itu. Justru para ibu yang menuntun bangsa ini keluar dari neraka kebijakan yang sembrono.
Para ibu itu gelisah, tapi menolak pasrah. Mereka memimpin dengan cara yang paling sederhana, sekaligus paling sakral, yaitu mengetuk hati bangsa dengan dentang logam.
Darinya kita jadi bisa melihatnya dari perspektif feminisme kontekstual. Ibu-ibu di Bundaran UGM membuktikan bahwa domestik bukanlah tanda diam, melainkan sumber kekuatan politik. Benda dapur yang dianggap remeh, ketika dibawa ke jalan, menjadi simbol pembalikan kuasa. Aksi itu jadi seakan bersuara lantang: jangan pernah meremehkan ranah perempuan, karena di situlah kehidupan dijaga dan dari situlah perlawanan bisa lahir!
Kesalahan Orientasi Bernegara
Tapi yang tidak masuk akal adalah reaksi pejabat. Alih-alih merendah dan mengakui kesalahan, mereka menenangkan publik dengan frasa “program akan diperbaiki sambil berjalan.” Pernyataan ini terdengar konyol. Bagaimana mungkin nyawa anak-anak diperlakukan seperti draf kebijakan yang bisa direvisi sambil dijalankan? Pertanyaan yang mengonfirmasi kebijakan tersebut kepada Presiden justru diberangus oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden dengan mencabut kartu identitas liputan si wartawan (cnnindonesia.com, 28/9/2025).
Dalam tradisi etika publik, kehidupan manusia adalah nilai tertinggi yang tak bisa dinegosiasikan. Ketika negara gagal menempatkan itu di atas segalanya, maka suara panci adalah pengingat keras, bahwa ada yang keliru dalam orientasi bernegara kita.
Politik populis MBG adalah contoh bagaimana janji bisa berubah jadi racun. Kebijakan dikebut demi citra, bukan demi keselamatan. Padahal dalam doktrin agama apa pun, keselamatan nyawa manusia lebih utama daripada formalitas.
Dalam Islam, kaidah dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih menegaskan bahwa mencegah bahaya lebih penting daripada mengejar manfaat. Apa gunanya jargon “bergizi” bila faktanya ribuan anak sakit?
Dimensi Spiritual
Ada dimensi spiritual lain yang perlu dibaca. Tradisi Kristen mengenal gambaran Maria sebagai ibu yang berduka di kaki salib, Mater Dolorosa. Ia melambangkan penderitaan seorang ibu yang menyaksikan anaknya terluka oleh kekerasan kuasa.
Dalam konteks Yogyakarta hari itu, para ibu yang memukul panci adalah Mater Dolorosa kolektif. Mereka berdiri di tengah kota, menyuarakan derita anak-anak bangsa yang terluka bukan oleh musuh, tetapi oleh negara sendiri.
Aksi panci juga mengingatkan kita pada fungsi profetis suara perempuan. Dalam banyak kitab suci, suara perempuan sering diasosiasikan dengan ratapan yang mengguncang langit. Di Yogyakarta, ratapan itu berubah jadi dentang ritmis. Bukan tangis pasif, tetapi protes aktif. Mereka mengajukan politik kemanusiaan yang berakar pada kasih sayang, melawan politik negara yang bebal.
Di satu sisi, sejarah menunjukkan, sering kali suara rakyat dianggap bising sampai terlambat. Tetapi dentang panci itu bukan sekadar bising. Ia adalah alarm moral. Ia berkata: hentikan program MBG, lakukan evaluasi total, jangan main-main dengan hidup anak-anak. Jangan sampai janji populis menjadi darah dan air mata di rumah-rumah rakyat.
Bagi publik, aksi itu adalah undangan reflektif. Kita terlalu sering terjebak pada angka dan jargon, lupa pada tubuh-tubuh kecil yang menderita. Para ibu di Bundaran UGM mengingatkan bahwa politik bukan sekadar tentang kursi, melainkan tentang dapur, tentang kehidupan sehari-hari. Mereka menunjukkan bahwa politik sejati lahir dari kasih sayang, bukan dari ambisi.
Maka, pemerintah hari ini dihadapkan pada pilihan. Mendengar suara panci sebagai alarm kemanusiaan, atau mengabaikannya dan terus berjalan di jalan salah kaprah. Publik pun harus memutuskan: maukah kita ikut menutup telinga, ataukah kita akan ikut mengetuk panci bersama mereka?
Karena di ujung semua ini, suara panci bukan sekadar dentang logam. Ia adalah doa yang dibunyikan. Doa agar bangsa ini tidak kehilangan arah, doa agar anak-anak tidak lagi dijadikan korban, doa agar negara kembali ingat tugas utamanya: melindungi kehidupan. Dan doa, seperti dentang panci itu, tidak pernah bisa dibungkam.