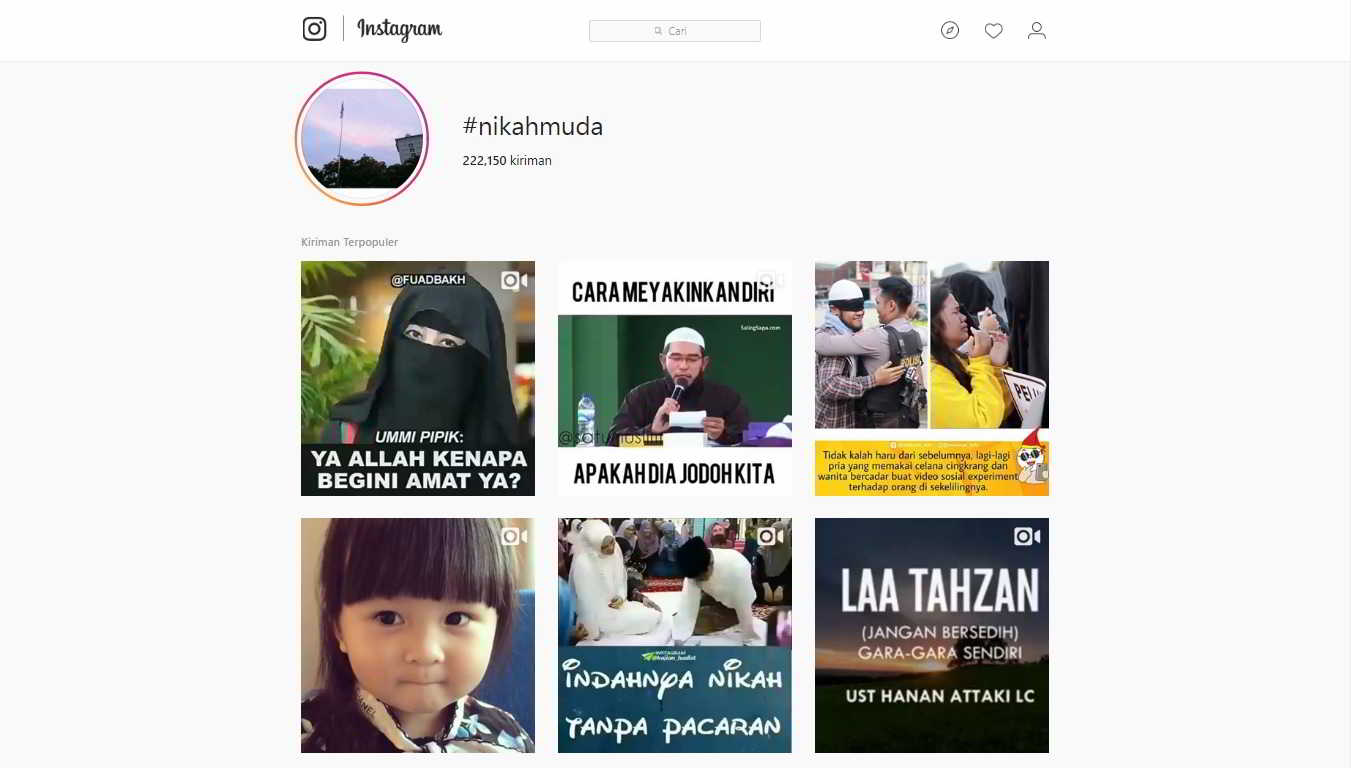Hari Ibu, Gandari, dan Perempuan di Ruang Publik
Kita lihat hari ini, perempuan terus hadir di ruang publik dengan keberanian yang tenang. Merayakan Hari Ibu, kita diajak melihat sejarah akan keberanian perempuan dan perannya di masa silam.

Peringatan Hari Ibu 22 Desember kerap menjadi perayaan yang hangat dan personal. Ia dipenuhi ungkapan terima kasih, kenangan masa kecil dan kisah pengorbanan seorang ibu. Romantisme sentimental hadir dalam memori tentang ibu.
Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi persoalan muncul ketika pemaknaan Hari Ibu berhenti di sana sehingga seolah-oleh peran perempuan (ibu) memang ada di sana, di lingkup domestik.
Padahal, dalam perspektif kultural maupun sejarah nasional, perempuan tidak selalu berada di pinggir dinamika. Hari Ibu di Indonesia justru lahir dari keberanian perempuan memasuki ruang publik dan berpikir politis tentang kehidupan bersama.
Hari Ibu ditetapkan sebagai penanda Kongres Perempuan Indonesia 1928 di Yogyakarta. Kongres ini bukan pertemuan simbolik, melainkan ruang diskusi yang mempertemukan perempuan dari berbagai latar belakang sosial dan ideologis. Mereka membicarakan isu pendidikan, kemiskinan, perkawinan anak, kesehatan, kolonialisme, hingga masa depan bangsa.
Dalam konteks itu, perempuan tampil sebagai subjek politik yang sadar akan kondisi struktural yang menindas dan merasa perlu mengambil bagian dalam perubahan. Maka, Hari Ibu sejatinya adalah monumen keberanian perempuan berpikir dan bersikap di ruang publik.
Figur Etis Politik
Untuk membaca ulang semangat ini secara kontekstual, cerita pewayangan menyediakan lensa yang kaya dan reflektif. Salah satu tokoh yang relevan adalah Dewi Gandari dalam kisah Mahabharata versi Jawa.
Gandari sering kali dipahami sebagai ibu dari seratus Kurawa atau sebagai simbol tragedi. Tapi lebih dari itu, Gandari adalah figur etis-politik yang kompleks. Keputusannya untuk menutup mata setelah menikah dengan Drestarastra bukanlah bentuk kepasrahan, melainkan tindakan simbolik yang menyimpan kritik mendalam terhadap kekuasaan.
Dengan menutup mata, Gandari menolak menikmati kenyamanan istana yang dibangun di atas ketimpangan dan kekerasan. Ia memilih berada dalam kesadaran gelap sebagai sebuah laku batin yang mencerminkan penolakan moral terhadap sistem yang tidak adil.
Gandari hidup di pusat kekuasaan Hastinapura, menyaksikan langsung bagaimana politik dijalankan melalui intrik, kekerasan, dan pengabaian nilai kemanusiaan. Namun sebagai perempuan, ruang geraknya dibatasi. Dalam kondisi inilah, sikap etis Gandari menjadi bentuk politik non-formal yang justru sangat kuat.
Gandari bukan figur domestik yang pasif. Ia adalah perempuan yang mengetahui dampak keputusan politik terhadap kehidupan banyak orang. Ia memahami bahwa perang Bharatayudha bukan sekadar konflik keluarga, tetapi pertarungan nilai yang akan menghancurkan tatanan sosial.
Dalam banyak versi pewayangan, ratapan Gandari setelah kematian anak-anaknya bukan sekadar kesedihan seorang ibu, melainkan kritik keras terhadap sistem kekuasaan yang melahirkan kekerasan berlapis. Gandari berbicara sebagai subjek moral yang menuntut tanggung jawab sejarah.
Logika Gandari ini sejajar dengan sejarah Hari Ibu di Indonesia. Perempuan pada Kongres 1928 hidup dalam struktur kolonial yang timpang dan patriarkal. Mereka tidak memegang senjata, tidak menduduki jabatan resmi, tetapi memiliki kesadaran politik dan keberanian etis.
Mereka memahami bahwa diam berarti membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Seperti Gandari, mereka mengambil posisi, bukan demi ambisi pribadi, melainkan demi keberlangsungan hidup bersama.
Sayangnya, seiring waktu, makna politik Hari Ibu mengalami pelunakan. Ia direduksi menjadi perayaan personal yang sentimental dan nostalgik. Ibu dipuja karena kesabaran dan pengorbanannya, bukan karena keberanian perempuan yang berpikir dan bersikap.
Perempuan yang bersuara di ruang publik sering dianggap tidak tahu diri, terlalu emosional, atau melanggar norma keibuan. Pola ini serupa dengan cara Gandari kerap disalahkan atas kehancuran Kurawa, tanpa memahami struktur kekuasaan yang menjebaknya.
Konteks Hari Ini
Jika ditarik ke konteks hari ini, logika Gandari justru menemukan relevansi yang kuat. Medan konflik memang berubah, tetapi ketidakadilan tetap ada. Maka perempuan, yang banyak di antaranya adalah ibu, hadir di garis depan berbagai perjuangan sosial.
Kita melihat ibu-ibu dalam Aksi Kamisan yang berdiri diam di depan Istana Negara, menuntut keadilan atas pelanggaran HAM berat. Dengan tubuh yang menua, mereka menjaga ingatan kolektif agar tidak dihapus oleh waktu dan kekuasaan. Mereka tidak berteriak, tetapi kehadiran mereka adalah sikap politik yang tegas.
Kita juga menyaksikan ibu-ibu Kendeng yang menolak tambang semen. Mereka membaca ancaman ekologis bukan sebagai isu abstrak, melainkan sebagai persoalan hidup-mati bagi generasi mendatang.
Ketika negara berbicara dengan bahasa pembangunan, mereka menjawab dengan bahasa tubuh, keteguhan, dan keberanian. Seperti Gandari, mereka berada dalam sistem yang timpang, namun memilih bersikap daripada diam.
Maka, refleksi atas Hari Ibu hari ini menjadi penting. Apakah kita merayakan ibu sebagai subjek yang berpikir, memilih, dan mengambil risiko, atau sekadar sebagai simbol moral yang menenangkan? Apakah perayaan Hari Ibu memberi ruang bagi keberanian perempuan di ruang publik, atau justru menutupinya dengan romantisasi domestik?
Nilai kemanusiaan universal yang ditawarkan kisah Gandari adalah empati, tanggung jawab moral, dan kesadaran struktural. Gandari mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu hadir dalam bentuk heroisme yang keras, tetapi juga dalam kesetiaan pada sikap etis di tengah keterbatasan. Nilai ini penting di dunia yang kerap menyederhanakan persoalan dan menghakimi individu tanpa memahami konteks.
Mengontekstualisasi Hari Ibu berarti mengembalikannya pada akar sejarah dan semangat kemanusiaannya. Hari Ibu bukan sekadar hari pujian dan bunga, melainkan pengingat bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menjaga, mengkritik, dan membayangkan masa depan bersama.
Seperti Gandari dan perempuan Kongres 1928, perempuan hari ini terus hadir di ruang publik dengan keberanian yang tenang namun menentukan. Merayakan Hari Ibu secara kontekstual berarti mengakui dan melindungi keberanian itu sebagai bagian dari etika kehidupan bersama yang adil dan manusiawi.