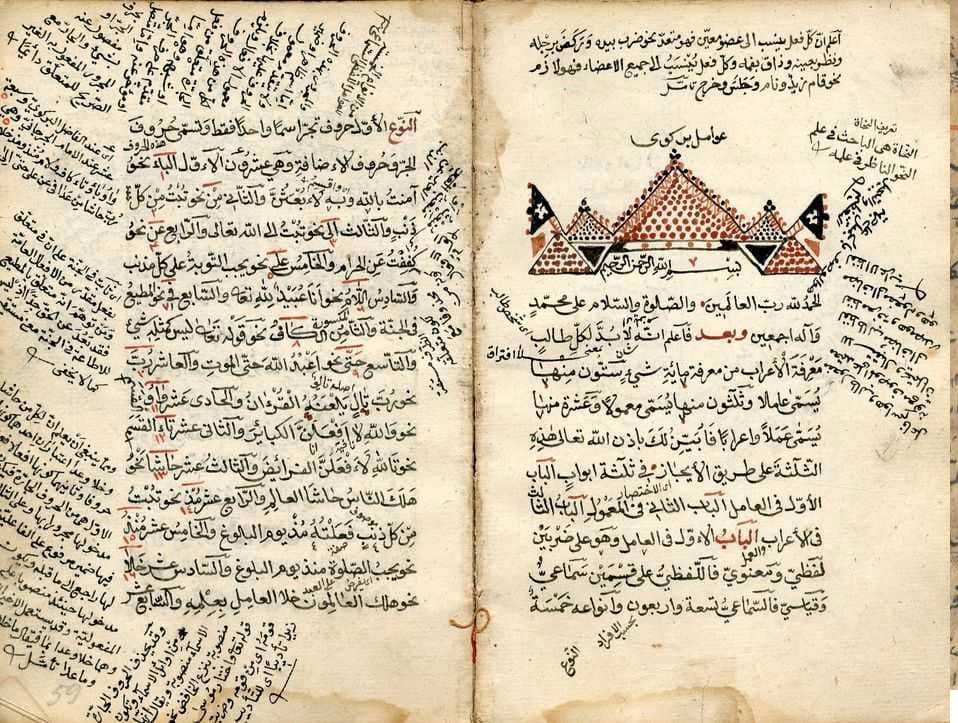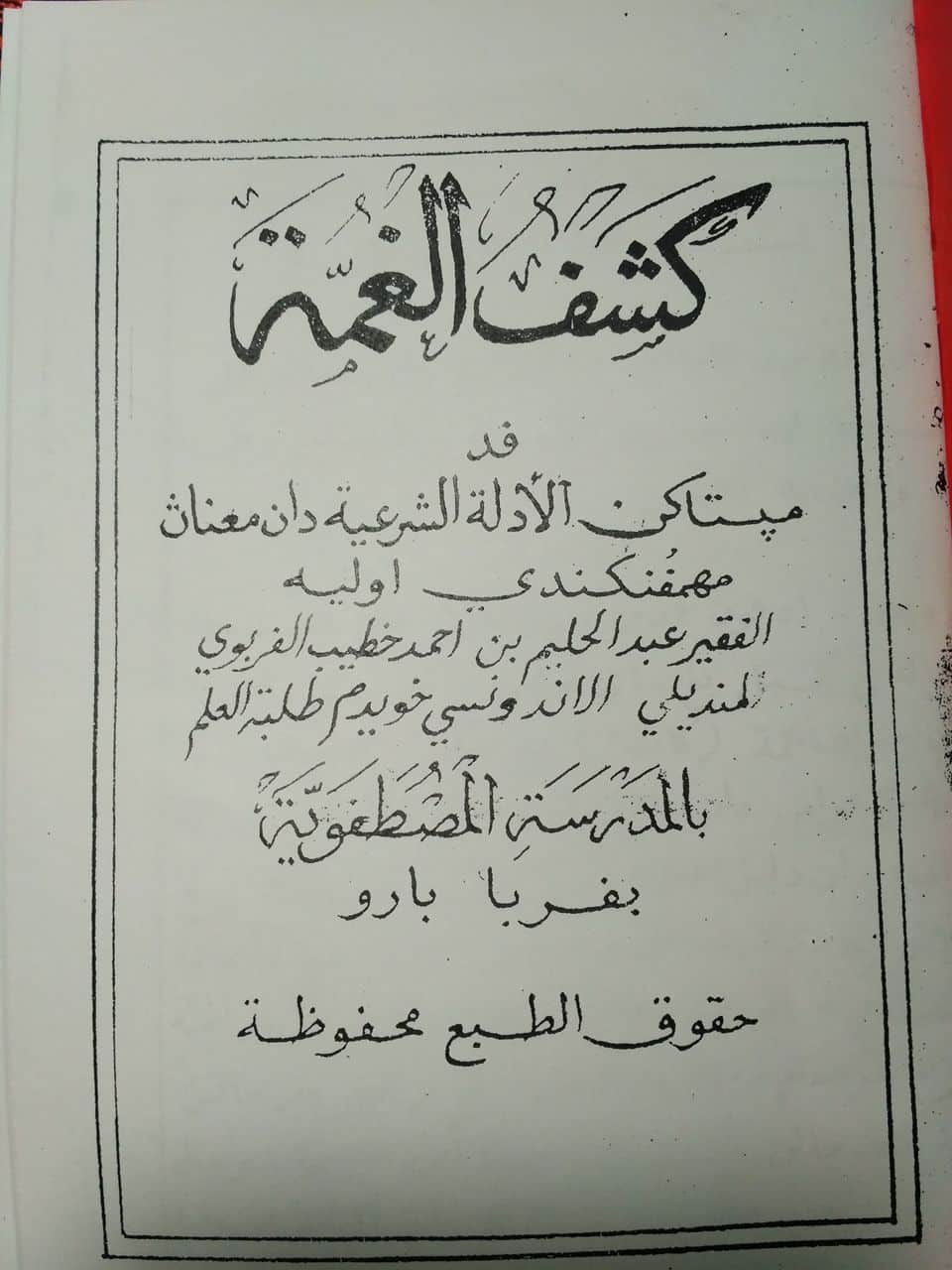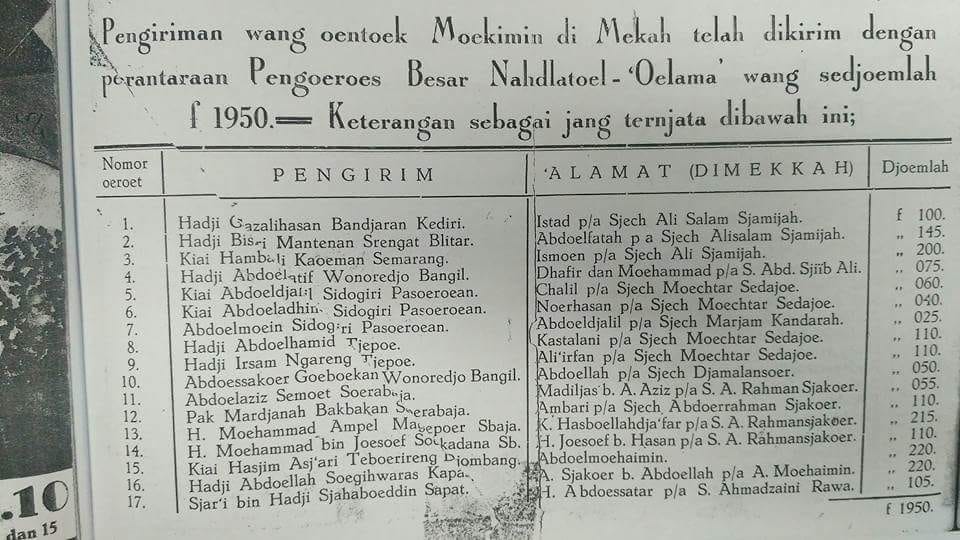Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad dimulai dengan satu kata sederhana namun penuh makna: iqra’. Perintah ini, dalam tradisi tafsir Islam, bukan sekadar ajakan untuk mengeja huruf, tetapi sebuah mandat yang pada akhirnya kemudian akan menyusun peradaban. Ia berarti membaca peristiwa, membaca dunia, membaca sejarah dan membaca tanda-tanda zaman untuk menyusun makna.
Pemikir Islam kontemporer Pakistan Fazlur Rahman Malik (1919–1988) menyebut iqra’ sebagai “kerja intelektual yang melibatkan kesadaran moral”. Ini karena membaca tidak pernah netral. Ia selalu menuntut manusia untuk memahami lalu bertanggung jawab atas pemahamannya. Membaca menjadi tindakan spiritual—sebuah ibadah pengetahuan sekaligus fondasi etika modernitas.
Ketika pemerintah hari ini mewajibkan siswa membaca buku dan menulis resensi (Harian Kompas, 20/11/2025), kebijakan itu secara sekilas tampak selaras dengan spirit iqra’. Tetapi persoalannya tidak sesederhana itu.
Membaca dalam tradisi Islam dan budaya Nusantara adalah tindakan yang menuntut ketekunan, kesungguhan, kontinuitas dan pengendapan makna. Sementara di dunia yang serba cepat seperti saat ini, membaca kerap direduksi menjadi sekadar aktivitas teknis untuk memenuhi tugas.
Terlebih dengan aktivitas harian yang dipenuhi dengan aktivitas scroll-scroll konten apa saja yang ada di gawai setiap orang. Dengannya, kita perlu menguji apakah kebijakan ini benar-benar menghidupkan semangat iqra’, atau justru memperdalam krisis literasi yang dikhawatirkan selama ini.
Antropologi Nusantara
Dalam antropologi budaya Nusantara, membaca dunia diterjemahkan dalam tiga konsep penting yaitu niteni, eling, dan waspada. Ki Hadjar Dewantara, dalam gagasan pendidikan kulturalnya, berulang kali menekankan pentingnya niteni berupa kemampuan memperhatikan dengan teliti, menangkap pola dari pengalaman, dan memaknai gejala secara perlahan. Ini merupakan kerja intelektual yang mirip dengan hermeneutika yaitu menyimak, menafsir, dan merangkai makna dari peristiwa-peristiwa yang terjadi.
Eling, bagi masyarakat Jawa, adalah kesadaran reflektif berupa kemampuan menghadirkan kembali pengetahuan untuk memahami situasi kekinian. Sementara waspada berkaitan dengan kepekaan moral atas peristiwa.
Dalam konteks ini, dengannya, membaca tidak hanya untuk tahu, tetapi untuk berjaga dari kesalahan, manipulasi, dan arus zaman yang menyesatkan. Ketiga prinsip ini sangat dekat dengan makna luas iqra’ yaitu membaca sebagai proses spiritual dan kultural yang utuh, bukan keterampilan mekanis.
Saat pemerintah mewajibkan resensi, tujuan resminya adalah meningkatkan minat baca dan kemampuan berpikir kritis. Namun pendekatan top–down dan serba administratif mengandung risiko. Paulo Freire dalam Pendidikan Kaum Tertindas (2019) mengkritik sistem pendidikan yang hanya menekankan pengumpulan informasi tanpa pemaknaan sebagai “pendidikan gaya bank,” tempat siswa diperlakukan seperti wadah kosong yang perlu diisi.
Membaca dan menulis resensi bisa jatuh pada kondisi yang seperti itu di mana ia hanya menjadi produk tugas yang harus disetorkan, bukan pengalaman pembacaan yang membentuk kedalaman logika dan kepekaan rasa. Jika literasi diperlakukan sebagai target kuantitatif (berapa buku yang berhasil diselesaikan dalam seminggu) maka hilanglah perlahan makna niteni, eling, dan waspada yang esensial dalam membaca.
Bukan Proses Intelektual
Terlebih di era sekarang ini, kecepatan informasi mempengaruhi cara kita memahami dunia. Nicholas Carr dalam The Shallows: Internet Mendangkalkan Cara Berpikir Kita? (2011) menjelaskan bagaimana internet mendorong pola pikir yang serba instan, membuat manusia kehilangan kemampuan untuk melakukan deep reading. Kita menjadi “pengguna informasi,” bukan pembaca.
Di media sosial, opini viral sering dianggap lebih penting daripada proses memahami teks. Anak muda terbiasa mengonsumsi potongan informasi ketimbang merenungkan satu gagasan secara mendalam. Ketika budaya ini meresap ke sekolah, membaca buku dan menulis resensi bisa berubah menjadi sekadar formalitas untuk memenuhi tuntutan kurikulum, bukan proses intelektual yang memupuk kedalaman berpikir.
Padahal membaca membutuhkan waktu, ruang, dan infrastruktur. Banyak sekolah masih kekurangan perpustakaan, buku bermutu, serta guru yang terlatih mendampingi proses literasi. Ekosistem yang timpang ini membuat kebijakan wajib resensi berpotensi menjadi beban tambahan bagi sekolah tanpa menghasilkan perubahan bermakna.
Lebih jauh, literasi harus dipahami sebagai ekosistem sosial. Bukan hanya interaksi individu dengan teks, tetapi relasi antara guru, komunitas, penerbit, dan kebijakan publik. Antonio Gramsci (2013) menekankan pentingnya institusi budaya dalam pembentukan hegemoni.
Literasi yang sehat bukan hanya soal distribusi buku, tetapi soal pembentukan kebiasaan membaca yang memberi ruang bagi wacana alternatif. Komunitas baca, pojok literasi, dan perpustakaan hidup dapat menjadi jembatan antara kebijakan formal dan praktik kultural yang otentik.
Dalam konteks iqra’ (tidak hanya kewajiban membaca dan menulis resensi), negara memiliki tanggung jawab moral untuk menyediakan ruang dan kondisi yang memungkinkan kegiatan membaca berjalan secara otentik. Menyuruh anak membaca tanpa menyediakan akses buku yang layak ibarat memerintahkan orang berpuasa tanpa memberi mereka kesempatan untuk makan yang cukup sehari sebelumnya.
Di tengah kondisi semacam ini, literasi berisiko menjadi ritual simbolik yang dilakukan untuk memenuhi instruksi, bukan karena kebutuhan intelektual. Dalam tradisi keilmuan Islam, membaca selalu dikaitkan dengan proses tadabbur (merenungkan) dan tafaqquh (memahami secara mendalam).
Sementara dalam tradisi budaya Jawa, membaca tanda zaman membutuhkan niteni yang seksama dan eling yang bening. Keduanya tidak mungkin hadir jika membaca dipaksa mengikuti ritme cepat yang ditentukan kebijakan. Yang lahir hanyalah generasi yang terbiasa menyalin ringkasan, bukan menulis tafsir.
Inti Literasi
Meski demikian, kebijakan pemerintah tetap dapat menjadi peluang. Jika diiringi dengan pendampingan literasi yang tepat, membaca dan menulis resensi bisa menjadi latihan membentuk penalaran, bukan sekadar tugas sekolah. Guru dapat memberikan pertanyaan pandu yang bersifat reflektif: apa pengalaman yang berubah setelah membaca? gagasan apa yang paling mengusik? bagaimana buku itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari?
Literasi tidak boleh dipahami sebagai akumulasi halaman yang telah dibaca, tetapi sebagai proses. Membaca adalah kerja kehati-hatian sebagai praktik eling dan waspada dan menuntut kesabaran yang bertentangan dengan ritme zaman. Ia melatih kesadaran, bukan hanya kemampuan akademik.
Ketika pemerintah memaksakan literasi dalam bentuk laporan atau resensi, risiko terbesarnya adalah hilangnya roh membaca itu sendiri. Kita tidak butuh generasi yang pandai membuat ringkasan, tetapi generasi yang mampu membaca dan mengendapkan makna, memahami dan memaknai realitas sosial, membedakan kebenaran dari kebisingan, serta menafsir tanda-tanda zaman dengan jernih, sebagaimana diperintahkan melalui iqra’.
Karena membaca adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara teks dan kehidupan, antara agama dan kebudayaan. Kita perlu membangun kebijakan literasi yang tidak hanya mengisi otak, tetapi juga mempertajam batin.
Membaca harus dikembalikan pada kehormatannya sebagai tindakan spiritual dan kultural. Jika tidak, ia akan berubah menjadi rutinitas sekolah yang hambar. Spirit iqra’, jika disatukan dengan etos niteni–eling–waspada, sebetulnya menawarkan satu pesan sederhana tetapi mendalam yaitu membaca adalah cara manusia merawat kejernihan hidup. Itulah yang seharusnya menjadi inti dari kebijakan literasi kita hari ini.