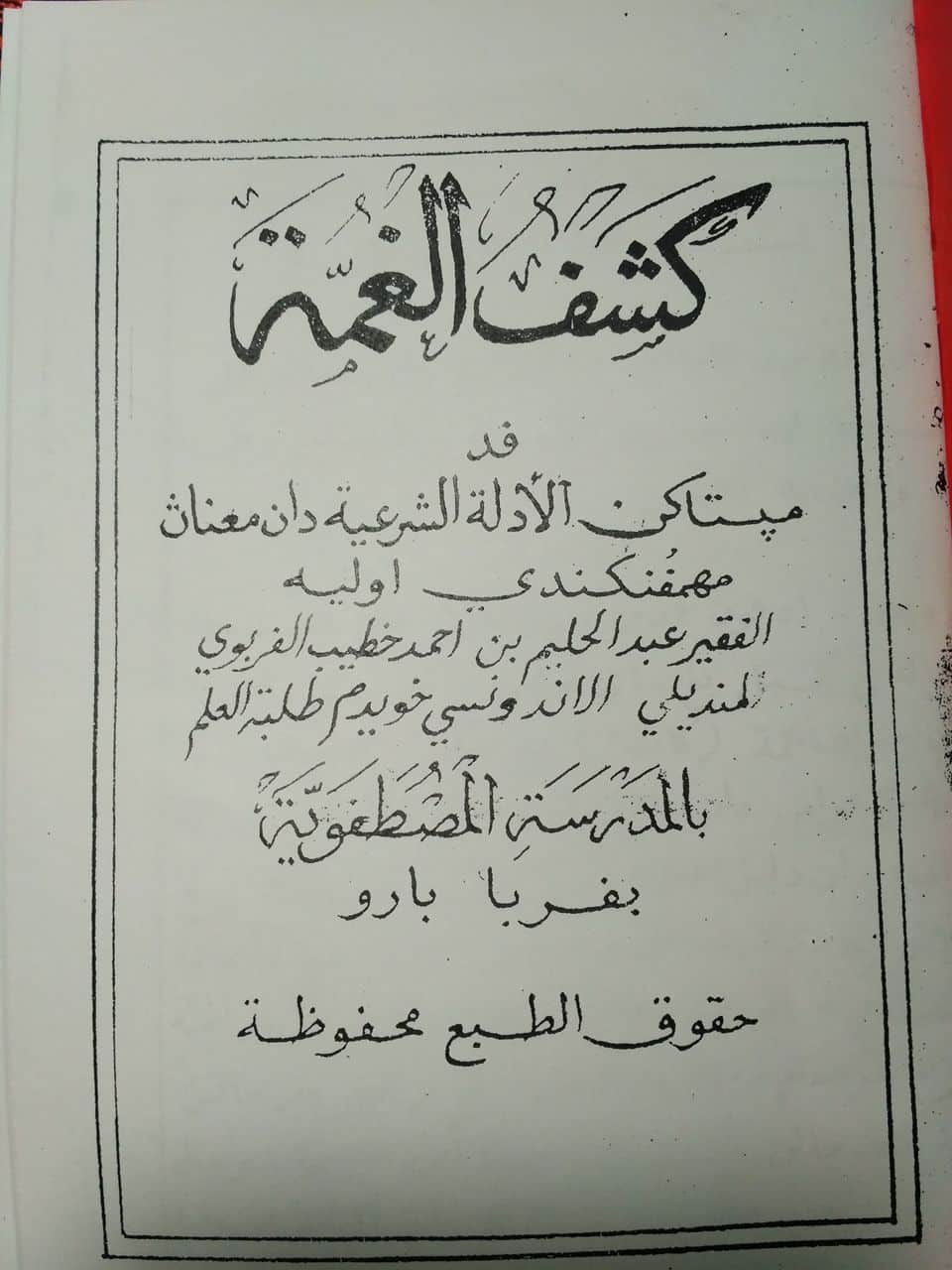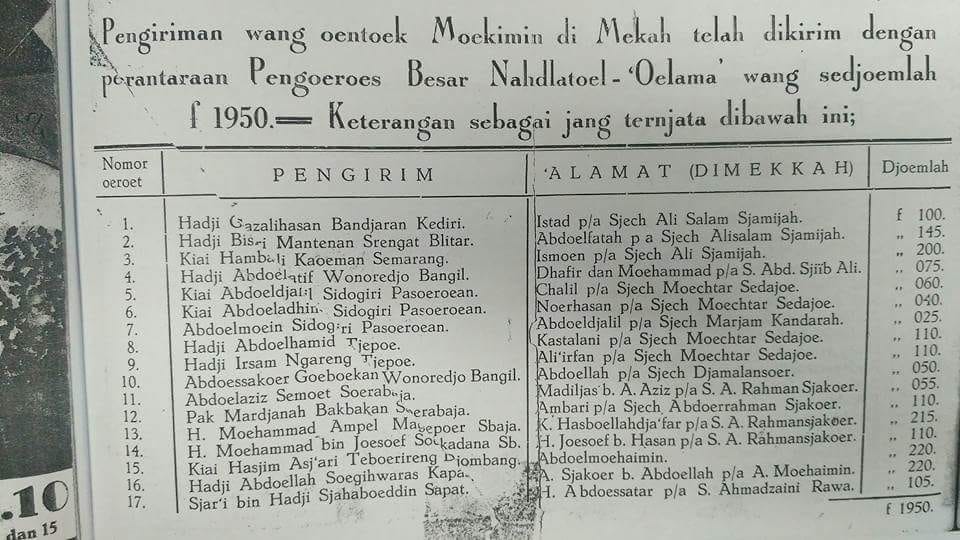Kita Masih Perlu Mendongeng
Mendongeng telah melatih nalar anak-anak dalam berimajinasi. Apalagi sekarang adalah era gadget, lebih berat daripada era televisi.

Televisi pernah menapaki babak awal kehidupan, merangsek di ruangan keluarga-keluarga di Indonesia. Para keluarga bersuka cita, gembira, dan penuh perhatian. Mereka menaruh fokus pada tayangan demi tayangan untuk mengisi waktu-waktu luang dalam keseharian. Televisi memberi ketersambungan para keluarga kepada ide-ide global. Baik berupa gaya hidup, makanan, pakaian, hingga hiburan.
Akan tetapi, tak dapat kita tampik, para keluarga juga menghadapi masalah—saat televisi menjelma menjadi benda yang terlampau menguasai pikiran. Televisi terlalu mendominasi itu adalah sebuah masalah. Gangguan-gangguan itu menjadi syarat merenungi situasi dan kondisi. Di surat kabar dan majalah, para pakar hadir membawa penjelasan untuk mengurai permasalahan.
Acuan tersebut setidaknya pernah dimunculkan dalam Majalah Femina edisi 2 Agustus 1979. Di sana kita temukan artikel berjudul “Mendongeng lebih bagus dari pada anak-anak Nonton TV”. Judul memberi peringatan. Televisi telah menemui masalah. Pihak majalah masih berpamrih terhadap buku-buku bacaan sebagai perhatian keluarga dalam menapaki kehidupan. Di artikel, kita mendapati penekanan mengenai dongeng.
Penjelasan terdapat dalam artikel: “Orang tua yang biasa membacakan cerita bagi anak-anaknya pasti akan memperhatikan bahwa anak-anak mereka senang sekali bila mendapat perhatian dari orang dewasa. Dan juga bahwa sebetulnya mereka lebih senang bila bersama-sama mendengarkan sebuah cerita sebuah cerita yang dibacakan bagi mereka daripada secara pasif menjadi penonton TV.”
Pada masanya, keterangan-keterangan mendongeng masih kita dapat. Keberadaan majalah memiliki misi bertemu dengan para keluarga Indonesia. Majalah Intisari pernah menerbitkan sekian artikel yang pernah dimuat dalam tema-tema keluarga dan anak menjadi buku. Buku itu berjudul Kumpulan Artikel Psikologi Anak 2 (1999). Artikel berjudul “Mendongeng itu Perlu” membuat kita merasa penting akan keberadaan dongeng.
Keterangan penting kita kutip: “Mendorong anak gemar terhadap dongeng memang bermuara pada peran aktif orang tua sejak dini, yakni sejak anak berusia 3 tahun. Pada usia itu anak sudah mampu mengingat dengan kuat, sehingga kemesraan dan cinta kasih yang dirasakan ketika Anda membacakan dongeng untuknya akan diingat sepanjang hayat.”
Baca Juga:
Bila Santri Melepas KangenDongeng menyiratkan keterhubungan terhadap buku-buku bacaan, cerita lisan, dan cerita rakyat. Dari ruang-ruang keluarga, dongeng juga menyangkut fungsi akan pendidikan. Orangtua dan guru memiliki tanggungan terhadap telinga-telinga para bocah. Pada 2024, kita masih diajak berpikir mengenai dongeng. Di Harian Kompas edisi 12 September 2024, terdapat liputan berjudul “Guru PAUD Harus Bisa Mendongeng”.
Dongeng masih menjadi fondasi jalan kehidupan mutakhir, kendati televisi sudah tak begitu memberi tantangan, sebab kini yang kita hadapi bersama adalah dominasi dari perkembangan dunia digital. Dijelaskan dalam liputan: “Kemampuan bercerita atau mendongeng seorang guru di tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan faktor penting untuk pengembangan kognitif dan emosional anak.”
Peletakan dongeng sebagai tanggung jawab guru menarik ditelisik, terlebih merefleksikan sekian masalah dalam hiruk-pikuk dunia pendidikan. Sederet masalah masih kerap mewarnai. Mulai perundungan, kekerasan, hingga intoleransi. Kesemuanya menjadi tantangan bersama di dalam narasi kebangsaan. Itu tak terlepas akan gejala-gejala yang saling berkelindan atas dinamika kehidupan digital yang ditopang keberadaan media sosial.
Konon banyak pihak terlalu menyerahkan diri pada rutinitas hidup dengan dikendalikan teknologi digital. Kait kelindan itu memicu keterbukaan yang justru mudah menyelinap pada situasi kebablasan. Pengendalian diri terhadap teknologi digital menjadi sulit. Keluarga-keluarga kadang mudah patuh atas kehendak anak-anaknya dalam menggerakkan tubuh terhadap teknologi digital.
Apa yang menjadi masalah? Masalah itu adalah terdapat ketidakhadiran interaksi antara satu dengan lainnya yang justu melahirkan paradoks. Alih-alih teknologi digital membuat kita yakin akan perkembangan kecerdasan dalam berbagai hal, nyatanya ada ruang yang tak pernah disentuh. Itu tentu saja berhubungan dengan tradisi bercerita, percakapan akan keilmuan, hingga pewarisan cerita dalam bentuk dongeng sebagai latihan imajinasi.
ST. Kartono adalah guru yang rajin dalam membuat tulisan-tulisan kepada publik. Ia pernah menulis buku berjudul Menjadi Guru untuk Muridku (Kanisius, 2011). Ia pamrih dalam berbagi pengalaman dalam kegiatan mengajar, cara mengajak murid sadar terhadap ilmu, hingga menyoal kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan. Di buku tersebut, ia juga menyoal bagaimana peranan guru yang perlu mendongeng bagi murid-muridnya.
Ia justru menggarisbawahi bahwa harapan orang tua mau mendongeng pada anak-anaknya menjelang tidur hanya berandai-andai. Yang kemudian ditekankan adalah keberadaan guru dengan menyinggung proses menjadi guru. Jelasnya: “Menghadirkan para guru sekolah dasar yang pintar mendongeng adalah sebuah upaya sistematis, bukan berandai-andai. Hal itu dimulai sejak para mahasiswa menyiapkan diri akan menjadi guru.”
Materi yang perlu diajarkan saat kuliah adalah mendongeng. Penjelasan tambahan: “Pengetahuan dan pengalaman mendongeng kiranya akan menjadi inspirasi untuk berbuat serupa kelak mengasuh murid sekolah dasar.” Kini kita masih menaruh harap pada dongeng, baik di ruang keluarga maupun sekolahan. Dongeng itu memuat imajinasi, melatih bernalar, mendekatkan pada pengetahuan, dan menuntun diri terhadap bacaan-bacaan.[]