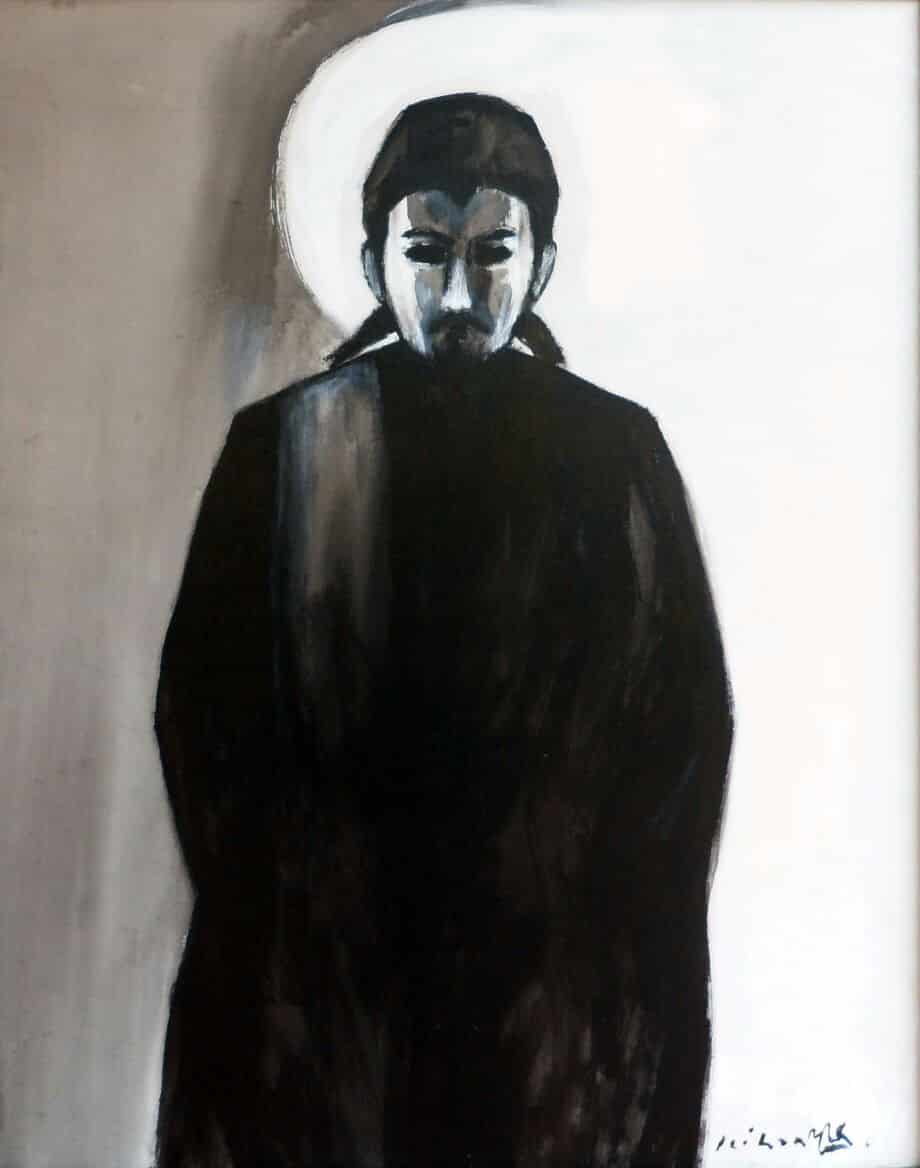Pesantren di Layar Televisi: Antara Rating, Fakta, dan Jurnalisme Damai
Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Kini ramai orang membicarakan pesantren, termasuk perannya supaya bisa masuk ke layar kaca dan memberikan tontonan yang menyejukkan.

Dorothy G. Singer (2003: 2) dalam Television and its Potential for Imagination menilai jika khalayak yang menonton program televisi akan menurun ketika tidak ada kreativitas dan imajinatif dalam konten yang disajikan.
Apakah televisi-televisi pernah berpikir untuk menyampaikan kebenaran? Apakah yang dipikirkan hanya rating? Tim redaksi menilai jika semakin tinggi rating, maka semakin berani untuk membuat program televisi. Meskipun menabrak tatanan sosial dan membuat kerunyaman antar sesama anak bangsa karena telah mendapat keuntungan dari konflik yang dibuatnya.
Televisi swasta nasional yang telah menggemparkan tatanan sosial terkait pesantren seharusnya memanfaatkan digitalisasi untuk mengetahui lebih dekat dengan keinginan positif penonton. Olaf Acker dkk (2013: 33) dalam The Digital Future of Creative Europe; The Impact of Digitization and The Internet on The Creative Industries in Europe menyebutkan jika digitalisasi memberikan kesempatan kepada orang-orang kreatif untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen mereka, belajar lebih banyak tentang pilihan konsumen serta menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen.
Tim redaksi program televisi harus melakukan riset untuk membuat konten yang disenangi oleh penonton. Apa mungkin televisi swasta nasional tersebut tidak melakukan riset untuk membuat program acara yang akhirnya menyinggung tradisi pesantren?.
Pesantren terbuka untuk siapa saja. Dilihat dari sejarah, sebagaimana menurut Ahmad Baso (2013: 7-8) dalam bukunya yang berjudul “Agama NU untuk NKRI” menegaskan jika ulama pesantren terbuka dengan siapa pun, baik komunis ala PKI, reformis ala Muhammadiyah hingga nasionalis ala PNI, bahkan tokoh PNI sendiri, Ir. Soekarno berguru ke ulama pesantren.
Konten Televisi Edukatif
Jika berpikir praksis dalam konteks apapun, tradisi pesantren dalam program acara televisi swasta nasional ini dideskripsikan tidak dengan sebenarnya. Pertama, santri yang memberikan amplop kepada kiai dianggap salah. Padahal itu tradisi tulus. Bukan sogokan. Tapi bentuk terima kasih santri kepada kiai yang telah berjasa dalam hidupnya. Kedua, memandang negatif kepada kiai dengan kehidupan mapan. Sebab menumpuk amplop dari santri. Padahal banyak kiai yang memiliki sawah dan perkebunan luas serta bisnis halal bahkan memberi nafkah kepada banyak orang termasuk para santrinya.
Ketiga, mengambil potongan video dari pondok besar yang berdiri tahun 1910 M, saat Negara Indonesia belum merdeka, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Pondok yang sudah melahirkan banyak orang hebat yang telah berbakti untuk bangsa ini.
Jika dilihat dari sejarah, momentum kesadaran berbangsa dan bernegara serta moderasi beragama ulama pondok pesantren dilaksanakan melalui wadah bernama Nahdlatul Ulama sebagai jalur strukturalnya. Misalnya fatwa Muktamar NU tahun 1936 di Banjarmasin tentang kewajiban membela tanah air (Hindia Belanda yang kelak menjadi Indonesia) walaupun dengan penguasa non-muslim.
Selain itu, Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya dan Muktamar NU 1984 di Situbondo dengan penegasan kembali penerimaan NU atas Pancasila sebagai ideologi bangsa (Wasid Mansyur, 2014: 10). Artinya pondok pesantren sudah terbukti memiliki nasionalisme tinggi untuk negara ini.
Ketiga pandangan negatif program acara televisi swasta nasional itu disebabkan karena memandang dari sudut pandang luar terhadap pesantren. Coba lakukan riset dan observasi mendalam agar lahir program televisi yang edukatif dan berdasarkan fakta. Padahal yang terpenting adalah program televisi berkualitas harus memiliki nilai-nilai pembelajaran dan pendidikan.
Program yang mengandung substansi moral dan keislaman amat penting, apalagi jika dihubungkan dengan peran televisi sebagai sarana edukasi dan pembentukan karakter masyarakat. Sehingga tidak ada lagi program televisi yang tidak bermanfaat untuk kehidupan masyarakat relijius (Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Kedaulatan Frekuensi; Regulasi Penyiaran, Peran KPI dan Konvergensi Media, 2013: 15-17).
Peace Journalism untuk Kesejukan Penonton
Televisi di Indonesia harus tampil beda dengan televisi di negara lainnya dalam penulisan berita. Jika televisi luar negeri bisa menggunakan pendekatan konflik atau jurnalisme perang (war journalism), maka televisi dalam negeri seharusnya berani menggunakan pendekatan atau jurnalisme damai (peace journalism).
Akibatnya orang yang melihat, mendengarkan dan menikmati pemberitaan akan menjadi cerdas. Peace journalism memberikan penjelasan yang seimbang antara pemberitaan yang salah dan yang benar dengan disertai bukti, sehingga khalayak tidak menyimpulkan sendiri.
Dasar pemikiran normatif peace journalism adalah jika media memainkan peran negatif dalam meningkatkan ketegangan antara pihak-pihak yang sedang berkonflik, maka mereka juga dapat memainkan peran positif dengan mempromosikan perdamaian.
Pertanyaannya adalah, haruskah media mempromosikan perdamaian? Jika ya, bagaimana kita bisa membuat mereka melakukan hal demikian? Suleyman Irvan (2006: 34) dalam Peace Journalism as a Normative Theory: Premises and Obstacles berpendapat bahwa, media harus terlibat dalam promosi perdamaian, terlepas dari kerugian terkait dengan promosi perdamaian.
Jake Lynch (2006: 75) dalam What’s so Great About Peace Journalism? mengutip model Galtung yang menjelaskan bahwa war journalism adalah propaganda-orientated (berorientasi pada propaganda), sedangkan peace journalism, sebaliknya yaitu pada truth orientated (berorientasi pada kebenaran). Program acara televisi swasta nasional itu berorientasi pada propaganda untuk menciptakan pandangan negatif kepada pesantren. Akhirnya tatanan sosial terbelah, ada yang pro dan kontra. Inilah jahatnya war journalism dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lebih rinci, Jake Lynch (2007: 2) dalam A Course in Peace Journalism menegaskan jika war journalism mengarahkan pembaca dan penonton untuk mendapatkan nilai kekerasan yang berlebihan, sebagai respon terhadap konflik dan krisis yang terjadi.
Peace journalism juga menciptakan peluang bagi masyarakat luas untuk mempertimbangkan dan menghargai berita yang tidak menampilkan kekerasan sebagai respon terhadap perkembangan. Untuk mengembalikan perkembangan tatanan sosial seperti sedia kala, tim redaksi program televisi itu tidak hanya menghapus dan meminta maaf kepada para pengasuh pesantren, tapi juga membuat program televisi tentang pesantren dengan pendekatan peace journalism. Sekian.