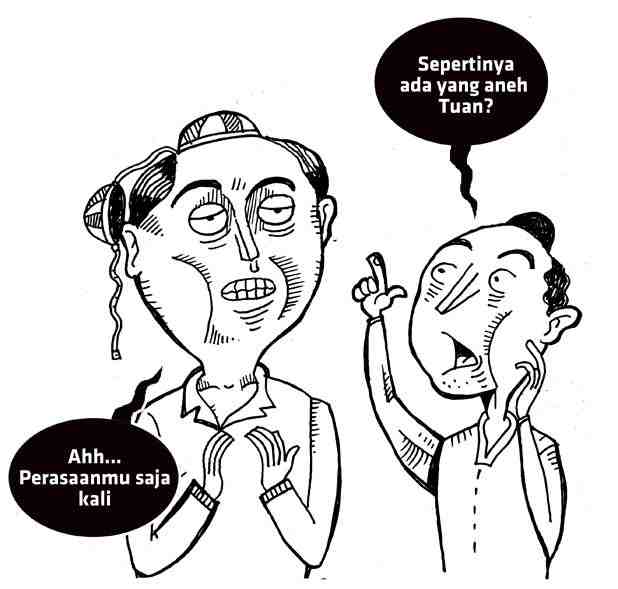Aksi Kamisan sebagai Teologi Sosial
Kamisan adalah wujud dari teologi sosial. Doa yang berubah menjadi tindakan, spiritualitas yang menjelma menjadi perlawanan.

Di depan Istana Negara, setiap Kamis sore, tubuh-tubuh berbaju hitam berdiri diam dengan payung terbuka. Mereka bukan sekadar orang yang menuntut keadilan, tapi mereka adalah ingatan yang menolak dilupakan.
Aksi Kamisan, yang telah berlangsung sejak 18 Januari 2007, bukan demonstrasi biasa, tapi sebuah ritual kebudayaan. Ia adalah sebuah liturgi kemanusiaan yang berlangsung di tengah jantung kekuasaan. Ia menjadi cara warga biasa mengingat bahwa republik ini pernah berdiri di atas luka-luka yang belum disembuhkan.
Ingatan Kolektif
Dalam pandangan kultural, Kamisan adalah bentuk cultural memory—ingatan kolektif yang tidak disimpan di museum atau di lembar arsip negara, tapi di tubuh-tubuh yang hadir di ruang publik. Profesor studi bahasa Inggris dan sastra Jerman, Aleida Assmann (2011) menyebut bahwa cultural memory hidup melampaui institusi formal. Ia bergerak di antara ritus, narasi, dan simbol-simbol sosial. Kamisan mewujudkan itu dengan sederhana: keheningan menjadi bahasa, payung hitam menjadi ikon, dan keberulangan menjadi ingatan.
Di tengah kultur politik yang gemar memproduksi lupa, Kamisan adalah praktik etis yang melawan lupa itu sendiri. Ia bukan sekadar protes terhadap negara, tetapi juga pengingat bagi masyarakat bahwa keadilan bukanlah proyek birokrasi, melainkan kesetiaan moral terhadap kemanusiaan. Di sana, setiap Kamis sore, ibu-ibu korban berdiri dalam kesunyian, membawa wajah anak-anaknya yang hilang, dan menghadirkan makna yang jauh lebih dalam dari orasi mana pun.
Dari sudut pandang performance studies, sebagaimana dijelaskan Richard Schechner dalam Performance Studies: An Introduction (2002), tindakan berulang seperti Kamisan dapat dibaca sebagai ritual of resistance. Tubuh-tubuh yang berdiri diam itu adalah performa politik yang melampaui kata.
Mereka menolak logika protes yang bising dan memilih kesunyian yang menggugat. Dengan itu, Kamisan mendekonstruksi relasi antara rakyat dan negara, karena justru dalam diam, kekuasaan dibuat kehilangan pijakan simboliknya.
Di sisi lain, filsuf feminis Amerika, Judith Butler dalam Gender Trouble (1990) menjelaskan bahwa tindakan yang diulang dapat menghasilkan subversi makna baru. Kamisan, yang dilakukan setiap pekan selama lebih dari satu dekade, telah menjelma menjadi tindakan performatif yang mengguncang struktur makna kekuasaan. Diam di depan istana menjadi bentuk komunikasi spiritual dan politik sekaligus: rakyat tak bersuara karena negara terlalu lama tuli terhadap jeritan mereka.
Ingatan semacam ini adalah bentuk politik ingatan intergenerasional sebagai bentuk penyampaian kesaksian moral dari generasi korban kepada generasi baru. Paul Ricoeur dalam Memory, History, Forgetting (2004) menulis bahwa mengingat selalu terkait dengan “siapa yang berhak menceritakan.”
Dalam konteks Indonesia, negara sering berusaha memonopoli narasi sejarah dengan menentukan siapa korban, siapa pelaku, siapa pahlawan. Kamisan menolak monopoli itu. Ia menghadirkan versi lain dari sejarah, versi yang lahir dari luka dan air mata, bukan dari podium kekuasaan.
Fakta bahwa hingga kini Komnas HAM telah menuntaskan penyelidikan banyak kasus pelanggaran HAM berat—dari Tragedi 1965 hingga Penghilangan Paksa 1997–1998—namun Kejaksaan Agung terus menolak melanjutkannya ke pengadilan (Kompas.com, 13 Januari 2023), menunjukkan bahwa negara memilih melupakan ketimbang menebus kesalahan. Karena itulah Kamisan tidak sekadar aksi, melainkan perlawanan terhadap struktur kenegaraan yang menolak bertobat.
Soal Iman
Namun Kamisan bukan hanya soal politik. Ia juga soal iman. Dalam diam itu, ada doa yang tak diucapkan, ada keyakinan yang dipelihara. Teolog pembebasan Gustavo Gutiérrez dalam A Theology of Liberation (1973) menyebut bahwa iman sejati adalah keberpihakan kepada yang tertindas.
Kamisan adalah wujud dari teologi itu dalam praktik sosial, doa yang berubah menjadi tindakan, spiritualitas yang menjelma menjadi perlawanan. Para ibu yang berdiri setiap Kamis sore tidak hanya menuntut keadilan bagi anak-anaknya, tetapi juga sedang menjalani ziarah panjang atas kemanusiaan.
Religiositas yang hidup dalam Kamisan bukan religiositas formal yang berpusat pada institusi keagamaan, melainkan iman yang lahir dari penderitaan dan cinta. Dalam pandangan ini, mengingat adalah bagian dari ibadah.
Menjaga kenangan para korban adalah bentuk kesetiaan terhadap nilai ilahi dalam diri manusia. Kamisan mengajarkan bahwa beriman tidak hanya berarti percaya pada Tuhan, tetapi juga menolak ketidakadilan yang menistakan ciptaan-Nya.
Keheningan di depan istana adalah bentuk dzikir sosial dalam pengulangan yang menghadirkan kesadaran moral kolektif. Ia mengingatkan bahwa negara tanpa nurani hanyalah mesin kekuasaan. Dalam keheningan itu, spiritualitas dan politik berpadu. Bahwa manusia tidak hanya menuntut hukum ditegakkan, tapi juga agar hati bangsa ini kembali hidup.
Walter Benjamin, dalam Theses on the Philosophy of History (1940), menulis bahwa sejarah yang ditekan akan selalu “meledak kembali” ketika ketidakadilan dibiarkan. Kamisan adalah letupan itu.
Bukan dalam bentuk kekerasan, melainkan dalam bentuk kesetiaan. Kesetiaan untuk terus datang, berdiri, dan diam. Dalam era ketika informasi bergulir begitu cepat, kesetiaan menjadi tindakan yang paling radikal.
Dengan cara itu, Kamisan menjadi semacam doa nasional yang tak pernah selesai. Ia tidak membutuhkan pengeras suara, sebab kekuatannya justru ada pada kelembutan. Ia tidak menuntut ganti rugi, sebab yang dicari adalah pengakuan, pengingatan, dan pemulihan martabat. Kamisan mengajarkan bahwa ingatan adalah cara paling manusiawi untuk menolak kematian kedua berupa kematian dalam ingatan publik.
Mungkin inilah paradoks tersubtil dari Aksi Kamisan. Bahwa dalam sunyi, mereka bersuara paling keras; dalam kelemahan, mereka menunjukkan kekuatan yang tak tertaklukkan; dan dalam iman, mereka menegakkan kemanusiaan. Setiap Kamis sore, di bawah langit yang mungkin mendung, mereka berdiri bukan untuk mengutuk, tetapi untuk menjaga agar bangsa ini tidak kehilangan jiwanya.
Aksi itu bukan hanya ritual politik, tetapi ritual kemanusiaan. Ia menunjukkan bahwa ingatan bisa menjadi jalan keselamatan sosial, sebagai sebuah bentuk pertobatan kolektif bagi bangsa yang telah terlalu lama menunda kebenaran. Kamisan menegaskan keadilan bukanlah milik mereka yang berkuasa, tetapi milik mereka yang setia mengingat.
Di tengah dunia yang kian bising oleh propaganda, hoaks, dan euforia pembangunan, Kamisan menuntun kita kembali ke pusat nurani, ke titik di mana kemanusiaan, iman, dan kebudayaan saling berkelindan. Diam para ibu di depan istana adalah cermin iman yang tak goyah, doa yang tak pernah berhenti, dan janji bahwa kebenaran, betapa pun lama tertunda, akan selalu menemukan jalannya.
Seperti kata Milan Kundera, “perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.” Tugas kita adalah memastikan ia tidak berhenti sebagai simbol, melainkan menjadi energi untuk menuntut keadilan yang nyata.