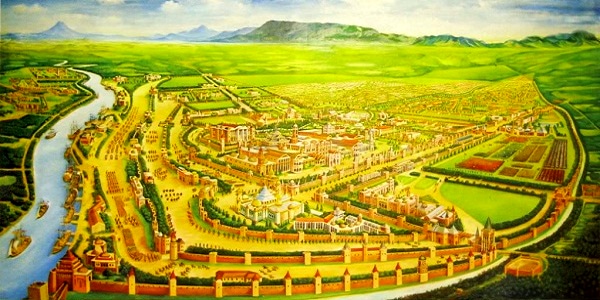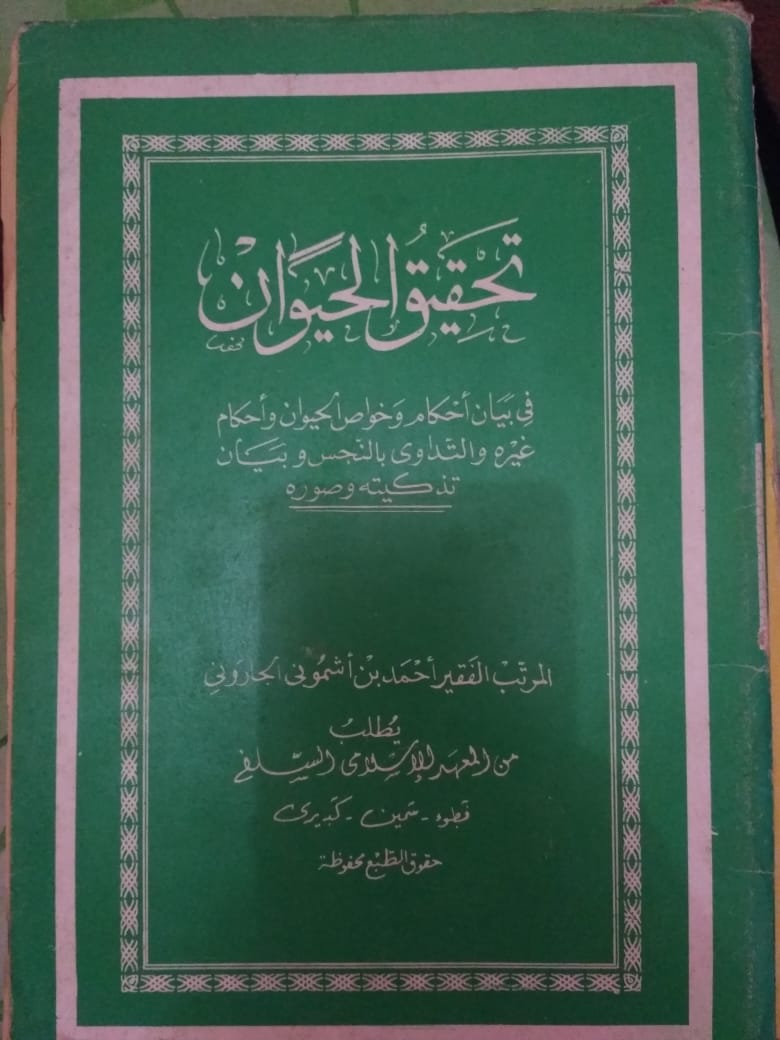Menjadi Hening di Dunia yang Bising: Spiritualitas Zaman Sibuk
Tapa ngrame: menjalani tapa di tengah keramaian, demi keselamatan batin, berbuat kebajikan tanpa pamrih, berperan di tengah masyarakat dengan ilmu dan kesadaran hidup.

Di zaman ketika setiap detik berharga dan setiap bunyi menuntut perhatian, keheningan menjadi kemewahan yang langka. Dunia modern berputar dengan ritme yang tak memberi jeda—pemberitahuan yang berdenting tanpa henti, tenggat yang mengejar, dan layar yang selalu menyala bahkan ketika mata ingin terpejam. Dalam kebisingan semacam itu, manusia kehilangan ruang untuk mendengarkan dirinya sendiri.
Kita hidup, meminjam istilah filsuf kontemporer Korea Selatan Byung-Chul Han, dalam society of fatigue—masyarakat yang lelah oleh dorongan untuk terus produktif, namun miskin kesadaran akan makna keberadaannya (The Burnout Society, 2010, Masyarakat Kelelahan, Marjin Kiri, 2021). Krisis keheningan itu berimbas langsung pada dimensi religius manusia.
Ritual dan ibadah, yang semestinya menjadi jalan perjumpaan dengan yang ilahi, kerap menjelma sekadar rutinitas. Spiritualitas jadi menghadapi ujian terbesarnya: bagaimana menjadi hening di dunia yang bising, bagaimana beriman di tengah hiruk-pikuk yang memecah perhatian, bagaimana tetap hadir sepenuhnya tanpa kehilangan jernihnya batin.
Seperti dikatakan teolog Thomas Merton, “Kita hidup dalam masyarakat yang kehilangan kemampuan untuk duduk diam di kamarnya sendiri.” (Thought in Solitude, 1958). Keimanan berubah menjadi aktivitas sosial, bukan perenungan spiritual. Ia menjadi gema yang berdengung di alam bawah sadar, tapi bukan jadi gema kesadaran dalam perbuatan.
Dalam keseharian, kita beribadah dengan sibuk, berdoa dengan terburu-buru, beragama dengan terfragmentasi. Di tengah kebisingan algoritmik ini, manusia modern sebenarnya sedang mencari sesuatu yang sederhana, berupa sebuah ruang hening untuk menata batin dan mengingat dirinya sebagai makhluk yang rapuh.
Menghidupi Kesadaran
Religiositas di masa kini, karena itu, tidak cukup hanya dimaknai sebagai kepatuhan pada aturan atau ritual. Teolog-filsuf Jerman-Amerika Paul Tillich menyebut agama sebagai ultimate concern—keprihatinan terdalam manusia terhadap makna eksistensialnya (Dynamics of Faith, 1957; Dinamika Iman, Kanisius, 1995). Menurut Tillich, etiap manusia sebenarnya religius — bukan karena semua beragama, tapi karena semua mencari makna terdalam dalam hidupnya.
Sedangkan pemikir lintas iman Karen Armstrong menegaskan bahwa inti dari setiap tradisi keagamaan adalah compassion, kasih yang menembus batas-batas institusional (Twelve Steps to a Compassionate Life, 2010; Dua Belas Langkah Menuju Hidup Penuh Welas Asih, Gramedia Pustaka Utama, 2011).
Dengan demikian, religiositas sejati bukan sekadar soal bagaimana manusia berdoa, melainkan bagaimana ia menghidupi kesadarannya di tengah keseharian yang riuh. Keberagamaan tidak lagi diukur dari seberapa sering kita bersujud, tetapi dari seberapa sadar kita hadir dalam setiap tindakan seperti bekerja, mendengar, menolong, dan mencinta.
Dalam konteks ini, falsafah Jawa menawarkan sesuatu yang terasa relevan yaitu tapa ngrame. Konsep ini, sebagaimana tersirat dalam Serat Wedhatama karya Mangkunegara IV, berbicara tentang kemampuan menjaga laku batin di tengah keramaian dunia.
Tepa-tepa tapa ngrame,
Kinarya mrih rahayu,
Kang tumindak ngamal becik,
Tan mikir saniskara,
Ing ngarsa ana prajurit,
Kinarya mrih kawruh,
Wruhira ing ngaurip.
(Kurang lebih bermakna: Menjalani tapa di tengah keramaian, demi keselamatan batin; berbuat kebajikan tanpa pamrih; berperan di tengah masyarakat dengan ilmu dan kesadaran hidup.)
Berbeda dengan pertapaan asketis yang menjauh dari kehidupan sosial, tapa ngrame justru menuntut seseorang untuk tetap hidup di tengah masyarakat sambil memelihara kejernihan batinnya. Ia bukan bentuk pelarian, tetapi laku kesadaran yang berakar pada keseharian. Dalam tafsir kontemporer, tapa ngrame bisa dibaca sebagai praktik mindfulness Nusantara: keheningan yang tidak menolak keramaian, melainkan hadir di dalamnya.
Gagasan ini bersinggungan dengan apa yang diajarkan Thich Nhat Hanh, biksu Vietnam yang mempopulerkan konsep engaged Buddhism. Bahwa pencerahan bukan hasil menyepi, melainkan hasil kesadaran dalam tindakan. Makan, berjalan, berbicara, bahkan menyapu lantai dapat menjadi laku spiritual bila dilakukan dengan sepenuh kesadaran.
Seperti halnya tapa ngrame, ajaran Thich Nhat Hanh menolak dikotomi antara dunia dan pertapaan. Keduanya menyatu dalam praksis hidup yang berkesadaran. Spiritualitas bukan pelarian, melainkan cara hadir di dunia secara utuh. Dalam pandangan ini, keramaian justru menjadi ladang latihan batin, tempat kita menguji kejernihan dan belas kasih di tengah kekacauan.
Menata Cara Hadir
Filsuf – mistikus Prancis Simone Weil pernah menulis bahwa “perhatian yang sungguh-sungguh adalah bentuk tertinggi dari doa.” Bagi Weil, doa sejati bukan permohonan, tetapi tindakan memperhatikan dengan sepenuh hati — membuka diri terhadap kehadiran ilahi dalam segala hal, terutama dalam yang rapuh, kecil, dan terabaikan. Dengannya, spiritualitas sejati bukan pelarian dari dunia, tetapi partisipasi penuh dalam penderitaan dan kenyataan, dengan sikap batin yang disebutnya attention — kesadaran murni tanpa ego (Waiting for God, 1951; Menanti Tuhan, 2010).
Dalam kalimat itu, kita menemukan makna tapa ngrame. Perhatian, atau dalam istilah Jawa eling lan waspada, menjadi inti dari laku spiritual yang membumi. Dengan perhatian, kerja bukan lagi sekadar aktivitas ekonomi, melainkan pengabdian. Mendengarkan bukan hanya sopan santun, melainkan perjumpaan batin dan diam bukan lagi pasif, melainkan ruang untuk menumbuhkan kesadaran.
Di sinilah spiritualitas menemukan bentuk barunya berupa laku kesadaran dalam aktivitas keseharian. Dengannya, manusia modern tidak harus meninggalkan hiruk-pikuk kota untuk menjadi religious. Ia hanya perlu menata cara hadirnya.
Religiositas Masa Kini
Namun, tantangan baru muncul di era digital. Di tengah kebutuhan akan keheningan, spiritualitas justru terjerat logika pasar. Filsuf sosial Shoshana Zuboff menyebut fenomena ini sebagai bagian dari surveillance capitalism. Bahwa perhatian, kesadaran, dan bahkan spiritualitas manusia telah menjadi komoditas yang dieksploitasi (The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, 2019; Era Kapitalisme Pengawasan: Pertarungan untuk Masa Depan Umat Manusia di Perbatasan Baru Kekuasaan, Marjin Kiri, 2021).
Di tengah arus “kapitalisme pengawasan” ini, pengalaman batin seperti keheningan, doa, atau kontemplasi kehilangan ruangnya karena segala sesuatu telah diukur, dipantau, dan dipasarkan. Pengalaman batin kini dikomodifikasi—dijadikan konten, produk, dan gaya hidup. Aplikasi meditasi, retret “detoks digital”, dan konten “healing” sering kali menawarkan kesunyian yang artifisial berupa spiritualitas yang dikonsumsi, bukan dijalani.
Padahal, seperti diingatkan penulis Amerika Serikat bell hooks, spiritualitas sejati adalah ethic of love—etika cinta yang menuntut kesadaran penuh akan kasih, keterhubungan antar manusia dan keterlibatan sosial, bukan sekadar kenyamanan pribadi (All About Love: New Visions, 2000; Semua tentang Cinta: Visi Baru, Marjin Kiri, 2023).
Tapa ngrame, dalam hal ini, menolak menjadikan spiritualitas sebagai citra. Ia adalah bentuk laku jujur yang mengembalikan makna kesunyian kepada tindakan, bukan performa belaka.
Untuk itu, religiositas masa kini, agar tidak tercerabut dari kehidupan, harus kembali membumi. Ia perlu bersenyawa dengan kepedulian ekologis dan sosial. Pope Francis, melalui ensiklik Laudato Si’, menegaskan bahwa spiritualitas sejati tak dapat dipisahkan dari tanggung jawab terhadap bumi dan sesama.
Dalam bingkai Nusantara, tapa ngrame berarti ikut menanggung penderitaan masyarakat tanpa kehilangan kejernihan batin. Ia adalah bentuk manunggaling kawula lan Gusti—kesatuan antara manusia dan kehidupan semesta—yang menjadikan keterlibatan sosial sebagai bagian dari perjalanan rohani. Dalam laku ini, hening tidak berarti menjauh, tetapi menghadirkan cinta di tengah hiruk-pikuk dunia yang porak-poranda.
Maka, di tengah dunia yang bising dan waktu yang terfragmentasi, tapa ngrame menghadirkan tawaran yang lembut namun revolusioner: pertapaan tanpa meninggalkan dunia. Ia mengajak manusia modern untuk menemukan Tuhan di tengah riuhnya kota, di antara tumpukan pekerjaan, di ruang rapat atau jalanan.
Dengannya, religiositas tidak lagi berbicara tentang menjauh, tetapi tentang menyucikan cara kita berada di dunia. Dalam laku tapa ngrame, hidup sehari-hari adalah altar, kesadaran adalah doa, dan kasih adalah bentuk tertinggi dari ibadah.
Mungkin, di sanalah letak spiritualitas masa kini: hening di tengah ramai, hadir di tengah sibuk, bening di tengah riuh. Tapa ngrame di zaman yang kehilangan waktu untuk diam, tapi masih menyimpan peluang untuk menjadi sadar. Sebab pada akhirnya, seperti diingatkan Merton, yang ilahi tak pernah jauh dari kita, tapi kitalah yang terlalu bising untuk mendengarnya.