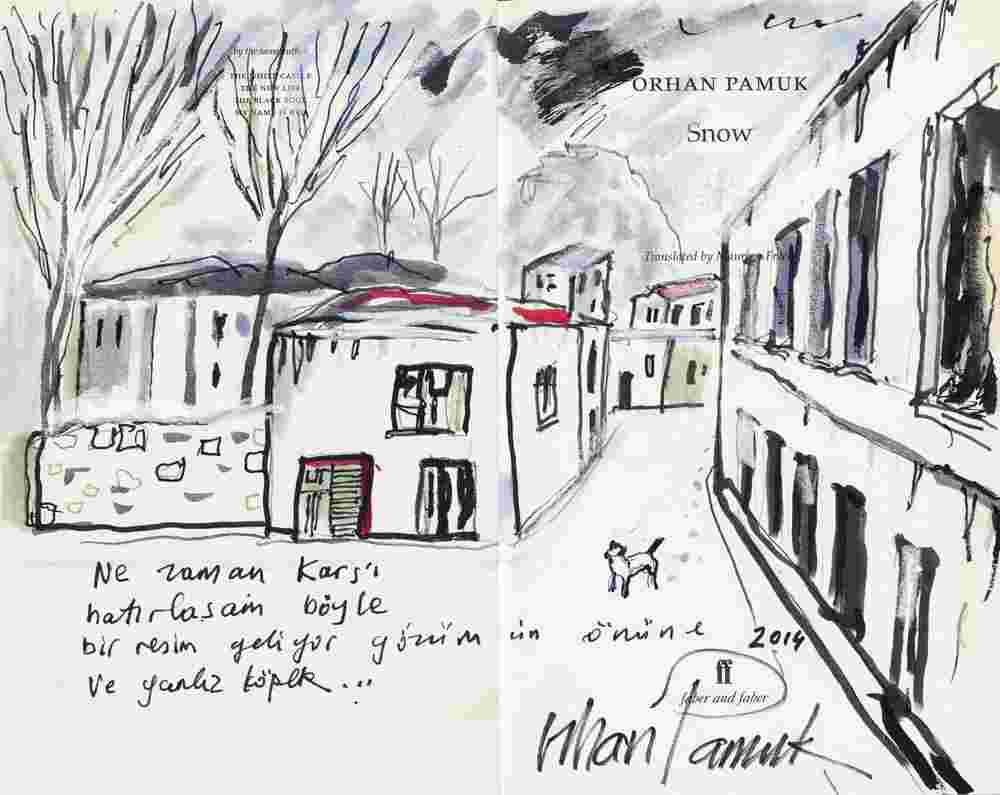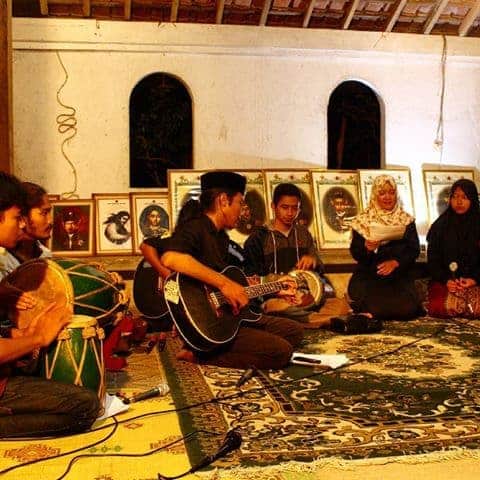Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Badudu-Zen (1994: 1284) pengertian sentimen yang berasal dari bahasa Belanda itu ada dua: 1) perasaan (perseorangan) dan 2) rasa tidak suka yang terpendam. Sedangkan rezim (1994: 1166) yang berasal dari bahasa Prancis juga bermakna dua: 1) cara pemerintahan dan 2) pemerintah(an) yang berkuasa.
Maka sentimen rezim berarti perasaan seseorang yang tidak suka kepada pemerintah yang sedang berkuasa atau tidak setuju cara pemerintah tersebut memerintah.
Akan tetapi, dalam prakteknya belakangan, pengertian ini seturut perasaan saya mengalami pergeseran. Pertama, sentimen rasa-rasanya tak hanya menyatakan tidak suka, namun juga perasaan suka. Kedua, rezim tak hanya ditujukan bagi pemerintah(an) yang sedang berkuasa, tapi juga pada pemerintahan yang sudah tidak berkuasa.
Dalam dua pengertian berdasarkan perasaan saya inilah, saya melihat banyak di antara kita, disadari atau tidak, terlibat dalam sentimen rezim. Suatu sikap yang, sekali lagi disadari atau tidak, menganggap sebuah rezim sebagai bagian dari dirinya atau kelompoknya sehingga dalam istilah sekarang ia akan gampang jadi baper saat rezim itu disebut. Pendengarannya akan lebih tajam dan suaranya akan lebih nyaring, menyangkut hal-ihwal rezim yang ia sentimeni. Sering, saking tajam dan nyaringnya pembelaan, para pihak yang terlibat dalam fenomena sentimen rezim saling menyerang.
Akibatnya, kita bukan lagi berpikir dan berdiskusi soal kebangsaan atau hal-hal yang sifatnya lebih luas, melainkan terkungkung dinding rezim yang serba terbatas. Ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang merasa disentil, namun juga bagi yang menyentil (mengkritik). Potret ini terutama dapat diamati dengan terang-benderang di media sosial.
Ambil misal, ketika pemerintah memutuskan mengimpor garam beberapa waktu lalu, berbagai status atau tagar gencar mempersoalkannya secara streotipe: Laut kita luas, kenapa harus impor garam? Komentar penangkis yang muncul biasanya juga simplisit-streotipe: Impor garam tak hanya terjadi sekarang, juga dilakukan rezim terdahulu. Selanjutnya terjadi balas-membalas komentar. Tapi intinya tetap pada upaya terlokalisirnya persoalan sebatas rezim. Pihak yang tak setuju atau menyerang menyalahkan rezim yang sedang berkuasa. Sementara pihak yang membela balik mengunduh kebijakan rezim terdahulu.
Menguatnya sentimen ini tidak terlepas dari episode Pemilu tahun 2014 lalu yang memang paling ramai dalam sejarah politik tanah air, seiring terbukanya kran berekspresi di media sosial dengan segala perangkatnya. Namun sedihnya, ini bukan hanya melibatkan masyarakat biasa terutama di dunia maya, kalangan tokoh politik dan pejabat publik pun sering bersikap demikian. Anggota DPR dari partai “non-rezim” sering terlihat baper jika apa yang dilakukan rezim dianggapnya kurang pas; sebaliknya pihak di seberang juga ngotot membela.
Apa yang sedang terjadi sebenarnya?
Yang terjadi adalah sikap kita yang berdiri di sebuah tembok rezim, baik rezim lama maupun rezim yang baru. Cinta kepada rezim mengendap di bawah alam sadar menjadikan semua kepentingan terbuhul di sana. Padahal, sebagaimana pernah dinyatakan Ariel Heryanto, pemerintah bukan negara dan negara bukan (hanya) pemerintah. Tanpa menyadari ini, persoalan kebangsaan yang lebih besar daripada urusan rezim, kerap terlupakan. Bahwa bangsa ini bolak-balik mengimpor garam, misalnya, juga kebutuhan primer lain, seharusnya kita letakkan di atas kerangka kebangsaan.
Laut kita memang luas, Tuan, akan tetapi upaya mendirikan industri garam ternyata tidak mudah. Tak hanya soal potensi, Puan, juga infrastruktur dan sumber daya manusia. Lebih dari itu, memang soal tekad dan kemauan. Kita tentu miris menyadari hal ini, dan seharusnya menjadi tugas dan cita-cita bersama untuk menegakkan kedaulatan garam.
Pemerintah, dari rezim apa pun, perlu didorong untuk memikirkannya, sekalipun kita tidak tahu pada rezim siapa swasembada ini nantinya bakal terwujud. Tapi jika kelak di kemudian hari swasembada ini tercapai, jangan pula dijadikan klaim-mengklaim: hanya pada rezim si Badu kita tidak impor garam. Atau sebaliknya: itu rezim Badu tinggal terima bersih, padahal rezim Fulan yang merintisnya dulu!
Apakah sensitivitas SARA harus digenapi menjadi Suku, Agama, Ras, dan Rezim (SARAZIM)?
Jaga Perasaan, Jaga Momentum
Apa yang saya ceritakan di atas, sering terjadi tidak hanya dalam urusan garam. Juga dalam pembangunan dan peresmian jembatan, kerjasama internasional, impor sapi, sampai ke wacana penggunaan dana haji untuk pembangunan. Seolah kerja-kerja pemerintahan bukan bagian dari kesinambungan antar rezim—atau memang demikiankah kenyataannya? Alangkah sedih kalau begitu.
Pihak yang berkuasa, tentu mesti mendengar apa pun jenis masukan yang berniat mulia. Apa yang disampaikan mesti menjadi renungan dan kemudian tekad untuk ke luar dari kerkapan persoalan yang ada. Berbagai upaya harus dilakukan, sekalipun itu baru bersifat rintisan, karena kita tahu ada banyak pekerjaan yang tak bisa selesai oleh satu-dua kekuasaan. “Kerja belum selesai, belum apa-apa,” kata ponakan Sutan Syahrir, Chairil Anwar.
Maka pihak yang berkuasa mesti memberi apresiasi secara terbuka kepada program atau proyek rintisan rezim terdahulu. Sebaliknya, para mantan juga mesti mengapresiasi apabila program atau proyeknya dilanjutkan, apalagi jika sampai berhasil sebagaimana yang dicita-citakan. Justru malah bagus. Tidak perlu jeles bagi yang lalu, dan tak perlu lebay bagi yang sekarang.
Semua kerja mesti dilihat dalam kerangka kesinambungan, (seharusnya) bukan untuk politik pencitraan. Mungkin itulah sebabnya, selain Pancasila yang betul-betul merangkum soal-soal kebangsaan di luar sekat politik, sosial dan budaya, kita membutuhkan GBHN, atau semacam kerangka acuan sebagaimana REPELITA dan PELITA yang diumumkan secara terbuka kepada rakyat banyak. Jika perlu biarkan rakyat banyak mengadakan musyawarah tentang itu, alih-alih mengambil spirit Tan Malaka via Murba.
Ancangan bersama ini penting bukan saja untuk mengikis sentimen fanatik atas sebuah rezim, melainkan menjadi standar pencapaian bangsa secara keseluruhan.
Saya membayangkan, seandainya rezim Soeharto bertugas hanya dua periode sebagaimana rezim SBY, maka konsep PELITA yang dirumuskannya akan dilanjutkan oleh rezim selanjutnya (Habibie, Gus Dur dan Megawati) sehingga akan ada penyempurnaan maupun penyegaran-penyegaran.
Namun karena rezim Soeharto mengental jadi rezim zaman yang berkuasa lama sekali sehingga seturut sebaris puisi Acep Zamzam Noor, “seperti memindahkan gunung berapi”, maka REPELITA dan PELITA hanya ajeg di satu rezim dan sulit dijadikan tolok-ukur untuk rezim yang lain.
Upaya untuk tidak baper ini, juga terkait dengan cara kita menjaga momentum. Pemerintah harus menjadikan semua niat dan pikiran baik yang datang dari segala arah sebagai tekad bersama. Sebaliknya pihak lain perlu mendukung dan mengapresiasi setiap upaya pemerintah yang berkuasa. Tentu tidak menutup kemungkinan bahwa program di suatu rezim ada yang jelek dan itu tidak perlu dilanjutkan. Upaya mengoreksinya itu pun bagian dari unsur penting kesinambungan—bukan atas nama rezim apalagi SARAZIM.