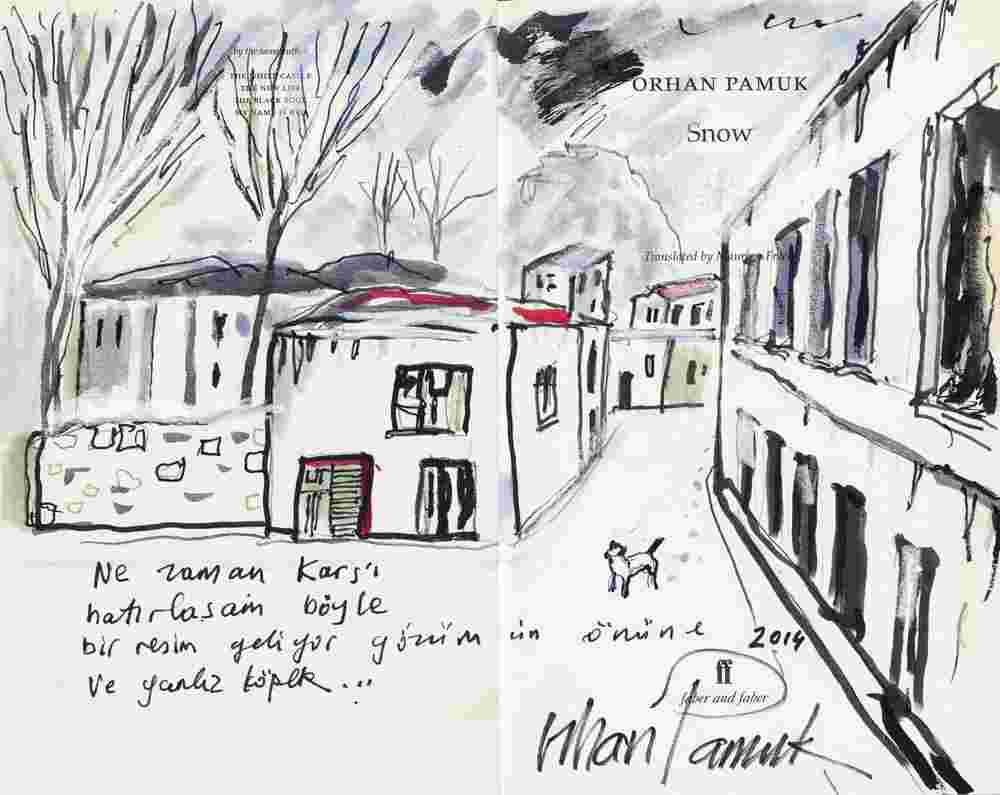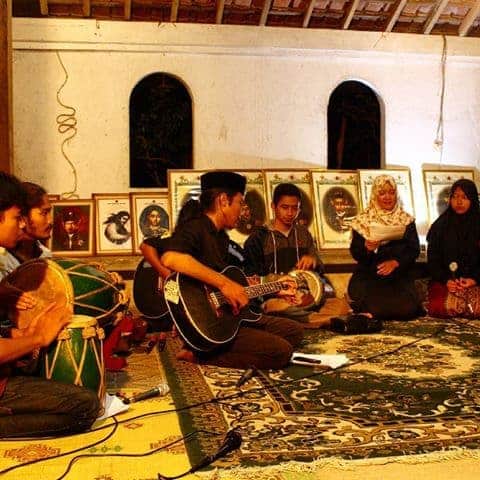Republik Pangreh Praja dan Politik Uang di Nusantara

Ong Hok Ham atau Onghokham adalah sejarawan Indonesia kelahiran Kota Pahlawan, Surabaya, tahun 1933. Ia selalu punya persfektif lain atas sejarah kita, di luar yang dipahami umum. Salah satunya terlihat dalam bukunya Dari Soal Priayi sampai Nyi Blorong (Refleksi Historis Nusantara), Penerbit Buku Kompas, 2002. Dalam pengantar buku tersebut, Dr. Asvi Warman Adam menyebut bahwa pemikiran Ong sangat reflektif dan orisinal.
Ketika banyak sejarawan melihat Proklamasi sebagai pemutus hubungan antara penjajah dan si terjajah, Ong justru melihat keterhubungan itu masih kuat. Tak hanya fisik-material, juga mental. Salah satu yang menjadi perhatiannya ialah posisi birokrasi.
Sebuah negara, kita tahu, butuh birokrasi sebagai mesin penggerak pemerintahan. Jelas, jumlah birokrat sangat banyak di semua lapisan. Presiden dan kabinet boleh muncul silih-berganti, tapi birokrat atau aparatur negara tetap dalam barisan yang rapi. Hanya pensiun, mundur, dipecat, atau ajal yang mengakhiri peran mereka di “dunia ini”.
[caption width="360" id="attachment_205648" align="alignleft"] Calon-calon Pangreh Praja berfoto di sekolah pelatihan untuk pegawai pemerintah Hindia Belanda (Foto: Koleksi Tropen Museum)[/caption]
Calon-calon Pangreh Praja berfoto di sekolah pelatihan untuk pegawai pemerintah Hindia Belanda (Foto: Koleksi Tropen Museum)[/caption]
Menurut Ong, ketika Indonesia merdeka, kita bukan saja mewarisi sejumlah produk hukum kolonial, juga barisan birokrasi yang disebut pangreh praja. Pangreh praja inilah yang bertugas menjalankan birokrasi di Hindia-Belanda. Mereka bukan orang Belanda, melainkan pribumi yang ditugaskan sebagai perpanjangan tangan kolonial. Tak heran, sikap mental mereka juga berbau kolonial. Hal yang mewarnai tradisi birokrasi kita kemudian.
Ketika kemerdekaan diproklamasikan, birokrasi bukan diisi oleh orang-orang dari unsur revolusi dan nasionalis, melainkan tetap mempertahankan unsur pangreh praja ini. Apakah kealpaan semata, atau pemimpin awal republik menyadari tak gampang menyediakan barisan birokrat yang siap pakai? Selain jumlahnya besar, melatih atau mendidiknya akan memakan waktu panjang, alih-alih menggerakkan saja mesin birokrasi yang sudah ada. Lagi pula, para pangreh praja diyakini lebih berpengalaman.
Karena itu, gempita revolusi di jalanan, tak ikut merasuk ke gedung-gedung pemerintahan. Birokrasi tak mengalami perubahan. Boleh jadi dari segi tugas, posisi dan struktur ada pergeseran, namun watak-mental tak bergeser dengan sendirinya.
Inilah yang terwariskan hingga hari ini. Mental kepegawaian cenderung tidak berubah. Tugas dan kewajiban melayani publik, sering terbalik: merekalah yang seolah minta dilayani. Gaya hidup dan pola pergaulan terkesan elitis, jauh dari interaksi sekitar. Jam kantor sering dibuat mulur-mungkret alias jam karet. Toh, gaji dan segala fasilitas tetap diterima apa pun yang terjadi. Masa tua ada jaminan pensiun dan tetek-bengek lainnya.
Bagaimana birokrasi kita membangun dirinya, bahkan dapat ditelusuri dari motivasi orang jadi pegawai negeri. Gaji tetap, fasilitas dan iming-iming pensiun, kadang menjadi motivasi dasar. Panggilan pengabdian alasan ke sekian. Karena itu, jamak kita dengar bahwa pegawai yang ditempatkan di daerah jauh atau terpencil, alamat kiamat bagi karirnya. Birokrasi jadi tak efektif. Daerah perkotaan yang fasilitasnya banyak, jadi idaman; sebaliknya daerah pinggiran dianggap tempat buangan.
Tak mudah membenahi sikap mental demikian. Di dalam kabinet kita sampai ada menteri yang khusus mengurus aparatur, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Birokrasi memang perlu ditangani khusus. Selain jumlahnya besar, mungkin terbesar di dunia, birokrasi kita juga menyerap paling banyak anggaran.
Pada era otonomi, bisa dilihat presentase APBD di propinsi atau kabupaten/kota rata-rata di atas 50 persen diserap oleh gaji dan belanja pegawai. Bahkan ada daerah yang APBD-nya 80 persen diserap oleh mesin birokrasi, sisanya yang 20 persen barulah untuk keperluan rakyat! Dalam situasi demikian, tetap saja kita dengar terjadi penyelewengan keuangan, korupsi dan kolusi, sungguh mengenaskan.
Mata Uang yang Memecah-Belah
Cara pandang lain yang unik dari Ong Hok Ham adalah tentang politik Belanda dalam memecah-belah masyarakat Nusantara. Lazim dalam pelajaran sejarah disebut bahwa taktik Belanda berupa adu-domba, pecah-belah dan kuasailah (divide et impera) lalu angkat senjata.
[caption width="360" id="attachment_205651" align="alignleft"] Ong Hok Ham, 1933-2007 (Foto: Inside Indonesia)[/caption]
Ong Hok Ham, 1933-2007 (Foto: Inside Indonesia)[/caption]
Ong berpendapat lain.
Di balik politik pecah-belah, kata Ong, ada faktor yang dominan, yakni politik uang. Secara general bisa disebut aspek ekonomi-finansial. Ong membuktikan, penguasaan kolonial atas kraton di Jawa, jarang berhadapan langsung (vis to vis) dengan senjata. Belanda tak mengeluarkan amunisi, kecuali menghadapi Sultan Agung dan Diponegoro pada abad ke-19.
Pada abad sebelumnya, VOC maupun pemerintah Hindia-Belanda, cukup menghamburkan mata uangnya. Bagaimanakah cara Belanda memakai mata uang sebagai senjata pemecah-belah? Tidak lain dengan memberi kompensasi atas raja atau keluarga sultan dalam bantuan ekonomi berbentuk uang kontan. Ini dimungkinkan ketika Belanda lewat “perjanjian lunak” berhasil menguasai tanah atau lahan perkebunan. Ketika hasil perkebunan laku di pasaran dunia (tebu di Jawa, karet di Sumatera), praktis keluarga raja tidak memiliki akses penghasilan langsung dari sana.
Lewat priayi yang dijadikan pangreh praja, keluarga raja digaji dan diberi tunjangan. Gaya dan biaya hidup yang tinggi antar kelompok priayi, menyebabkan terjadinya persaingan, rivalitas, gesekkan, dan memuncak pada konflik. Ketika konflik terjadi, Belanda menjadi pihak ketiga yang lagi-lagi siap mengucurkan uang bagi keluarga yang dianggap sejalan dengan strategi Hindia-Belanda. Dalam konteks ini, Belanda adalah “cukong terbesar” yang pernah ada di Nusantara.
Segala hal yang terjadi pada masa kolonial, ternyata masih memiliki relevansi dengan zaman kini. Secara global, sektor ekonomi-finansial sangat menentukan nasib kehidupan di planet bumi. Hal ini melibatkan mata rantai yang panjang, mulai Bank Dunia, negara donor hingga negara super power.
Apa yang disebut Bank Dunia, lebih berupa tengkulak global yang beroperasi di negara-negara miskin. Mereka bukannya menolong, tapi kerap kali menjerat negara terkait dengan hutang. Itulah sebabnya sejumlah negara ketiga belakangan menolak campur-tangan Bank Dunia dalam mengatasi kemelut ekonomi negaranya. Setali tiga uang, negara donor, yang menyebut pemberian hutangnya dengan “bantuan”, tak lebih jerat yang melenakan.
Pinjaman berjumlah besar, minus pengawasan, membuatnya rentan dikorupsi. Negara donor tahu itu, dan membiarkan. Toh, semakin tinggi penyelewengan, semakin besar kegagalan suatu program, sehingga ketergantungan atas negara donor tetap berlanjut. Persis perlakuan terhadap para kuli kontrak di perkebunan yang dilengkapi fasilitas judi dan hiburan. Tiap kali seorang buruh menerima gaji, uangnya habis buat taruhan dan bersenang-senang, lalu kembali berhutang, dan dengan cara itu mereka selamanya jadi hamba sahaya.
Selama puluhan tahun negara kita pernah menerima perlakuan semacam itu dari pihak donor. Sementara negara kuat, kerap membuat embargo ekonomi sebagai senjata untuk menundukkan negara yang memiliki visi berbeda.
Di dalam negeri sendiri persoalan keuangan ini juga sangat problematis. Berbagai bank besar, menengah dan kecil, berlomba menawarkan program bagi orang banyak, namun jeratan bunga dan segala tetek-bengek lainnya selalu menyertai. Bahkan bank yang berlabel syariah pun tak kalis dari perburuan laba. Alhasil, gagasan Hatta tentang koperasi megap-megap ditelan bumi. Atau, kita bisa meminjam narasi Ong atas keruntuhan Majapahit oleh Demak pada 1400 Saka (1478 Masehi), sebagaimana dinukilkan kembali oleh Asvi Warman Adam, candrasangkala: sirna ilang kerta ning bumi, hilangnya kejayaan dunia—karena hutang dan bunga uang (xi: 2000).
Menoleh Boleh, Berbalik Jangan
[blockquote align="none" author="Ong Hok Ham"]”Keuangan yang akhirnya dapat membeli kekuasaan dari masyarakat yang katanya nonmaterialis.”[/blockquote]
Apakah kita akan menyalahkan kolonial yang mewarisi sikap mental pangreh praja dan politik uang? Terlalu naif jika kita balik ke belakang. Sebagian besar penyakit birokrasi yang ada sekarang, disebabkan oleh kita sendiri yang tidak segera mengubah diri. Soal seleksi penerimaan pegawai dan pengawasan, misalnya, pemerintah kolonial lebih selektif dan ketat, ketimbang kita yang hidup dalam kultur nepotisme. Memang sebagian dari pangreh praja pada zaman kolonial terdiri dari priayi atau penguasa lokal, namun mereka tak bisa leluasa membawa “gerbong” keluarganya untuk ikut jadi aparatus kolonial.
Kemudian selama puluhan tahun, disadari atau tidak, pendidikan mengarahkan subjek didik jadi barisan pangreh praja. Pandangan sosial masyarakat juga menganggap jadi pegawai negeri ukuran keberhasilan orang sekolahan. Didukung sikap kolusi dan nepotisme, jadilah birokrasi sebagai muara yang menampung hasrat orang jadi birokrat. Akibatnya, jumlah pangreh praja membengkak dan tambun, geraknya lamban bak kura-kura tua yang rabun.
Hal paling menyedihkan, mata uang masuk ke dunia politik yang dikenal sebagai politik uang (money politic). Pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan lurah, kerap diwarnai tindak-tanduk ini, sehingga mereka yang punya banyak uang kerap menang. Suara rakyat suara Tuhan pun perlu dipertanyakan. Masyarakat kita tiba-tiba menjadi amat permisif dengan kebendaan. Padahal dalam ajaran adiluhung digambarkan kita adalah masyarakat yang memiliki refleksi kuat atas makna bendawi. Atau jangan-jangan anggapan warisan itu tidak sepenuhnya benar. Terbukti, keberhasilan VOC dan Hindia-Belanda menyebar mata uang dalam menguasai Nusantara, mengisyaratkan bahwa ketakjuban pada kilau piis (uang) sudah ada sejak dulu kala.
Bahkan Ong sampai pada sebuah kalimat sarkas,”Keuangan yang akhirnya dapat membeli kekuasaan dari masyarakat yang katanya nonmaterialis.” Ironis!
Apakah penyakit-penyakit akut birokrasi cum politik kita sudah tandas sejak Reformasi? Sulit menjawabnya, atau sebaliknya, jawaban mudah didapat. Hanya saja kita boleh melihat ke belakang, belajar banyak dari sana, tapi tidak untuk kembali berjalan mundur. Karena itu pembenahan terus diupayakan, berbagai regulasi, undang-undang, apresiasi dan pengawasan terus ditingkatkan. Dalam banyak hal, ada pencapaian. Tapi harapan terbesar tetap kita tujukan kepada sikap mental, sesuatu yang akan membedakan Republik Pangreh Praja bermental uang dengan Republik Indonesia Raya yang me-Revolusi Mental!