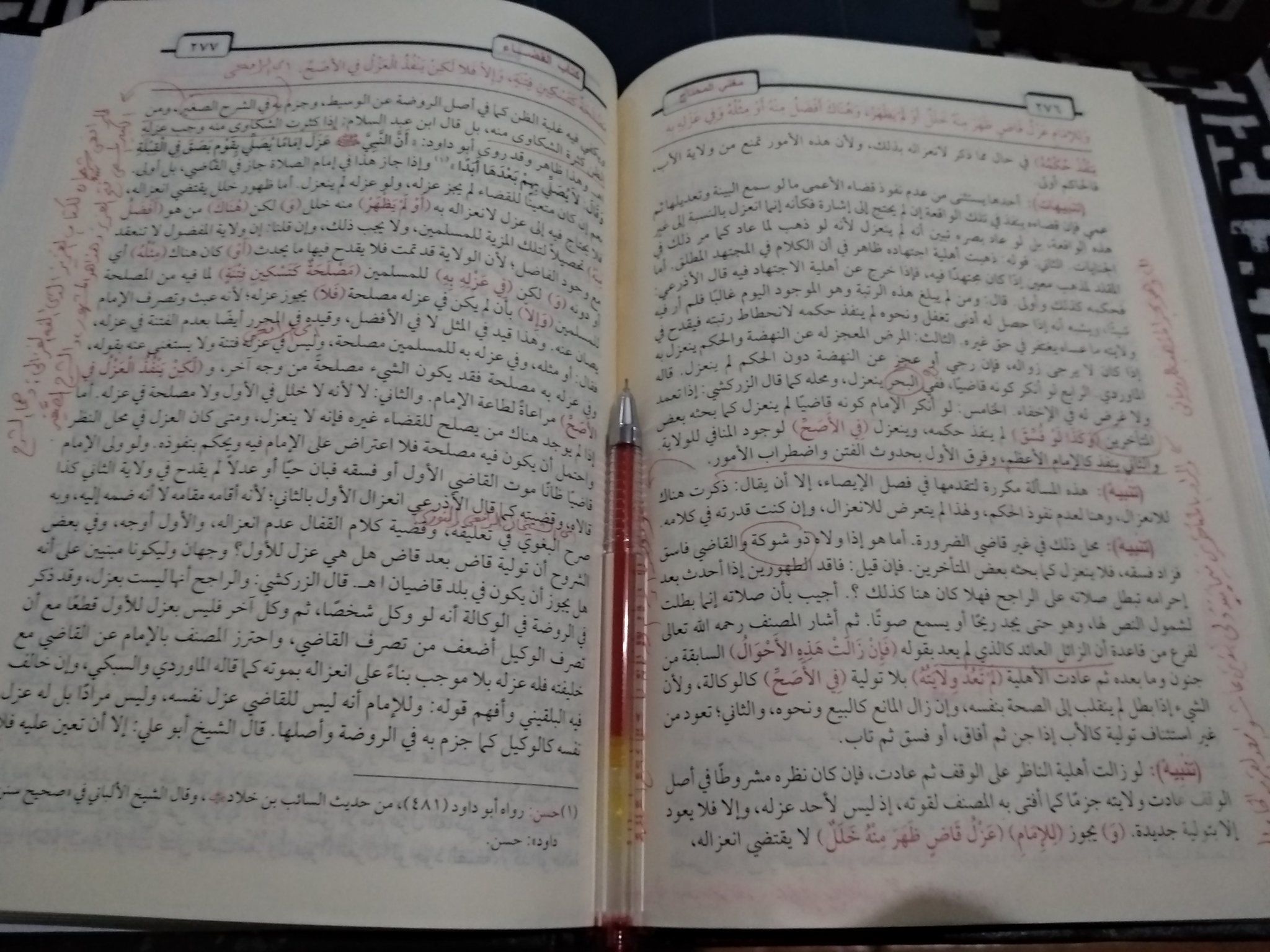Di tengah lorong panjang perdamaian Israel-Palestina, perdebatan konsep kedaulatan antar kedua negara masih belum menemukan terang cahaya. Konsep kesepakatan damai, yang berbasis ‘two-state solitution’ maupun ‘one-state solution’, masih belum menemukan bentuk final. Kontestasi antar pemimpin di level politik internasional mengindikasikan perdebatan ini.
Setelah bertemu dengan Benjamin Netanyahu pada Rabu, pertengahan September 2018, Donald Trump mengungkapkan dukungannya terhadap ide solusi dua negara (two-state solution). “I like (the) two-state solution. It is a dream of mine to be able to get that done prior to the end of my first team [Saya suka solusi dua negara. Itu merupakan mimpi saya untuk dikerjakan, menjadi penting pada masa akhir tim pertama—kepemimpinan—saya],” ungkap Trump, sebagaimana dilansir BBC (26 September 2018).
Bagaimana konsep ‘two state solution’? Hal ini merupakan konsep dalam strategi perdamaian Israel-Palestina yang telah lama digaungkan oleh beberapa aktifis perdamaian dan pemimpin politik untuk mengakhiri konflik. Konsep two state solution memungkinkan warga Israel dan Palestina dapat hidup bersama, seraya membagi kawasan Gaza, Tepi Barat (West Bank) dan Jerusalem sebagai ruang komunal untuk hidup bersama.
Konsep perdamaian dengan menggunakan two-state solution, mengimajinasikan warga Israel dan Palestina dapat membaur dalam tiga kawasan yang selama ini menjadi titik konflik maupun perdebatan. Kawasan Gaza selama ini menjadi titik perjuangan kaum muslim Palestina untuk mendapatkan hak-nya di hadapan pemerintah Israel. Sementara Tepi Barat merupakan kawasan hunian antara orang-orang Yahudi Israel dan Muslim Arab-Palestina. Jerusalem, sebagai kota suci yang diperebutkan selama berabad-abad, antara penguasa Yahudi, Nasrani dan Muslim.
Dengan mengandaikan ‘two-state solution’ sebagai alternatif di tengah kebuntuan resolusi perdamaian, warga Israel dan Palestina dapat menikmati ruang bersama, khususnya di kawasan Jerusalem yang menjadi rujukan ibadah pemeluk tiga agama. Jerusalem menjadi titik panas dalam diplomasi internasional, setelah Presiden Donald Trump menggeser Kantor Kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke kota ini. Trump juga mengisyarakatkan dukungan bahwa Jerusalem sebagai kota Israel, kota penting warga Yahudi.
Namun, ungkapan Trump terkait two-state solution pada akhir 2018 lalu, berbeda dengan sikapnya di tahun 2017. Publik internasional mengingat bagaimana pernyataan Trump setelah menjamu Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, pada Februari 2017. “I’m looking at two-states and one state,” jelas Trump. “I’m very happy with the one that both parties like. I can live with either one”. Pernyataan Trump jelas ungkapan diplomatis. Ia ingin mencari celah agar Amerika Serikat dapat menjadi penentu dalam dinamika konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan.
Saling klaim kawasan
Perdebatan tentang konsep kedaulatan Israel-Palestina tidak bisa lepas dari saling klaim kawasan yang berlangsung sepanjang sejarah. Kedua pihak merujuk pada teks-teks klasik untuk saling mengklaim wilayah masing-masing. Tentu saja, saling klaim ini tidak menyelesaikan masalah, hanya menambah runcing konflik antara kedua negara ini. Dari konflik wilayah kenegaraan, kemudian sering bergeser menjadi konflik agama: Yahudi dan Islam. Padahal, sebelumnya konflik bermula pada ruang saling klaim kawasan. Keruntuhan Turki Utsmani (Ottoman) menjadi awal mula perpecahan negara-negara Arab, selain bangkitnya nasionalisme di kawasan ini.
Pada tahun 1921, TransJordan (sekarang disebut Yordania) secara resmi terpisah dari kawasan Palestina (sekarang kawasan Israel dan Gaza). Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) pada 1947 mengajukan kesepakatan pembagian wilayah antara Yordania dan kawasan Israel-Palestina, yang dipisahkan oleh sungai Jordan.
Dua kawasan ini, yakni satu wilayah disebut sebagai sebuah negara yang mana Yahudi Zionis menjadi mayoritas. Sementara, satu kawasan lain dihuni oleh Arab Palestina yang menjadi mayoritas. Namun, proposal yang diajukan oleh UN ini ditolak oleh beberapa kelompok. Mereka tidak setuju dengan pembagian kawasan, yang memisahkan orang-orang Yahudi Israel dan Arab-Palestina.
Pada 1948, berlangsung perang antara Israel dan Arab-Palestina. Perang ini merupakan kelanjutan dari kebuntuan gagasan perdamaian, atas saling klaim wilayah. Selang beberapa waktu, Jordania mengokupasi kawasan Tepi Barat (West Bank). Sementara, Mesir menguasai Gaza. Kecamuk perang membakar kawasan Palestina.
Konflik berlangsung lama. Pada perang enam hari pada 1967, militer Israel memukul mundur tentara Jordania di kawasan Tepi Barat. Sementara, Mesir juga didorong melepaskan kawasan Gaza. Perang enam hari pada 1967 ini mengubah lanskap politik internasional terkait dengan konflik Israel-Palestina. Posisi Israel menjadi kuat dengan barisan militer yang didukung aliansinya, sementara lobi diplomatik di antara negara-negara internasional juga di atas angin. Negara-negara Arab terpuruk, terpukul mundur, tercerai berai dalam konflik politik berkepanjangan ini.
Colin Shindler, profesor emeritus dari School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London, melacak bagaimana dinamika dan tarik ulur kesepakatan antara pemimpin Israel-Palestina-Yordania, belum sepenuhnya selesai hingga sekarang. Shindler menulis esai ‘Israel and Palestinians: What are alternatives to a two-state solution?’. Dalam esai ini, Shindler mengulas bagaimana alur ‘two-state solution’, ‘one-state solution’, hingga ‘three-state confederation’ (konfederasi tiga negara).
Pemimpin Palestina, Yaser Arafat, mengkampanyekan konsep two-state solution sejak tahun 1974. Ia menggemakan otoritas Palestina atas kawasan Tepi Barat dan Gaza, mengikuti Perjanjian Oslo pada 1993. Sementara, Perdana Menteri Israel, mulai dari Ehud Barak, Ariel Sharon, Ehud Olmert dan terakhir Benjamin Netanyahu—menerima konsep Palestina sebagai sebuah negara. Akan tetapi keempat Perdana Menteri itu berbeda pandangan dalam penafsiran atas konsep ‘state’ sekaligus kewenangan, kawasan, serta kedaulatan yang melingkupinya.
Sementara, gagasan ‘one state solution’ mengandaikan bahwa kawasan Gaza, Jerusalem dan Tepi Barat yang selama ini diperdebatkan, menjadi wilayah resmi Israel. Orang-orang Arab-Palestina diperbolehkan menempati kawasan ini, namun tidak memiliki hak suara dalam politik elektoral. Konsep ‘one state solution’ juga didasarkan anggapan bahwa 400.000 orang Yahudi yang menghuni Tepi Barat tidak memungkinkan untuk dipindah secara paksa atau secara sukarela meninggalkan kawasan ini.
Sedangkan, tawaran ‘three-state confederation’ telah menjadi perdebatan sejak tahun 1948. Konsep yang terakhir ini tidak banyak menjadi alternatif perbincangan secara luas di antara pemimpin politik dan pejuang kemanusiaan di level internasional.
Colin Shindler juga meninjau konsep alternatif dari mantan Perdana Menteri Israel, Menachem Begin. Pada 1977, Menachem Begin mengajukan tawaran konsep otonomi administratif untuk menyudahi perdebatan dan konflik Israel-Palestina. Konsepnya, warga Palestina punya aturan khusus terkait wilayahnya. Namun, Israel berwenang atas keamanan dan kebijakan luar negeri, sementara secara ideologis warga Palestina dipersilahkan mempertahankan klaimnya atas Samaria (Tepi Barat). Tentu saja, konsep ini menjadi perdebatan yang meluas meskipun tidak banyak dukungan atas konsep ini.
Jalan panjang untuk menginisiasi perdamaian Israel-Palestina terlihat belum menemukan ujung. Konsep two-state solution masih menjadi perdebatan di antara pejuang kemanusiaan, pengasa politik Israel-Palestina, hingga antar pemimpin lintas negara. Presiden Joko Widodo berulang kali mendukung konsep ‘two-state solution’ untuk perdamaian Israel-Palestina. Meski, dalam beberapa kesempatan, terlihat bagaimana Presiden Jokowi main aman dengan mendukung Palestina sebagai negara merdeka, untuk membungkam kritik dari kelompok Islamis di Indonesia.
Perdamaian Israel-Palestina menunggu gebrakan dalam diplomasi kemanusiaan di level internasional. Indonesia punya peluang untuk menjadi penengah di tengah perdebatan konsep perdamaian yang tak kunjung tuntas ini. Bagaimana strategi diplomasi Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya? Waktu dan sejarah yang akan menjawabnya. (RM)