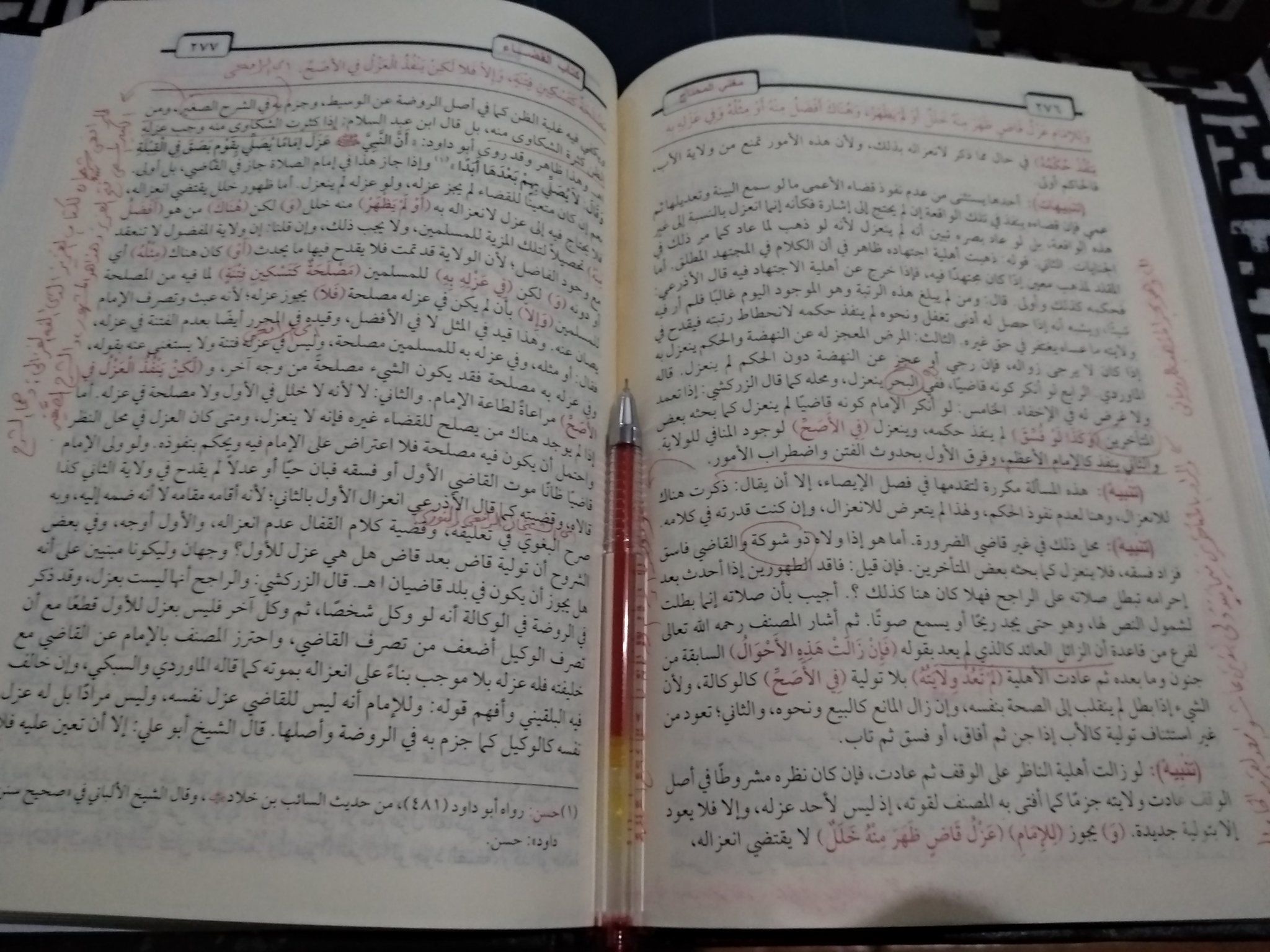Salah satu diskursus keagamaan yang paling hangat pada awal abad 20 adalah menguatnya gerakan purifikasi keagamaan dalam Islam yang diinisiasi kalangan Wahabi. Ajaran Wahabi yang menentang mazhab mendapat perlawanan sengit dari kalangan pesantren yang kuat sekali menganut sistem bermazhab dalam beragama: Ahlussunnah wal Jama’ah.
Ketegangan di antara kelompok yang menganut mazhab (mutahadibin) dengan anasir yang anti-mazhab tersebut terjadi di berbagai antero Nusantara, tak terkecuali di Banyuwangi, daerah yang berada di ujung timur pulau Jawa tersebut. Di tempat ini, kalangan pesantren menjadi garda terdepan untuk menghalau datangnya paham Wahabi dan anti mazhab lainnya yang mulai masuk seiring industrialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial masa itu.
Salah satu peristiwa pertentangan antara dua kelompok tersebut, yang tercatat sejarah adalah penolakan terhadap masuknya Muhammadiyah di Banyuwangi. Saat itu, organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan itu, oleh sejumlah kiai diidentikkan dengan gerakan Wahabi, karena adanya kesamaan anti mazhab.
Sutrisno Kutoyo dalam buku Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Persyarikatan Muhammadiyah (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), menceritakan perihal ancaman yang diterima oleh KH. Ahmad Dahlan. Tersiar kabar, pendiri Muhammadiyah itu akan hadir ke Banyuwangi untuk mengisi rapat umum guna mendirikan Cabang Muhammadiyah di Banyuwangi. Mendengar hal ini, kelompok masyarakat yang menganut Aswaja merasa risih. Lantas mengirimkan surat ancaman kepada KH. Ahmad Dahlan untuk membatalkan kedatangannya ke Banyuwangi.
Namun, surat ancaman tersebut tidak menyurutkan langkah KH. Ahmad Dahlan. Setibanya di Banyuwangi, tepatnya di stasiun lama Banyuwangi (Karangrejo), Kiai Ahmad Dahlan mendapatkan perlindungan ketat dari polisi Belanda karena pada saat itu, kerumunan massa telah datang untuk menolak kehadiran Kiai Dahlan. Meski demikian, Kiai Dahlan tetap melanjutkan agendanya untuk mengisi rapat umum pendirian Cabang Muhammadiyah. Kejadian yang berlangsung pada Januari 1922 itu pun diakhiri dengan lemparan batu ke atap rumah yang dijadikan lokasi rapat umum tersebut.
Munculnya gerakan-gerakan Wahabi tersebut, memantik Kiai Saleh Syamsudin dari Lateng Banyuwangi untuk melakukan berbagai tindak pencegahan. Salah seorang kiai yang turut mendeklarasikan berdirinya Nahdlatul Ulama itu, banyak melakukan kajian terhadap pemikiran kaum anti mazhab tersebut langsung dari berbagai kitab yang menjadi rujukan para ulama penganut paham Wahabi.
Di dalam perpustakaan kitab peninggalan Kiai Saleh Lateng banyak ditemukan kitab-kitab yang disusun oleh ulama Wahabi. Di antaranya adalah kitab karya Ibnu Taimiyah berjudul Al-Minhajul Sunnah an-Nabawiyah, Ghoyatul Iman karya Syekh Abi Ma’ali as-Syafi’i as-Salami dan Zaddul Ma’ad karya Ibnu Qoyim. Menariknya, di kitab-kitab tersebut ditulisi sebuah peringatan di halaman awal kitab.
“Ati-ati kitab ini kitab orang Wahabi. Iling-iling jangan gampang nuruti.” (Hati-hati, ini kitab [karangan] orang Wahabi. Ingat-ingatlah, jangan mudah terpengaruh).
Tidak cukup dengan membaca literatur sendiri, Kiai Saleh dengan kaukus ulama Banyuwangi dan dari Jawa Timur lainnya, juga mendasarkan berbagai argumentasinya dengan berdasarkan pada fatwa Mufti di Mekkah. Hal ini sebagaimana terungkap dalam kitab al-Ajwibah al-Makkiyah ala al-As’ilah al-Jawwiyah.
Kitab yang berupa fatwa-fatwa dari Qadliul Qudhat dan Mufti Wilayah Hijaz, Syaikh Abdullah bin Abdul Raman Siraj (w. 1949). Kitab yang ditulis pada 1340 H (1922 M) itu, merupakan jawaban atas pertanyaan yang dikirim dari Jawa. Sebagaimana dalam kata pengantarnya, sang mufti menulis demikian:
“telah datang kepadaku sepucuk surat dari salah satu kota Negeri Jawi, yang ditandatangani oleh beberapa ulama negeri itu (yaitu) al-Mukaram Syaikh Zubair bin Abdul Qudus, al-Haj Abdul Rahim Giri, al-Haj Muhammad Shiddiq Jember, al-Mukaram Muhammad Syamsudin Banyuwangi (Kiai Saleh Lateng), al-Haj Abdul Aziz Banyuwangi, al-Haj Ahmad Banyuwangi, al-Mukaram Abu Dzar, al-Mukaram Ahmad Sanusi, al-Mukaram Muhammad Ma’ruf Kediri,”
Pertanyaan yang dikirim dari Jawa tersebut, tak jauh dari seputar permasalahan khilafiyah yang kerap menjadi ajang perdebatan antara kalangan santri dengan para penganut Wahabi. Setidaknya ada empat soal yang diajukan. Meliputi (1) masalah jihad dan taqlid, (2) hukum bertawasul dengan perantara para Nabi dan orang-orang sholih, (3) hukum merayakan maulid Nabi Muhammad, dan (4) hukum ziarah kubur.
Selain itu, Kiai Saleh juga menjalin korespodensi dengan para ulama Nusantara yang ada di Mekkah untuk mempertanyakan persoalan-persoalan yang masih seputar isu khilafiyah tersebut. Satu diantaranya adalah surat balasan dari Kiai Asnawi Kudus. Dalam salah satu surat yang dikirim oleh Kiai Asnawi dari Mekkah adalah tentang pembahasan Manaqib Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Dalam surat yang ditemukan di perpustakaan Kiai Saleh tersebut, Kiai Asnawi menjelaskan tentang ungkapan-ungkapan syatahat yang banyak disalahpahami sebagai ungkapan yang menyekutukan Allah, sehingga ada kalangan yang melarang pelaksanaan manaqib.
Peranan Kiai Saleh tidak hanya sebatas itu. Untuk menangkal faham Wahabi, ia pun turut membidani organisasi Al-Khairiyah yang menjadi vis a vis dari Al-Irsyad yang menyerupai pemahaman Wahabi. Meski bukan keturunan bangsa Arab, namun pada sejarahnya, Al-Khairiyah membuka kesempatan bagi umat Islam lainnya. Terlebih yang memiliki pemahaman keagamaan yang sama.
Salah satu kegiatan Al-Khairiyah adalah melakukan pengajian umum (open baar) di Masjid Jami Banyuwangi. Dimana pengajian tersebut, diberi nama Nahdlatul Islamiyah. Dalam pertemuan yang kelak menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama Cabang Banyuwangi ini, sarat dengan bahasan-bahasan soal khilafiyah atau furuiyah.
Dalam Soera Nahdlatoel Oelama edisi ketujuh tahun ke-2, Rajab 1348 H, pernah memuat salah satu pertemuan dari Nahdlatul Islamiyah tersebut. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan orang dengan berbagai latar belakang etnisnya. Baik Arab, Madura maupun Melayu. Bahkan, tidak hanya diikuti masyarakat Banyuwangi, tapi juga orang-orang dari Bali.
Dalam kegiatan yang digelar pada Rabu, 16 Januari 1930 itu, mendatangkan tiga ulama dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yakni, KH. Wahab Chasbullah, KH. Bisri Syansuri, dan KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz. Ketiga ulama tersebut, mengupas empat permasalahan yang erat kaitannya dengan persoalan khilafiyah.
Permasalahan pertama, hukum berdiri ketika membaca sholawat berzanji (marhabanan). Lalu, soal tentang tawasul kepada Nabi Muhammad, menalqin mayat setelah dikubur dan terakhir, adalah hukum membaca Surat Yasin sebanyak tiga kali pada pertengahan bulan Syaban (nisfu sya’ban). Keempat pertanyaan tersebut, dijawab bergantian oleh ketiga ulama tersebut dengan perspektif Syafi’iyah dan Ahlussunnah wal jama’ah.
Apa yang dilakukan oleh Kiai Saleh dan sejumlah tokoh Ahlussunnah wal Jamaah di Banyuwangi itu, cukup berhasil. Persebaran ajaran Wahabi ataupun organisasi yang memiliki kemiripan prinsip anti-madzhab tak dapat berkembang pesat. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh penulis Belanda pada 1926, Dr. Y.W. de Stoppelaar dalam bukunya Blambangansch Adatrecht: “ tak ada yang selera dengan aliran Wahabi.” Hingga saat ini pun, gerakan wahabisme di Banyuwangi tak dapat berkembang dengan maksimal.