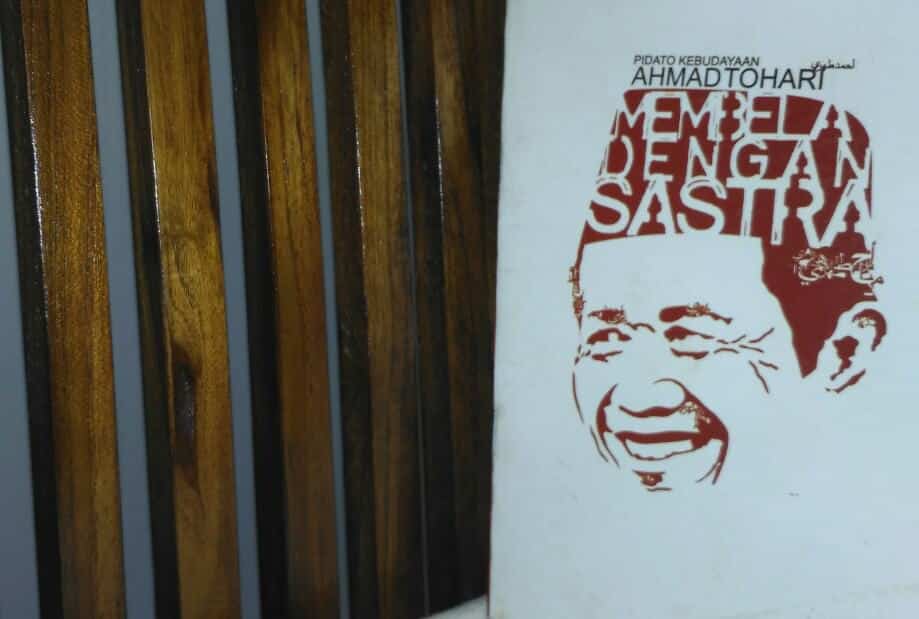Pemaknaan peristiwa sastra turut ditentukan oleh peristiwa-peristiwa terdahulu. Di Pesantren Tebuireng, Jombang, 2-4 Desember 2022, Lesbumi Jawa Timur mengadakan simposium “sastra pesantren”. konon, peristiwa itu sudah diawali dengan seminar bertema “sastra pesantren” di Surabaya. Peristiwa-
peristiwa itu teringat untuk menantikan ada peristiwa-peristiwa baru sebagai
“sambungan” atau “patahan”.
Konon, pemaknaan peristiwa-peristiwa itu terjadi di media sosial dengan debat segala arah. Pemaknaan pun terjadi di warung kopi atau serambi rumah bagi orang-orang masih berpikiran “sastra pesantren”. Pemaknaan dengan kata-kata disaingi keramaian mengunggah foto-foto (sendiri atau bersama) selama mengikuti seminar dan simposium. Pada abad XXI, peristiwa sastra di Indonesia
terbukti menghasilkan ribuan foto tapi tak ada janji menghasilkan ratusan tulisan.
Pada 22 Oktober 2022, Balai Bahasa (Jawa Tengah) mengadakan acara pemberian penghargaan Prasidatama di UIN Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Di ruangan, sosok santun itu duduk menikmati pidato dan pentas seni. Penampilan sederhana untuk pengarang besar di Indonesia. Ia memilih bertopi, bukan
berpeci. Sosok bernama Ahmad Tohari. Di acara, ia menjadi tamu istimewa untuk
membenarkan bobot acara berurusan bahasa dan sastra. Acara selesai dengan
lelah dan hujan, sosok itu disibukkan oleh para pengarang minta foto bersama.
Sekian menit atau jam, foto para pengarang dan Ahmad Tohari beredar di media sosial. Peristiwa sastra memang menerbitkan ratusan foto dengan keterangan-keterangan pendek. Foto-foto belum mengajak orang-orang bermain
ingatan atau memberi tanggapan berupa tulisan 1-5 halaman. Orang-orang mengerti bila Ahmad Tohari itu pengarang tenar. Ia bakal selalu teringat dengan Ronggeng Dukuh Paruk. Pengenalan dicukupkan singkat, tak ada bujukan-bujukan untuk terus membicarakan sosok mengikuti beragam tema.
Di Pesantren Tebuireng, Jombang, Ahmad Tohari tak ada di ruangan simposium. Sekian pembicara menghadirkan sebagai nama dan novel. Penjelasan agak panjang tapi disisipi keraguan untuk menaruh novel-novel
gubahan Ahmad Tohari dalam arus “sastra pesantren” atau turut dalam selera
dicap “sastra pesantren”. Pada 2022, Ahmad Tohari masih mendapat perhatian
tanpa ada tuntutan agar muncul “suara” atau “tulisan” menanggapi “sastra pesantren. Di Purwokerto, Ahmad Tohari sempat berbisik tentang usia. Kita diminta mengaitkan usia dan sastra. Ia mengaku tak lagi menulis (cerita pendek atau novel). Kita justru mau repot untuk menghubungkan persembahan sastra
dari Ahmad Tohari dan “sastra pesantren”.
Di buku berjudul Sastra dan Budaya Islam Nusantara (1998), kita menemukan esai buatan Ahmad Tohari berjudul “Sastra Pesantren, Sastra Dakwah”. Semula, tulisan disampaikan dalam seminar nasional di IAIN Sunan
Kalijaga, 1997. Tulisan hadir dalam peristiwa sastra.
Ia mengawali dengan paragraf tanpa kepastian: “‘Sastra pesantren’ adalah
istilah baru yang mungkin dimaksudkan untuk menyebut karya sastra yang hidup
dan diciptakan oleh kalangan pesantren, atau karya sastra yang bermuatan misi
dakwah. apabila pembatasan ini benar, maka sastra pesantren sesungguhnya sudah hadir sejak masuknya Islam di Indonesia sekitar abad ke-12, sekaligus merupakan bagian tak terpisahkan dari sastra Indonesia.” Penelusuran terlalu jauh untuk “memastikan” sastra (di) pesantren. Sejarah sastra (di) Indonesia
dianjurkan menaruh babak terlama melatari kemunculan “sastra pesantren”.
Di buku-buku sejarah sastra Indonesia diajarkan di sekolah dan perguruan
tinggi, kita tak menemukan ada masa atau masalah “sastra pesantren”. Kita
mungkin belum ada kemauan memikirkan “sastra pesantren” saat membuka
buku-buku susunan A Teeuw, Ajip Rosidi, atau Bakri Siregar. Godaan-godaan mungkin bermunculan dengan tulisan-tulisan dibuat Goenawan Mohamad, Abdul Hadi WM, Kuntowijoyo, Jamal D Rahman, dan lain-lain. Jarak waktu dalam penghadiran masalah “sastra pesantren” menentukan “ragu” dan “pasti” dalam pemberian penjelasan dan pembuktian.
Ahmad Tohari memberi keterangan mengikuti arus zaman: “Apabila kehidupan sastra dalam batas tembok pesantren bisa dikatakan redup, tidaklah
berarti ‘sastra pesantren’ juga tidak berkembang di luarnya. Dalam hal ini agaknya
telah terjadi semacam metamorfosis dari sastra pesantren lama yang biasanya
berciri tradisional ke bentuk sastra pesantren modern dengan segala ciri
modernitasnya.” Keberanian untuk memasalahkan pengarang, tempat, tema, dan
bentuk. Usaha menjelang pengakuan bahwa ada perwujudan “sastra pesantren”
di Indonesia abad XX.
Pengamatan dilakukan menghasilkan pendapat: “sastra pesantren”
bergerak cepat dengan puisi, bukan novel. Kita membaca pendapat itu dikaitkan
latar perkembangan sastra masa 1980-an dan 1990-an. Ahmad Tohari
berharapan di puisi tapi (agak) pesimis di novel. Kita mungkin meragu dengan
model pengamatan dan kelengkapan catatan dibuat Ahmad Tohari.
Paragraf dibuat Ahmad Tohari sebelum novel-novel ditulis orang pernah di
pesantren atau mengenai pesantren laris di pasar buku: “Sementara orang
mengatakan, sastra bentuk novel memang akan sulit lahir dari kalangan
pesantren (baca: ortodoksi muslim), setidaknya karena suatu hal, yakni masih
adanya anggapan bahwa membuat karakter (pelaku) fiksi dihukum haram karena
dianggap sama dengan membuat patung. Kenyataannya memang demikian,
tidaklah banyak lahir novelis atau cerpenis dari kalangan ortodoksi, baik ortodoksi
modern maupun ortodoksi tradisional. Novelis atau cerpenis Islam kebanyakan
muncul dari kalangan abangan.”
Paragraf wajib diperdebatkan dengan melihat situasi sastra setelah
keruntuhan rezim Orde Baru (1998). Pendapat itu bisa diralat atau menghasilkan
polemik-polemik memastikan terjadi perubahan besar atau berlangsung
pembuatan arus sastra berselera pesantren. Puluhan pengarang hadir dengan
cap pesantren. Novel-novel terbit dan laris. Novel pun bergerak untuk dijadikan
sebagai film. Di jarak waktu tak lama, pendapat-pendapat Ahmad Tohari
mendapat “jawaban-jawaban” mengejutkan dari pengarang-pengarang novel
pernah tinggal di pesantren atau fasih mengisahkan pesantren.
Pada 2003, Ahmad Tohari menulis esai biografis berjudul “Tanpa Diciptakan, Saya Jadi Pengarang”. Tulisan penting bagi pembaca novel-novel gubahan Ahmad Tohari. Tulisan terlambat datang tapi penting dibaca (ulang) untuk mengaitkan dengan tulisan mengenai “sastra pesantren”.
Kita sulit menemukan diksi dan situasi kepesantrenan dalam tulisan Ahmad
Tohari, sekian tahun setelah ikut dalam seminar di IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 1997. Kita cukup diingatkan babak sebagai bocah masa 1950-an:
“Selain dari sekolah, di rumah ada koran. Ini luar biasa karena pada tahun 1955
ayah saya seorang pegawai Kantor Urusan Agama sudah berlangganan koran
lewat pos. Koran tersebut tiba di rumah setelah satu minggu dari tanggal terbit.
Selain koran dan majalah serta primbon dalam bahasa Jawa, di rumah juga banyak kitab dalam bahasa Arab maupun Jawi dalam tulisan pegon.” Kita menduga ia berkenalan dengan kitab-kitab, membaca tapi tak mengalahkan
keseruan membaca novel-novel gubahan pengarang Indonesia atau novel-novel edisi terjemahan dari pengarang-pengarang dunia.
Ahmad Tohari rajin menulis novel-novel. Ia mengaku itu ungkapan religius dan keberpihakan untuk kaum bawah, pinggiran, atau lemah. Pada masa 1980-an, ia mendapat kritik dari Gus Dur. Kritik agak menimbulkan marah. Sekian tahun berlalu, Ahmad Tohari sadar tentang kritik itu “pedoman” untuk terus bersastra.
Kritik tak berkaitan dengan “sastra” dan “pesantren” pernah diungkapkan Gus Dur
(1973). Kita membaca (lagi) tulisan biografis Ahmad Tohari cuma bertemu masalah
religius, bukan penggamblangan sastra cap pesantren atau “sastra pesantren”.
Ahmad Tohari mengaku: “Seperti halnya Ronggeng Dukuh Paruk, hampir semua
karya saya terilhami oleh pengalaman nyata, hasil pembacaan lahir-batin atas lingkungan yang kemudian diperkaya dengan idealisme dan komitmen kemanusiaan. Maka semua karya saya sederhana, amat membumi dan karena komitmen kemanusiaan maka semuanya punya keberpihakan. Masyarakat di
mana saya hadir di dalamnya dan ikut bernapas adalah objek penulisan yang
tiada habisnya bagi saya. Entahlah, yang jelas ‘religiositas’ pribadi selalumembawa saya ke arah mereka ketika niat menulis mulai muncul di hati.”
Novel-novel gubahan Ahmad Tohari biasa mendapat penghargaan dan cetak ulang. Novel-novel menjadi sumber pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi. Sekian tahun berlalu, sekian novel perlahan ditaruh dalam urusan “sastra
pesantren”. Kita menduga ada kaitan-kaitan biografis, seminar (1997), dan perkembangan sastra mutakhir.